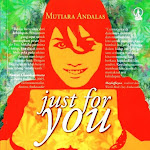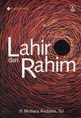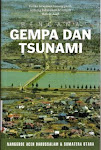EKOTEOLOGI:
Menebus Tubuh Tuhan dari Holocaust
Oleh Mutiara Andalas[1]
Kehidupan ekologi sedang berarak menuju kematian dini. Holocaust barangkali merupakan kata yang mampu mewakili gawatnya krisis ekologi saat ini. Kita bergumul mencari tahu pelaku kerusakan ekologi dan jari telunjuk kita akhirnya kembali pada diri kita. Kita menjadi terdakwa utama dalam perusakan ekologi dan bertanggung jawab dalam menebus ekologi dari bahaya holocaust. Komunitas beriman tak luput dari tanggung jawab global menebus ekologi. Ekoteologi merupakan sumbangan komunitas beriman untuk menebus ekologi dari ancaman kematian dini. Ia melihat semesta sebagai tubuh Tuhan yang menanti penebusan karena kedosaan manusia menggagahi ekologi hingga ekologi terancam mengalami kematian dini.
Krisis ekologi berderet panjang melintasi batas-batas geografi. Ia juga telah merambah bumi Indonesia hampir tanpa jeda. Pembalakan hutan, pengerukan mineral, gempa bumi, gelombang pasang, dan banjir hampir mengenai semua wilayah Indonesia. Lolosnya para pelaku perusakan ekologi dari jerat hukum dan lambannya tanggapan terhadap para korban bencana ekologi merupakan penera yang menunjukkan masih rendahnya kepedulian negara kita terhadap krisis ekologi. Kita juga menerima dampak krisis ekologi global dalam bentuk desakan dari komunitas dunia untuk memelihara hutan kita sebagai salah satu paru-paru dunia. Krisis ekologi juga mendesak teolog untuk menggambarkan ulang mengenai Allah penebus di tengah kerusakan ekologi.
Agenda Baru Teologi
Ekoteologi menamai sebuah fokus baru dalam ranah teologi sebagai tanggapan terhadap krisis ekologi. Ia merupakan anak ilmu dalam teologi yang masih membutuhkan eksplorasi akademik untuk mengisi kosa kata baru ini. Ia menandai babak baru dalam dalam relasi antara teologi dan ekologi yang dalam periode sebelumnya telah melahirkan teologi penciptaan dan lingkungan. Kedua teologi pendahulu ini berangkat dari asumsi manusia sebagai pusat ciptaan yang mendapatkan tugas dari Allah untuk merawat keutuhan ciptaan (integrity of creation). Ekoteologi melukis ulang kisah penciptaan dan tanggung jawab baru manusia sebagai rekan Allah dalam menebus kerusakan ekologi. Ekoteolog mengajukan dakwaan dosa kepada manusia kontemporer yang menggagahi ciptaan-ciptaan lain. Mereka menawarkan budaya ekologi baru yang menuntut komitmen manusia sebagai salah satu ciptaan dalam ekologi untuk membalut luka-luka dalam tubuh ekologi.
Akademisi dan praktisi di bidang-bidang lain yang membuka mata para teolog terhadap situasi genting ekologi kontemporer. Mereka memberikan sumbangan luar biasa kepada para teolog dalam menggeser fokus pertanyaan teologi dan membidani lahirnya ekoteologi. Pada kesempatan kali ini penulis berfokus pada gerakan ekologi dalam tradisi kristiani.[2] Para teolog yang melibatkan diri dalam diskusi krisis ekologi menggunakan hasil kajian ilmu alam berkaitan dengan sejarah ciptaan dalam alam semesta. Mereka juga menggunakan kajian ilmu-ilmu sosial untuk memotret kebudayaan manusia yang membiakkan perusakan ekologi, dan efek negatif dari teologi penciptaan dan lingkungan yang masih menekankan manusia sebagai pusat ciptaan. yang melahirkan perusakan ekologi. Mereka mengusulkan untuk tidak memisahkan diskusi krisis ekologi dari keadilan ekonomi. Para ekoteolog menyadari diri dengan rendah hati sebagai pendatang belakangan dan berkomitmen untuk melibatkan diri dalam diskusi dan praksis global menebus ekologi dari ancaman kematian dini.
 Sallie McFague, teolog ekofeminis Amerika Serikat, mendeteksi kegagalan teologi kristiani menanggapi isu penting dan mendesak ekologi. McFague menangkap pergeseran agenda teologi mulai abad 20 hingga saat ini. Para teolog bergumul dengan agenda mengenal Allah hingga tahun 1960-an. Teologi pembebasan yang berkuncup pada tahun 1970-an dan bermekaran sesudahnya menawarkan agenda baru membebaskan dunia. Agenda teologi abad 21 merupakan penggalian lebih lanjut dari periode-periode sebelumnya, yaitu menyelamatkan ciptaan-ciptaan Allah dari ancaman kematian dini.[3] David C. Hallman melihat komunitas beriman kristiani sedang menjalani masa transisi dari teologi perawatan lingkungan menuju ekoteologi.[4] Perspektif sejarah membantu kita untuk memahami pergumulan Gereja, bahkan kegagalannya, dalam menanggapi krisis ekologi secara lebih empatik.
Sallie McFague, teolog ekofeminis Amerika Serikat, mendeteksi kegagalan teologi kristiani menanggapi isu penting dan mendesak ekologi. McFague menangkap pergeseran agenda teologi mulai abad 20 hingga saat ini. Para teolog bergumul dengan agenda mengenal Allah hingga tahun 1960-an. Teologi pembebasan yang berkuncup pada tahun 1970-an dan bermekaran sesudahnya menawarkan agenda baru membebaskan dunia. Agenda teologi abad 21 merupakan penggalian lebih lanjut dari periode-periode sebelumnya, yaitu menyelamatkan ciptaan-ciptaan Allah dari ancaman kematian dini.[3] David C. Hallman melihat komunitas beriman kristiani sedang menjalani masa transisi dari teologi perawatan lingkungan menuju ekoteologi.[4] Perspektif sejarah membantu kita untuk memahami pergumulan Gereja, bahkan kegagalannya, dalam menanggapi krisis ekologi secara lebih empatik.
Gereja hingga saat ini barangkali masih satu-satunya institusi agama yang hampir selalu berada di kursi terdakwa saat pemerhati ekologi berdiskusi mengenai pelaku utama atau figuran dalam kerusakan ekologi. Para pemerhati ekologi mendakwa Gereja sebagai pewaris tunggal budaya patriarki dan menyusun teologi penciptaan dan perawatan lingkungan yang biastelah mengeluarkan dan mengekalkan teologi penciptaan dan perawatan lingkungan yang bias patriarki. Teologi penciptaan dan perawatan lingkungan dalam prakteknya membiakkan kerusakan ekologi. Para teolog kristiani hendaknya menempatkan kritik mereka dalam bingkai pengaruh agama kristiani dalam kebudayaan Barat. Studi-studi lanjutan mengenai relasi agama kristiani dengan kerusakan ekologi, terutama kajian feminisme dan poskolonialisme, mencelikkan mata semua komunitas beriman karena virus patriarki juga bersarang dalam komunitas-komunitas beriman lainnya. Persenggamaan patriarki dengan industrialisasi dan kolonialisme membiakkan monster ekonomi yang mengabaikan kelestarian ciptaan. Monster ekonomi ini tak pernah puas dalam menghisap kekayaan ekologi. Ekoteolog tak boleh alpa terhadap para pelaku ekonomi dari level lokal sampai multinasional yang seringkali luput dari pandangan kita saat kita berbicara mengenai krisis ekologi.
Ekoteolog melukiskan kembali kisah penciptaan. Mereka menolak pandangan tradisional yang melihat penciptaan dari tingkatan yang lebih sederhana menuju tingkatan yang lebih sempurna. Dalam bingkai ini manusia menjadi puncak kisah penciptaan. Teologi penciptaan dan perawatan lingkungan dibangun dari bingkai kisah penciptaan ini. Manusia ditempatkan sebagai ciptaan istimewa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia berelasi dengan ciptaan-ciptaan lain secara piramidal. Mereka tidak hanya menemukan diri mereka berbeda, tetapi juga terpisah dari ciptaan-ciptaan lain. Ia menaikkan diri sebagai tuan atas ciptaan-ciptaan lainnya. Ia juga merasa mendapatkan penugasan istimewa dari Tuhan untuk merawat ciptaan-ciptaan lain. Mereka dapat mempergunakan atau mengeksploitasi ciptaan-ciptaan lain demi keberlangsungan hidup manusia.
Ekoteolog melukis kisah penciptaan secara kosmosentris. Kisah penciptaan mulai kehadiran ciptaan-ciptaan bukan manusia dan manusia menyusul kehadirannya di planet bumi. Mereka memiliki mekanisme mempertahankan dan memekarkan kehidupan mereka secara lestari. Kehidupan mereka dapat berlangsung sebelum manusia hadir diantara mereka. Manusia menjadi anggota kemudian di planet bumi setelah periode penciptaan sangat panjang. Ekoteolog menolak pencitraan manusia sebagai tuan atas ciptaan-ciptaan lain karena gagasan itu mengingkari kisah penciptaan. Manusia berelasi dengan ciptaan-ciptaan lain tidak dalam relasi hirarkis melainkan relasi lingkaran. Semua ciptaan saling terkait dan tergantung satu sama lain. Ekoteolog menanggalkan citra palsu manusia sebagai tuan atas ciptaan-ciptaan lain. Mereka tetap mengakui peran penting manusia dalam kehidupan planet bumi, namun menolak klaim peran utama manusia dalam ekologi.
Ekoteolog berhadapan dengan lukisan penciptaan yang dirusak dosa manusia. Sebagian kerusakan ekologi tertera jelas dalam pandangan indera publik. Kerusakan ekologi besar seringkali justru tersembunyi dari penglihatan mereka. Ekofeminis menawarkan gender sebagai instrumen hermeneutik untuk membongkar para pelaku kejahatan ekologi. Alam mengalami penderitaan seperti perempuan dalam sejarah. Rosemary Radford Ruether mengutuk budaya patriarki karena budaya ini memberikan kontribusi negatif tidak hanya terhadap kemanusiaan perempuan tetapi juga terhadap perusakan alam sepanjang sejarah. Ruether tanpa ragu menunjuk tangan manusia yang menyembah budaya patriarki menyebabkan pencemaran terhadap alam. Kerusakan ekologi pertama-tama dan terutama terjadi karena perilaku dominatif manusia terhadap alam. Ruether mengusulkan agar laki-laki dan perempuan berbagi kesetaraan dalam tanggung jawab sebagai wakil Tuhan dalam mengelola alam.[5]
[1] Rohaniwan Katolik yang sedang mendalami teologi sistematik di Jesuit School of Theology di Berkeley dan mengembangkan teologi kemanusiaan kontemporer
[2] Rosemary Radford Ruether mengamati mekarnya tulisan-tulisan perempuan mengenai ekologi. Ruether sekaligus menilai bahwa tulisan-tulisan ecofeminis belum sampai pada taraf kedalaman dan membutuhkan eksplorasi akademik lanjutan. Saya mengusulkan beberapa tulisan rintisan pendek mengenai ecofeminisme dari tradisi religius lain antara lain Stephanie Kaza, “Buddhism, Feminism, and the Environmental Crisis”; Judith Plaskow, “Feminist Judaism and Repair of the Word”; Lina Gupta, “Purity, Pollution, and Hinduism”; Chung Hyun Kyun, “Ecology, Feminism, and African and Asian Spirituality: Towards a Spirituality of Eco-Feminism.”
[3] Sallie McFague, “An Earthy Theological Agenda” dalam Carol J. Adams (Ed.), Ecofeminism and the Sacred (New York: Continuum, 1993), 84.
[4] David G. Hallman, Beyond “North/South Dialogue” dalam David G. Hallman, Ed., Ecotheology: Voices from South and North (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994), 6.
[5] Rosemary Radford Ruether, New Woman/New Earth (1975), 186; Ruether, 1989, 2. Ruether, “Eco-feminism and Theology” in David G. Hallman, Ecotheology, 199 – 201.
http://mudrajad.com/wp-content/upload/gempa.JPG