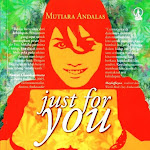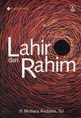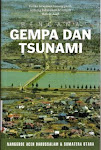Di Sisi Korban Tersalib
Oleh Mutiara Andalas, S.J. [1]
Simon dari Kirene dan Veronika hadir sepintas dalam lintasan jalan salib. Prajurit menarik paksa Simon dari Kirene dari tengah massa untuk membantu memanggul salib Yesus menuju Golgotha. Menyeruak dari kerumunan massa dan menerobos penjagaan prajurit, Veronica mengusap paras Yesus. Kahlil Gibran (1883 – 1931), dalam The Prophet, menggubah dialog imajiner antara Yesus dan Simon dari Kirene. “Engkau turut meminum cawan penderitaan. Engkau akan besertaku mereguk piala keselamatan.” "Tangan-Mu di bahu mengangkat salib berat yang kupanggul." Di mata Kardinal Yosef Bernardin (1928 – 1996), Veronica merupakan pewahyuan sakramental dari perempuan yang berperan penting dalam kehidupan Yesus dengan keberanian lembutnya. Ketukan panggilan yang menggerakkan Simon dari Kirene dan Veronika di jalan salib Yesus terdengar lagi saat membaca Saatnya Korban Bicara.
Kesaksian Tanpa Pendengar
Kisah para korban kekerasan negara juga muncul dalam kesaksian saat aksi Kamisan. Jika aksi Kamisan memilih nirkata sebagai bahasa perlawanan, Saatnya Korban Bicara menggunakan kata sebagai instrumen perlawanan. Keheningan dan kata paguyuban keluarga korban menyingkap penderitaan korban untuk membongkar kejahatan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana ditandaskan Ho Kim Ngo, ibu almarhum Yun Hap,“Percuma kami berteriak sekeras-kerasnya jika hanya kami sendiri yang mendengarkan. Kemana lagi kami harus mencari keadilan?” (69) Romo Sandyawan Sumardi, S.J., salah satu pendamping paguyuban keluarga korban, menangkap ‘sebuah kekuatan raksasa, entah itu bernama negara atau militer, di balik bayangan hiruk pikuk massa di jalanan dan di balik punggung para pelanggar hak asasi manusia’ (xv).
Paguyuban keluarga korban melukis ulang sejarah Indonesia berdasarkah kisah korban penembakan, pembakaran, kekerasan seksual, peracunan, penculikan, penggusuran, kekerasan terhadap buruh migran dan sebagainya. Tragedi penderitaan korban menjadi kisah sumber untuk menafsirkan peristiwa hidup sebelum dan sesudahnya. Kisah masa lalu, menyitir teolog pembebasan Leonardo Boff, menjadi sakramen pembebasan saat kita memandangnya dari penglihatan Allah. Sebaliknya antisejarah berlangsung ketika kuasa illah melanggar perikemanusiaan korban. Sejarah manusia dapat menjadi sakramen pembebasan atau sebaliknya penindasan.
Ciptaan Tersalib
Narasi korban menyingkapkan pergumulan eksistensial, bahkan relijius sebagai ciptaan Allah yang tersalib penderitaan. Peziarahan mereka mencari pelaku pelanggaran HAM merupakan via dolorasa yang memedihkan hati mereka. Kehampaan, kebuntuan, kekelaman, kabut merupakan sebagian kosa kata yang mengungkapkan sisi dalam peziarahan. Di sisi korban mereka mengajukan pertanyaan kepada aparat negara, masyarakat, dan Allah. Mereka berjumpa dengan kebisuan negara dan kekurangpedulian masyarakat. Allah dialami menyediakan bahu untuk memanggul tubuh paguyuban keluarga korban yang kelelahan memanggul salib kehidupan. Sebagaimana dituturkan Suciwati, “Kenapa bukan aku saja yang Engkau panggil, Ya Allah? Mengapa harus dia? Mengapa dengan cara seperti ini? Mengapa harus saat ini? Mengapa? Ya Allah, Kau boleh ambil nyawaku, hamba siap menggantikannya. Dia masih sangat kami butuhkan, negara ini butuh dia” (8).
Paguyuban keluarga korban menghadirkan kebenaran tragedi kemanusiaan dari perspektif korban yang selama ini dihilangkan dalam wacana politik. Pemerian kekerasan pada tubuh korban yang mendetail disertai pelakunya harapannya menggugah solidaritas kita dengan korban. Mereka juga berbicara dengan kita melalui bahasa air mata. Penyingkapan identitas korban dari pribadi-pribadi terdekatnya membongkar stigma sebagai subversif yang disematkan secara paksa pada tubuh mereka. Narasi korban subversif karena menggugat paradigma negara yang meniadakan kesaksian korban. Sebagaimana diungkapkan Arief Prijadi, ayah almarhum Wawan, “Ketika peristiwa masih segar, tangis keluarga korban memang penuh makna dan mampu mengundang empati orang. Namun dengan berjalannya waktu, apalagi masyarakat kita mudah terjangkit penyakit lupa, tangis kini hampir-hampir tidak lagi punya arti” (81).
Lanjutan Kisah Penyaliban
Membaca Saatnya Korban Bicara pada masa Prapaskah, penulis melihat kelanjutan kisah penyaliban Yesus. Korban Talangsari, Tanjung Priok, Poso, buruh migran, penarik becak, warga gusuran, dan rakyat miskin lainnya adalah tubuh-tubuh tersalib Indonesia. Kemanusiaan korban direnggut kesuciannya, bahkan dijarah nafas kehidupannya oleh rezim politik antikemanusiaan. Golgotha adalah lokasi historis penyaliban Yesus, sekaligus lokasi simbolik bagi komunitas kristiani untuk melukiskan penyaliban kemanusiaan korban sejarah dan mereka yang membela hidup korban. Menjelang pemilu 2009, kita akan mendengar kampanye politik yang mengangkat isu kerakyatan. Korban kekerasan politik telah lama dikeluarkan dari rahim kata rakyat. Sebagian politikus yang memacu diri untuk memimpin negara disebut kriminal HAM oleh paguyuban keluarga korban dalam buku.
Informasi Buku
Judul Buku : Saatnya Korban Bicara: Menata Derap Merajut Langkah
Pengarang : Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan
Kata Pengantar : I. Sandyawan Sumardi, S.J.
Penerbit : Yayasan TIFA, Jaringan Relawan Kemanusiaan, dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan
Tahun : 2009
Halaman : 200 + xxiii
[1] Rohaniwan Katolik yang pernah mendampingi paguyuban keluarga korban Mei - Semanggi 1998, dan menulis Kesucian Politik: Agama dan Politik di Tengah Krisis Kemanusiaan (Jakarta: Libri, 2008).