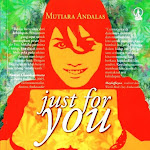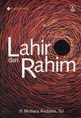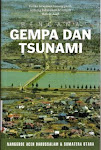Sejarah Tanpa Paras Korban
Oleh Mutiara Andalas[1]
Pilihan hidup bermartabat itu
ibarat menjatuhkan dadu kematian.
Eduardo Galeano, We Say No, 87.
| I |
stana Presiden, kantor Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan institusi negara lainnya kembali hadir dalam kenangan. Potret korban dan duka cita keluarga korban hadir dalam aksi korban menggugat. Mereka membawa serta penderitaan perempuan Indonesia etnis Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual massal dalam tragedi Mei 1998 yang dipinggirkan, bahkan ditolak kesaksiannya. Langkah paguyuban keluarga korban jarang sampai tujuan karena terhalang benteng aparat keamanan. Di titik-titik perhentian wakil paguyuban menyerukan pernyataannya. Perhentian demi perhentian, bahkan pembubaran paksa menjadi ritual berhadapan dengan negara yang seringkali melelahkan langkah paguyuban. Di jalan laras senjata menghadang kaki korban, di parlemen wakil rakyat mengabaikan suara mereka, dan di pengadilan aparat hukum menjegal langkah korban. Aksi Kamisan, perlawanan nirkata di depan Istana Presiden terhadap kekerasan negara, merupakan salah satu wadah bagi paguyuban korban Mei 1998 bersama korban politik lainnya untuk menyuarakan gugatannya.
Perjumpaan dengan sisi dalam penderitaan paguyuban korban menggugat hidup kemanusiaan-iman. Saya bergumul membingkai abjad kemanusiaan korban yang seringkali tersampaikan dengan air mata. Pembisuan korban mempersulit kita mendengarkan pesan kemanusiaan mereka. Saya menempatkan diri dalam satu aras pemikiran dengan Eduardo Galeano sebagai pemburu kenangan pascatragedi kemanusiaan.
Saya bukan ahli sejarah. Saya penulis yang tertantang teka-teki dan kebohongan, yang mendambakan masa sekarang berhenti menjadi sesal penuh derita untuk masa lalu, yang hendak melukis masa depan daripada menerimanya: seorang pemburu suara yang berserakan, hilang dan benar. Kenangan yang semestinya mendapat perlindungan telah diserakkan menjadi ribuan serpihan (We Say No, 256).
Penulisan tragedi kemanusiaan 1998 bahkan setelah 11 tahun tragedi masih menghapus paras korban. Kesaksian demi kemanusiaan korban tampil sebagai perlawanan terhadap kebisuan negara dan pembisuan korba pascatragedi. Narasi korban memiliki kuasa subversif karena mendorong masyarakat untuk berpaling kembali kepada tragedi yang semakin dilupakannya. Galeano lebih lanjut membantu saya untuk menempatkan penulisan kisah korban sebagai narasi harapan dan nubuat.
Kami mencari lawan bicara, bukan pengagum. Kami menawarkan dialog, bukan pertunjukan. Tulisan kami mengandung hasrat untuk bertaut dengan pembaca sehingga mereka terlibat abjad yang datang kepada kami dari mereka, dan mengembalikannya kepada mereka sebagai harapan dan nubuat (We Say No, 140).
Narasi Subversif
Berita media massa di sekitar tragedi Mei 1998 menyingkap, tetapi terkadang mendangkalkan penderitaan korban. Paguyuban keluarga korban semakin menemukan kekuatannya untuk menuturkan sendiri penderitaan korban. Penuturan mereka merupakan gerilya kemanusiaan untuk mengembalikan sisi subversif penderitaan korban. Mereka mengacungkan telunjuk jari pada aparat negara yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap tragedi. Mohamad Sani, orang tua korban Muhammad Ikhwan dan Mulyani, bertutur tentang tragedi
Mayat-mayat itu tidak semuanya hangus terbakar.
Kebenaran tampil tanpa paras dalam kesaksian korban kekerasan seksual massal. Kita jarang memperhitungkan trauma korban pascatragedi untuk memahami absennya suara korban. Alih-alih memandangnya sebagai kebisuan korban dan aksi bungkam relawan/wati kemanusiaan, kita hendaknya lebih berbicara tentang kebisuan negara dan pembisuan korban. Denyut politik pelupaan yang mengubur paksa kebenaran terdeteksi saat kita mengenali kebisuan negara dan pembisuan korban sebagai pilar-pilarnya. Publik terbawa arus memungut kata ‘kerusuhan’ untuk menamai peristiwa Mei 1998. Narasi versi negara menempelkan stigma perusuh dan penjarah pada tubuh korban meninggal yang kebanyakan rakyat miskin urban. Korban kekerasan seksual massal yang sebagian besar perempuan Indonesia etnis Tionghoa mendapat dakwaan sebagai penyebar kebohongan. Praduga bersalah terhadap korban menghalangi publik untuk solider dengan penderitaan mereka. Pada saat-saat awal pelaku melancarkan politik pelupaan demi memutus solidaritas dengan korban. Kebungkaman terhadap kejahatan diskriminasi rasial, bahkan suara penolakan terhadap korban sekarang keluar dari tutur publik.
Ketidakhadiran korban dalam narasi tragedi Mei pertama-pertama melukai paguyuban keluarga korban. Mereka yang diambil paksa kehidupannya dan diserang seksualitasnya menjadi korban sekaligus terdakwa dalam tragedi Mei 1998. Penulisan tragedi yang mendakwa korban melepaskan pelaku dari mata perhatian kita. merugikan paguyuban keluarga korban. Gerda Lerner memandang seleksi dan penyuntingan kenangan sebagai alat represi rezim.
Pelupaan kolektif terhadap sisi gelap masa lalu melukai baik individu maupun masyarakat. Penyembuhan dan keputusan yang lebih baik mustahil berlangsung jika tanggung jawab terhadap konsekuensi tindakan di masa lalu dihilangkan.... Pertautan dengan masa lalu mensyaratkan keterlibatan aktif. Imajinasi dan empati perlu ada untuk mendalami dunia yang berbeda dibandingkan sekarang, konteks yang jauh dari kita, cara berpikir-merasa asing. Kita harus memasuki dunia masa lalu dengan penuh selidik sekaligus hormat.... Kenangan selektif melucuti kemampuan kita melukis masa lalu yang benar. Kenangan selektif dan distorsi sejarah merupakan alat ampuh dari rezim penindas. Kita membutuhkan sejarah mereka yang sebelumnya dikebawahkan rezim (Why History Matters, 52. 201. 206).
Solidaritas dengan Korban
Kita baru saja melewati satu dekade tragedi Mei 1998. Peziarahan demi kemanusiaan Indonesia ini menguras tenaga paguyuban keluarga korban. Penjegalan demi penjegalan baik di lapangan maupun di ruang hukum melemahkan kaki perjuangan mereka. Ia juga menggoyahkan tubuh paguyuban. Kemunduran sebagian besar anggota menguruskan tubuh paguyuban. Tubuh pendamping juga mengalami pengerempengen. Suara kesaksian subyek korban tragedi kemanusiaan Mei 1998 terancam hilang. Subyek korban sudah bertindak maksimal untuk memperjuangkan kasusnya. Kita yang menyaksikan tragedi, bahkan hidup di sekitar subyek korban, masih minimal dalam membela kemanusiaan mereka.
Elie Wiesel bergumul dengan persoalan senada dalam One Generation After. Wiesel mengundang pembaca untuk menyadari bahwa mereka mengetahui tragedi kemanusiaan Holocaust. Tragedi Holocaust dalam arti tertentu merupakan misteri yang sulit ditangkap sepenuhnya oleh kajian keilmuan, bahkan dengan kesaksian subyek korban. Halangan ini hendaknya justru mendorong kita untuk menyingkapnya. Wiesel melihat publik terjerat dalam konspirasi untuk bungkam terhadapnya (conspiracy of silence). Mereka seharusnya berteriak untuk mengecam kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Pembungkaman juga terjadi pada mereka yang berusaha bicara tentangnya. Ia berbicara tentang tragedi kemanusiaan karena ingin mempertautkan kembali relasi dengan sesama yang terputus. Manusia perlu kembali pada kesadaran sejarah atau semangat solidaritas. Sebagai saksi tragedi, kita harus memperkarakan peradaban masyarakat atau rezim yang mengangkangi perikemanusiaan korban (One Generation After, 52. 166 - 167).
Kitab suci kristiani memiliki gambaran menyentuh mengenai solidaritas dengan korban. Kita dapat berpaling pada kisah di sekitar penyaliban Yesus untuk melihat praksis solidaritas. Meskipun sebagian besar rasul tercerai berai setelah penangkapan Yesus, Petrus dan Yohanes berusaha melihat perkembangan terakhir Yesus sebelum penyalibannya. Saat Pontius Pilatus memilih untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan melepaskan Barabas, para sahabat Yesus memprotes keputusannya. Mereka menyertai perjalanan Yesus memanggul salib. Simon dari Kirene menggantikan Yesus memanggul salib selama beberapa waktu. Komunitas kristiani juga menambahkan kisah Veronika yang berani menerobos massa dan aparat untuk mengelap paras Yesus. Para perempuan, komunitas yang mengalami pembebasan Yesus, berdiri di sepanjang jalan salib untuk berduka cita atas penderitaannya. Para perempuan, termasuk ibu-Nya, berdiri di sekitar salib sebagai saksi atas perendahan kemanusiaan Yesus di salib. Setelah wafat Yesus, mereka menyelamatkan tubuh-Nya dari ancaman perendahan lebih lanjut. Wafat Yesus, menyitir Ivone Gebara, mengubah salib dari alat hukuman menjadi simbol kedukaan (Out of Depths, 115).
Paguyuban keluarga korban Mei 1998 sekarang berjuang bersama korban kekerasan politik lain demi penegakan hak asasi manusia. Mereka menyadarkan masyarakat akan rezim kekuasaan yang memerintah dengan tangan kekerasan di masa lalu. Subyek korban memberikan kesaksian atas penculikan, penembakan, pembakaran, perkosaan terhadap warga oleh aparat negara. Sebaliknya aparat negara membela dirinya sebagai abdi yang taat perintah atasan untuk menjaga ketertiban umum atau keamanan nasional. Paguyuban keluarga korban menyadari jalan panjang yang harus dilalui untuk menyakinkan publik akan fakta brutal ini. Jika pada waktu-waktu sebelumnya kisah tragedi versi negara berhasil meraih kepercayaan publik, sekarang paguyuban keluarga korban menggoyahkannya dengan narasi lain yang subversif di mata negara. Paguyuban keluarga korban membongkar praktek negara yang menyeleksi kenangan akan tragedi menjadi kenangan kolektif dengan korban sebagai terdakwanya. Kebenaran versi negara merupakan kebohongan dalam pandangan paguyuban.
Paguyuban keluarga korban Mei 1998 mengakui pasang surut peziarahan mereka memanggul tubuh korban. Tragedi Mei 1998 bukan akhir penderitaan bagi keluarga korban. Sebagian keluarga mengalami penderitaan lanjutan pascatragedi. Perjuangan demi keadilan korban yang ternyata lebih panjang daripada yang dibayangkan menyebabkan sebagian besar anggota mengambil keputusan berat untuk undur diri. Mereka mendahulukan kepentingan memenuhi kebutuhan untuk anggota keluarga yang masih hidup. Mohamad Sani memilih perjuangan lain di luar paguyuban yang barangkali lebih membawa harapan keadilan bagi korban. Sebagian korban lain menata kembali hidupnya pascatragedi dan berharap tragedi Mei merupakan pelanggaran terakhir terhadap hak asasi manusia Indonesia.
Perjuangan demi keadilan korban bukan sekedar milik paguyuban keluarga korban. Perjuangan kemanusiaan membutuhkan keterlibatan bukan hanya pribadi-pribadi yang pernah bersentuhan dengan kasus korban. Paguyuban keluarga korban mengundang keterlibatan yang lebih luas dari publik dalam mendukung perjuangan mereka. Dukungan publik selama ini lemah karena paguyuban keluarga korban dikeluarkan dari publik. Kepentingan mereka dianggap sebagai kepentingan yang tidak mewakili kepentingan bersama. Solidaritas dengan mereka berarti mendaku kembali hubungan kita dengan mereka. Ketidakpedulian publik merupakan beban tambahan dalam perjuangan paguyuban.
Sampai saat ini Perjuangan mereka sangat membutuhkan dukungan kita yang diberi karunia melihat tragedi Mei 1998 baik langsung maupun melalui perantaraan media. Kita mengidap bahaya menjadi kebal terhadap penderitaan korban. Korban seringkali telah hilang dalam hitungan angka yang sedemikian mudah terlewatkan dari perhatian. Saat ini menjadi saat yang baik untuk kembali merengkuh korban karena hanya dengan demikian kita dapat melihat cacat negara Indonesia. Kita barangkali perlu melihat diri kita saat air mata korban kehilangan kuasa untuk menggerakkan hati kita. Barangkali kita telah membangun sistem kekebalan terhadap penderitaan orang lain. Terlalu lama kita membiarkan politik kekerasan dan kemudian disusul dengan pelupaan seolah menjadi bagian dari tubuh bangsa Indonesia. Kita dapat memulainya dengan gerakan mendukung perjuangan mereka.
Para korban sejak awal membuka tangannya terhadap keterlibatan publik. Politik pelupaan yang ditandai aksi bisu negara dan pembisuan korban mempersulit publik untuk merasakan penderitaan korban. Sekarang paguyuban keluarga korban menerobos rintangan politik untuk mengungkapkan kesaksian akan penderitaan sekaligus perjuangannya. Jika pada waktu-waktu sebelumnya kita berpaling dari mereka karena kurangnya pengetahuan atau kepeduliaan, sekarang saatnya publik mendengarkan kebenaran tragedi versi korban dan solider dengan mereka. Penulisan tragedi Mei 1998 tanpa paras korban merupakan pengkhianatan atasnya. Penghapusan paras korban dalam tragedi menyingkapkan rendahnya penghargaan kita terhadap kemanusiaan di Indonesia. Sekarang paguyuban keluarga korban mengundang publik untuk menyatakan penolakan terbuka atas perusakan kemanusiaan dalam tragedi Mei 1998.
Perjuangan Kemanusiaan – Iman
Saya mengakhiri tulisan dengan kisah pertobatan kemanusiaan-iman yang menghantar saya untuk semakin berbela rasa dengan penderitaan dan perjuangan korban. Pengalaman melihat korban bakar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan menghadiri penguburan massal mereka di TPU Pondok Rangon menggerakkan hati saya untuk berjumpa dengan keluarga korban. Korban yang kehilangan parasnya dibungkus dengan kain kafan dan dihantar ke pemakaman dengan doa. Penghormatan kehidupan juga berlangsung dengan tindakan jibaku relawan-relawati melindungi korban kekerasan seksual. Korban yang dirusak kemanusiaannya suci di mata keluarganya. Keluarga korban mendidik saya untuk melihat kesucian hidup korban dalam tubuh hangus dan dirusak dengan kekerasan seksual.
Air mata duka, bahkan peluh kelelahan korban saat berhadapan dengan aparat negara mengetuk saya. Tindakan membiarkan paguyuban sendirian memperjuangkan kasusnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan iman kristiani. Solidaritas menjadi titik perjumpaan perjuangan kemanusiaan dan komitmen iman kristiani pada korban. Perjuangan bersama paguyuban masih jauh dari kata selesai. Semakin jauh dari tragedi Mei, negara justru semakin mengabaikan janji untuk menyelesaikan kasusnya. Paguyuban telah berjuang maksimal untuk mendorong kasusnya agar mendapat perhatian aparat negara. Semoga tulisan ini mengobarkan solidaritas politik kita dengan perjuangan paguyuban. Pelupaan terhadap tragedi Mei 1998 dan pembiaran aparat negara yang disebut kriminal HAM oleh paguyuban semakin menghapus paras korban dari sejarah Indonesia.
Berkeley, 4 Mei 2009
Daftar Pustaka
Galeano, Eduardo. We Say No: Chronicles 1963 – 1991. Translated by Mark Fried and Others. New York: W.W. Norton and Company, 1992.
Gebara, Ivone. Out of Depths: Women’s Experience of Evil and Salvation. Translated by Anne Patrick Ware.
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, Saatnya Korban Bicara: Menata Derap Merajut Langkah. Kata Pengantar oleh I. Sandyawan Sumardi, S.J. Jakarta: Yayasan Tifa, Jaringan Relawan Kemanusiaan, Jaringan Solidaritas untuk Keadilan Korban, 2009.
Lerner, Gerda., Why History Matters: Life and Thought.
[1] Rohaniwan Katolik yang pernah mendampingi paguyuban keluarga korban Mei – Semanggi 1998. Ia menuangkan sebagian perjumpaan dengan komunitas korban dalam buku Kesucian Politik: Agama dan Politik di tengah Krisis Kemanusiaan (