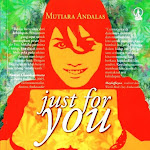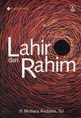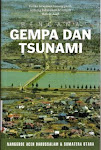Clara: Aku Bukan Asu!
Clara: Aku Bukan Asu! Oleh P. Mutiara Andalas, S.J.
Rasisme mempunyai kata awal
dan harapannya juga memiliki kata akhir.
Dinesh D'Souza
Siapakah aku? Dimana aku saat ini? Namaku Clara. Aku perempuan Indonesia beretnis Cina yang menjadi korban perkosaan massal dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998. Para pelaku melemparkan kedua saudariku, Monica dan Sinta, ke dalam api setelah mereka menggagahi keduanya. Mama juga menjadi korban perkosaan massal. Ia mengakhiri kehidupannya secara dini dengan menjatuhkan tubuhnya dari lantai empat. Dalam short message service terakhir, papa nampaknya akan mengikuti jejak mama. Di matanya, kehidupan telah habis dan ia merasa tak perlu melanjutkan kehidupannya sekarang. Kehidupannya hanya menyisakan hasrat memuncak untuk mati.
Kesaksian Clara tersela koma dan titik air mata. Kisah penderitaanya terangkai dalam kata-kata yang berserakan. Ia lebih banyak bertutur dengan bahasa keheningan. Setiap kali ia membuka bibirnya untuk bicara, ia mendengar teriakan-teriakan umpatan terhadap dirinya dan warga Indonesia beretnis Cina. Massa mengumpatnya sebagai asu dan pada saat yang sama mendaraskan Allahu Akbar. Umpatan asu menghantar penulis untuk membaca ulang tragedi kemanusiaan serupa di Muara Angke 1740 dan Kudus 1918. Clara dan warga Indonesia etnis Cina juga mengundang penulis untuk mengeja ulang kisah-kisah kitab suci yang menggunakan kata asu untuk menyapa yang lain.
Diskriminasi rasial dalam tragedi kemanusiaan Mei pertama-tama dan terutama politis, tetapi juga teologis. Para pelaku yang menggiring massa untuk menggelar teater kekerasan hendak menampilkan Allah diskriminasi rasial yang membenarkan kejahatan terhadap kemanusiaan warga Indonesia etnis Cina dan korban-korban tak bersalah lainnya. Refleksi atas sejarah diskriminasi rasial terhadap warga Indonesia etnis Cina berlanjut dengan refleksi teologis atas pertanyaan, “Siapakah Allah? Allah berpihak kepada siapa?” Pertanyaan-pertanyaan teologis ini mengundang penulis untuk membongkar citra-citra palsu Allah yang diciptakan rezim kolonial Belanda dan rezim kriminal Orde Baru. Penulis mengundang pembaca untuk memperhatikan citra baru Allah kehidupan sebagai menjumpai para korban sejarah akibat garis-garis pembatas yang diciptakan rezim kriminal.
Di Bawah Kaki Rezim Diskriminatif
Diskriminasi terhadap yang lain di Nusantara tampil ke permukaan dengan kehadiran rezim kolonial Belanda yang semula datang dengan eros ekonomi dan kemudian juga eros politiknya. Rezim kolonial Belanda mengklaim identitas dirinya dihadapan yang lain. Samuel Huntington dalam Who are We (2004) menjelaskan proses klaim identitas diri yang melahirkan pandangan terhadap yang lain.
Sebutan kita memiliki referensi tunggal atau jamak? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apakah faktor pembedanya ras, agama, etnisitas, nilai, budaya, kekayaan, politik, atau yang lainnya? … Jawaban terhadap pertanyaan identitas diri mempengaruhi kebijakan kita terhadap identitas lain. Konflik terhadap identitas yang lain berakar dari konflik terhadap identitas diri.
Rezim kolonial Belanda menemukan ras sebagai salah satu pembeda sosial di Nusantara dan membangun relasi hirarkis berdasarkan perbedaan ras. Mereka mendefinisikan ‘perbedaan rasial melalui hirarki sosial daripada hirarki sosial melalui perbedaan rasial. Hirarki sosial, dalam pandangan Steve Martinot, merupakan bentukan sosial. Para pelakunya menciptakan konsep ras dan rasialisasi berlangsung melalui pembuatan garis pembatas sosial berdasarkan perbedaan sosial. kategorisasi dan stratifikasi terhadap perbedaan.
Rezim kolonial Belanda menarik garis pembatas antara Belanda, Timur Jauh, dan Anak Negeri. Mereka mengeksploitasi warga Timur Jauh dan konglomerat lokal untuk memenuhi eros ekonomi-politik mereka Rezim kolonial Belanda menyingkirkan mayoritas warga Nusantara dan bahkan memutus tali pengikat komunitas antara warga Nusantara beretnis Cina dan Anak Negeri. Konflik horizontal antara warga Cina dan Anak negeri dapat berlangsung karena rezim kolonial Belanda menciptakan stigma kambing hitam politik dan ekonomi terhadap warga Nusantara etnis Cina. Rezim kolonial Belanda juga berhasil mengeksploitasi Anak Negeri sebagai tangan kekerasan terhadap warga Nusantara etnis Cina.
Tragedi Muara Angke meletus sebagai tanggapan keras rezim kolonial Belanda terhadap resistensi ekonomi-politik Rezim kolonial Belanda memandang mereka sebagai ancaman ekonomi-politik di Nusantara dan mengawasi mereka secara militer. Mereka menafsirkan kebakaran di salah satu rumah warga Indonesia etnis Cina sebagai resistensi politik terhadap kekuasaan mereka. Mereka menggelar pembantaian massal yang mengakibatkan lebih dari 10.000 warga Nusantara etnis Cina menderita kematian dini di Batavia. Warga Nusantara etnis Cina di penjara dan rumah sakit pun menjadi korban pembantaian massal. Mereka berhasil menghela budak berkulit hitam dan Anak Negeri untuk terlibat dalam pembantaian dengan alasan pembenar konspirasi Cina untuk menguasai Indonesia. Gubernur Jendral Belanda konon memberikan upah uang untuk setiap kepala warga Cina yang terpancung. Mereka juga memperkosa para perempuan Cina sebelum membantainya. Kejahatan terhadap kemanusiaan mereka sedemikian di luar bayangan keluarga korban dan keluarga korban sehingga sebagian memilih mengakhiri hidupnya sendiri atau melemparkan dirinya ke lautan api. Warga Nusantara etnis Tionghoa di Batavia pasca-tragedi hanya tersisa 3, 431
Pasca Tragedi Muara Angke, rezim kolonial Belanda mendirikan monumen yang ‘membaptis’ korbannya sebagai kriminal politik tak hanya terhadap mereka, tetapi juga terhadap Nusantara. bagi mereka, tetapi juga bagi Nusantara. Mereka juga menciptakan, yang dalam istilah Steve Martinot, ‘paranoia sosial.’ Tragedi kemanusiaan Muara Angke menjadi kenangan subversif bagi korban hidup dan keluarga korban. Warga yang tinggal di sekitar Muara Angke menyaksikan air bercampur darah, dan jenazah yang terapung membentuk jembatan penyeberangan.Samuel P. Huntington menjelaskan proses penciptaan stereotipe dan penghancuran identitas yang lain.
Identitas membutuhkan differensiasi dan perbandingan dibutuhkan dalam differensiasi. Perbandingan melahirkan penilaian. Kompetisi mengarah pada antagonisme dan perluasan atas persepsi terhadap yang lain yang semula kecil menjadi membiak. Stereotipe diciptakan, lawan diangkat ke tingkat musuh, kompetisi dan konflik hanya dapat terjadi antarentitas yang berada dalam semesta yang sama.
Tragedi Kudus pada tahun 1918 sepintas nampak sebagai konflik horizontal antara warga Nusantara beragama Islam dan etnis Cina. Tragedi Kudus sejatinya merupakan luapan keputusasaan dua warga Nusantara yang mengalami penderitaan ekonomi dan politik di bawah rezim kolonial Belanda. Para ulama yang mengelola bisnis lokal dan sekaligus memimpin jemaat Islam setempat melukis ulang identitas diri mereka dengan garis pembeda agama terhadap yang lain. Tragedi Kudus terjadi ketika beberapa pekerja yang mengangkut bahan bangunan untuk renovasi tempat ibadat mereka berjumpa dengan parade Cina di sekitar masjid. Massa di sekitar masjid meletup amarahnya ketika mendengar kabar burung bahwa parade Cina melecehkan melecehkan simbol-simbol Islam.
Massa mendengar kabar burung bahwa seorang laki-laki Cina mengenakan pakaian ulama dan duduk diapit dua perempuan yang mengenakan pakaian pekerja seks komersial. Mereka juga mendengar kabar burung bahwa warga Nusantara etnis Cina menampillan nabi Muhammad menenggak minuman keras dan menghisap mariyuana. Massa yang menerima provokasi menyerang parade dengan umpatan ‘Bunuh Cina’ dan mendarasakan ‘Allahu Akbar’ dan meluaskan tindakan anarksinya pada lokasi di sekitarnya. Ratusan warga Cina menyelamatkan diri ke daerah-daerah sekitar untuk mempertahankan kehidupan mereka dari ancaman kematian dini. Aparat pemerintah kolonial Belanda hanya menjadi penonton dalam tragedi itu dan menonton tragedi itu dan membiarkan konflik horizontal berlangsung.
Kekerasan Politik Berbaju SARA
Sebagaimana dalam era rezim kolonial Belanda, rezim Orde Baru juga memberikan keistimewaan ekonomi kepada beberapa konglomerat Indonesia etnis Cina. Tragedi Mei 1998 meledak setelah provokator berhasil menggiring massa untuk memasuki pusat-pusat perbelanjaan yang merupakan representasi kemakmuran dan sekaligus ketimpangan ekonomi. Mereka memprovokasi dengan stigma warga Indonesia etnis Cina sebagai penyebab krisis ekonomi. Kengerian mulai ketika para provokator membakar pusat-pusat perbelanjaan dan menjebak 1,185 warga dalam lautan api. Mereka juga menggelar perkosaan massal terhadap warga Indonesia etnis Cina di ruang terbuka atau dihadapan keluarga korban. Sebagian korban atau keluarga korban mengakhiri hidup mereka pasca-tragedi. Sebagaimana di Kudus, aparat keamanan berperan pasif atau minimal dalam menciptakan ketertiban umum.
Para provokator dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998 juga meneriakkan “Allahu Akbar” dan menyitir kata-kata bernuansa Islam untuk menyulut kemarahan massa. Banyak warga di sekitar lokasi melukis simbol-simbol bernuansa Islam di rumah atau lokasi bisnis mereka untuk melindungi diri dari perusakan dan penjarahan liar. Meskipun kurang mendapatkan dokumentasi, kita menemukan kisah-kisah kemanusiaan warga di sekitar lokasi tragedi Mei yang menyelamatkan saudara-saudari etnis Cina dari serangan fisik dan kekerasan seksual. Warga di sekitar lokasi tragedi yang mayoritas beragama Islam menyelamatkan warga Indonesia etnis Cina dengan mengenakan pakaian Muslim. Mereka menampung warga etnis Cina yang mengungsi dan mengadopsi mereka sebagai saudara-saudari baru mereka hingga keamanan berangsur pulih. Tak sedikit dari warga setempat mengajukan diri untuk melindungi aset warga etnis Cina dari amuk massa.
Allah Kehidupan di Nisan Kematian
Penulis menyaksikan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tragedi Mei 1998, dan mendampingi paguyuban keluarga korban mencari keadilan bagi korban. Mayoritas korban yang dievakuasi dari rerunAllah pusat-pusat perbelanjaan, menderita kematian dini dengan tubuh hangus. Keluarga korban tanpa lelah mencari tanda, betapapun kecilnya, yang dapat membantu mereka untuk mengenali identitas korban. Mereka mengabaikan bau busuk pada tubuh korban demi menjaga kesucian korban. Mereka mencari identitas korban untuk memberikan penghormatan kepada jenazah mereka dengan pemakaman yang layak. Paguyuban keluarga korban mengisahkan temuan korban di sekitar pintu keluar pusat-pusat perbelanjaan sebagai usaha terakhir korban menyelamatkan kesucian kehidupan. Sebagian korban meninggal dengan peluru bersarang pada tubuh mereka di dalam pusat-pusat perbelanjaan. Para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan korban Mei 1998 meninggal jejak mengerikan pada tubuh korbannya, namun menghilangkan jejak identitas para pelakunya.
Keheningan hadir di tempat pembaringan jenazah korban. Keheningan berlanjut ketika pemerintah memakamkan para korban tanpa identitas di Pondok Rangon. Pondok Rangon menjadi lokasi pertarungan kebenaran antara pemerintah yang ingin melupakan tragedi, dan paguyuban keluarga korban yang ingin mengenang korban. Pemerintah menempelkan stigma penjarah kepada para korban yang meninggal di dalam pusat-pusat perbelanjaan. Mereka juga menempelkan stigma warga Indonesia etnis Cina yang meninggalkan Indonesia pasca-tragedi sebagai pengkhianat bangsa. Pertarungan kebenaran juga berlangsung dengan kasus perkosaan massal terhadap warga Indonesia etnis Cina dalam tragedi Mei. Pemerintah hanya memiliki data yang sangat miskin untuk menemukan indikasi terjadinya perkosaan massal. Meminjam istilah Martinot, pengadilan resmi seringkali mendiskualifikasikan kisah korban hidup yang menjadi korban diskriminasi rasial untuk mengkualifikasikan kasusnya. Pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan ritual religius bersama sebagian keluarga korban untuk mendoakan korban dan mencuci tangan pemerintah dari tuntutan hukum.
Pondok Rangon menjadi titik awal bagi paguyuban keluarga korban untuk mengenang tragedi Mei dan membela kesucian korban. Tragedi Mei dalam kadar tertentu memiliki kesamaan dengan tragedi Nanking 1937 dimana pemerintah Jepang membungkam korban dan saksi korban. Iris Chang, dalam The Rape of Nanking (1997), membongkar kebohongan sistematis rezim Jepang untuk melupakan kenangan atas 20,000-80,000 perempuan Cina yang menderita perkosaan massal.
Kita harus mengenang perkosaan Nanking bukan sekedar karena jumlah massal korbannya, tetapi juga kekejaman terhadap korbannya yang menghantar mereka pada kematian dini. Militer Jepang tak segan-segan mengeksploitasi para lelaki Cina sebagai latihan bayonet dan kontes pancung kepala. Sekitar 20,000-80,000 perempuan Cina menderita perkosaan massal. Banyak prajurit Jepang tak sekedar memperkosa korbannya, tetapi melanjutkannya dengan merusak organ seksual korbannya, memotong payudaranya, atau memaku mereka hidup-hidup pada tembok. Mereka memaksa para ayah Cina untuk memperkosa puterinya dan anak laki-laki untuk menggagahi ibunya. Mereka memaksa anggota keluarga yang lain menonton adegan itu…. Namun perkosaan di Nanking tetap menyimpan keburaman sebagai tragedi.
Iris Chang mendeteksi kegagalan perkosaan Nanking menjadi kenangan bagi paguyuban keluarga korban dan kesadaran dunia. Kebanyakan korban hidup perkosaan memilih tutup mulut karena budaya mereka yang menjunjung tinggi keperawanan fisik atau kemurnian seksual tak mengizinkan mereka mengungkapkan kasus mereka. Sebagian korban berteriak dengan kata-kata rapuh untuk mencari keadilan, namun komunitas dunia seringkali gagal mendengarkan kesaksian mereka. Pemerintah Jepang menciptakan konspirasi kebungkaman yang menghalangi setiap usaha mengenang tragedi.
Tak seorang perempuan Cina pun tampil dihadapan publik untuk memberikan kesaksian bahwa anaknya merupakan korban perkosaan Nanking. Banyak bayi menderita kematian dini karena ibunya mengakhiri kehidupan mereka secara rahasia.… Para ibu korban perkosaan Nanking menghentikan nafas kehidupan bayi-bayi yang memiliki darah para pelaku perkosaan atau menenggelamkan para bayi itu segera setelah melahirkannya…. Rentang waktu antara 1937 dan 1938 tak terhitung korban perkosaan Nanking mengakhiri kehidupan mereka dengan melemparkan diri ke Sungai Yangtze.… Militer Jepang seringkali memaksa laki-laki Cina untuk melayani kebuAllah seksual mereka dengan sodomi atau memaksa para laki-laki Cina untuk memperagakan aktivitas seksual dihadapan militer Jepang yang menertawakan korbannya.
Militer Jepang menciptakan kebohongan institusional yang menolak fakta tragedi perkosaan Nanking dan tanggung jawab mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan korban. Mereka saat ini menggelapkan para korban Nanking “bukan dibawah tanah, tetapi dari ingatan sejarah.” Kesaksian Nagatomi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya terhadap perempuan Cina merupakan sebuah pengecualian.
Sedikit orang mengetahui fakta bahwa para prajurit Jepang menghunjamkan bayonet pada bayi-bayi Cina dan merebus korbannya. Mereka menggelar pesta seks dengan korban para perempuan Cina dari usia 12 hingga usia 80. Mereka membunuh para korbannya yang tak mampu lagi memuaskan seksualitas mereka. Aku memancung korbanku, membiarkan mereka mati kelaparan, membakar dan memakamkan korban hidup-hidup terhadap lebih dari 200 warga Cina. Kata-kataku tak mampu mengisahkan kebiadabanku seluruhnya. Aku bukan lagi manusia, melainkan binatang, bahkan iblis.”
Paguyuban keluarga korban Mei membantu penulis untuk lebih menyadari tempat-tempat baru untuk berdialog dengan Allah. RerunAllah pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, Pondok Rangon dan makam-makam pribadi lainnya menjadi tempat-tempat perjumpaan baru antara paguyuban keluarga korban dengan Allah. Tempat-tempat itu mengawali peziarahan paguyuban keluarga korban untuk menemukan identitas korban dan identitas Allah yang sejati. Mereka mencari bahasa liturgi yang menyuarakan penderitaan dan harapan korban. Mereka menyadari bahwa tragedi Mei menghancurkan bahasa dan kemampuan mereka untuk berdialog dengan Allah. Dialog mereka dengan Allah pasca-tragedi disela banyak jeda keheningan dan air mata. Bahasa resma ibadat seringkali menjadi disincarnated language. Mereka merangkai incarnated language yang seringkali sangat bernas dalam dialog dengan Allah. Mengapa? Mengapa, ya Allah?
Seno Gumira Ajidharma, dalam cerita pendek Clara, mendeskripsikan kesulitan korban untuk mengisahkan penderitaannya kepada publik dan kesulitan publik untuk mendengarkan kisah korban.
Dia bercerita dengan bahasa yang tidak mungkin dimengerti. Bukan Karena bahasa Indonesianya kurang bagus, karena bahasa itu sangat dikuasainya,tapi karena apa yang dialami dan dirasakannya seolah-olah tidak terkalimatkan…. Ceritanya terpatah-patah. Kalimatnya tidak nyambung. Kata-kata bertebaran tak terangkai sehingga aku harus menyambung-nyambungnya sendiri. Beban penderitaan macam apakah yang bisa dialami manusia sehingga membuatnya tak mampu berkata-kata?
Perjumpaan dan keterlibatan dengan paguyuban keluarga korban membantu penulis untuk melukiskan potret seorang beriman di tengah realitas korban. Paguyuban keluarga korban mengundang komunitas beriman di Indonesia berpaling kepada korban dan kepada Allah yang berbicara dari realitas korban. Paguyuban keluarga korban menyingkapkan illah-illah sejarah yang menggelar ritual kematian terhadap korban yang tak bersalah dan yang menggelarkan identitas anti-kehidupannya. Mereka mengundang komunitas beriman untuk berada di sisi mereka yang memperjuangkan keadilan bagi korban dan humanisasi masyarakat.
Saya bukan ahli bahasa, bukan pula penyair. Saya tidak tahu apakah di dalam kamus besar Bahasa Indonesia ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit, rasa terhina, rasa pahit, dan rasa terlecehkan yang dialami seorang wanita yang diperkosa bergiliran oleh banyak orang karena dia seorang wanita Cina…. Selangkangan saya sakit, tapi saya tahu itu akan segera sembuh. Luka hati saya, apakah harus saya bawa sampai mati? Siapakah kiranya yang akan membela kami? Benarkah kami dilahirkan hanya untuk dibenci?
Komunitas beriman rentan sekali jatuh dalam godaan mengabaikan realitas korban dan membangun sistem kekebalan dalam tubuhnya dari pengaruh penderitaan korban. Jon Sobrino mengundang komunitas beriman untuk menempatkan pembicaraan mengenai Allah dalam konfrontasi dengan illah kematian sejarah. Pembicaraan mengenai Allah mengalami pendangkalan ketika mengabaikan bahwa problem teologi
lebih dari sekedar berkutat sekitar keberadaaan atau ketiadaan Allah. Kita masih bergumul dengan persoalan illah sejarah, entah Allah ada atau tiada. Saya memahami berhala sebagai realitas teologis yang hidup, menawarkan janji keselamatan, dan meminta ritual korban, dan memerlukan ortodoksi. Kita dapat mendeteksi keberadaan illah sejarah dari ritual korban manusia yang dilakukannya. Pembicaraan mengenai Allah dan agama menjadi miskin, dangkal, ideologis, dan egois jika kita menempatkannya di luar konteks memuja illah kematian atau memuji Allah kehidupan.
Jon Sobrino mengundang komunitas beriman untuk memasuki realitas penderitaan dan melawan kebohongan institusional yang menggelapkan kebenaran. Kejujuran dengan realitas menghantar komunitas beriman untuk solider dengan korban sejarah dan untuk berkonflik dengan illah sejarah.
Kita tidak dapat menghapus kejahatan dengan tetap berada di luar realitas kejahatan. Agama Kristiani memahami inkarnasi sebagai tindakan memasuki realitas dan memahami Docetisme sebagai tindakan melarikan diri dari realitas. Kita membangun utopia keluarga umat manusia dengan jujur terhadap realitas dan solider dengan penderitaan korban yang hidup di sisi bawah sejarah.
Melintasi Dunia Yang Lain
Sejarah Indonesia berisi kisah warga yang berziarah melintasi garis-garis pembatas yang berpotensi memecah mereka, seperti suku, agama, ras, dan antarbudaya. Generasi pertama yang melakukan peziarahan jauh dari Hunan, berdasarkan Dinasti Han (206 BCE-220 CE), menyebut Indonesia sebagai Huang-Tze. Nusantara merupakan nama lain untuk Indonesia yang mengungkapkan peziarahan warganya melintasi batas-batas geografis kepulauan. Remy Sylado melukiskan Hein de Weit, seorang Belanda peranakan, dan Hien Nio, seorang Cina peranakan, sebagai generasi-generasi baru Indonesia yang melintasi pagar-pagar pemisah SARA dan membangun bangsa Indonesia berdasarkan kasih. Hein de Weit mendambakan Batavia dapat menjadi Amsterdam baru, kota yang penduduknya memeluk sejarah bersama dan menghormati sesamanya.
Aku menolak hidup dalam suatu lingkungan yang dibangun berdasarkan berdasarkan sentimen bangsa karena aku melhat cacat di dalamnya. Aku hidup di sini sekarang karena aku menghormati perikemanusiaan. Belanda dan Cina membuat kesalahan senada karena melecehkan perikemanusiaan dengan membangun tembok pemisah berdasarkan sentimen bangsa.
Sylado mendiskusikan pergumulan menjadi seorang Indonesia dengan mengangkat kasus warga Indoneisa yang memiliki nama Cina dan mempersembahkan hidup mereka pada pertiwi Indonesia dengan melawan Belanda. Ia juga mengangkat kasus mereka yang memiliki nama Indonesia namun melacurkan dirinya dengan menjadi antek penjajah Belanda. Musuh sesungguhnya bagi bangsa Indonesia bukan prasangka terhadap kebangsaan lain, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan. Sylado menolak garis-garis pembatas suku, agama, ras, dan antarbudaya sebagai karakter Indonesia.
Saya bukan seorang Belanda yang hidup diantara warga Cina, tetapi seorang manusia yang hidup diantara yang lain…. Sebagai seorang manusia, saya siap berada di garis depan untuk membela perikemanusiaan.
Sylado percaya Allah menciptakan bangsa Belanda setara dengan bangsa Indonesia. bangsa-bangsa lain. Rezim kolonial Belanda Bangsa memuja illah kematian karena mengklaim kuasa atas kehidupan dan kematian warga Nusantara etnis Cina. Hein de Weit dan Hien No merupakan citra baru generasi Indonesia yang meneruskan peziarahan generasi Indonesia sebelumnya yang melintasi batas-batas pemisah menuju Tanah Terjanji.
Kita akan hidup dimana pun yang menerima kami bukan sebagai seorang Belanda atau Cina, tetapi sebagai manusia. Tempat yang memungkinkan kemungkinan adalah Manado karena Manado dibangun dari percampuran darah Cina, Portugis, dan Spanyol.
Kitab Suci juga mencatat komunitas dan pribadi yang berziarah melintasi garis-garis pembatas yang berpotensi menceraikan komunitas manusia. Bangsa Israel dalam kitab suci menarik garis pembatas antara mereka dengan bangsa-bangsa lain untuk menjaga keberlangsungan kehidupan mereka. Mereka menyandang identitas sebagai putera-puteri Abraham. Yesus dalam perumpamaan mengenai Orang Samaria Yang Baik Hati (Lukas 10, 29 – 37) menggugat komunitasnya yang mengabaikan identitas yang lain. Yesus mengundang para pendengarnya untuk keluar dari zona kenyamanan mereka. Ia memperkenalkan karakter seorang Samaria untuk muncul ke panggung drama kemanusiaan pada saat kritis untuk menyelamatkan seorang Yahudi yang terancam menderita kematian dini karena menjadi korban kriminalitas.
Yesus menitikberatkan pelayanan-Nya di geografi komunitasnya, namun juga melintasi geografi lainnya. Komunitas Samaria Yesus memasuki daerah mereka ketika mengetahui bahwa ia berziarah menuju geografi komunitas Yahudi (Lukas 9, 51 – 56). Perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia berawal dengan konfrontasi dan berakhir dengan komunio (Markus 7, 25 – 30/Matius 15, 21 – 28). Yesus mengawali dialog sebagai seorang Yahudi yang menarik garis pembatas yang memisahkan diri-Nya dari perempuan itu. Ia menyapa komunitas Israel sebagai putera-puteri Allah dan menyebut yang lain sebagai asu. Saat mengutus para rasulnya, Yesus mengingatkan mereka, “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat” (Matius 10, 6).
Perempuan itu berdiri dihadapan Yesus sebagai pribadi berbeban ganda karena ia seorang perempuan Yunani. Ia menggunakan stigma yang dikenakan Yesus kepadanya untuk mengoreksi pandangan sempit Yesus akan komunitas dengan identitas lain. Ia menggugat hak eksklusif makan pada anak-anak dan mengajukan hak insklusif bagi anak untuk berbagi makanannya dengan asu. Ia mengundang Yesus untuk mempersilakan asu memasuki tempat barunya di dalam rumah dan meninggalkan rumah lamanya di kubangan sampah.
Clara dan para korban lain berdiri dalam posisi sepadan dengan perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Mereka menggugat Gereja, komunitas murid Yesus, dengan pertanyaan senada yang diajukan perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia itu. Kehidupan mereka berada dalam bahaya menderita kematian dini jika masyarakat terus-menerus mendehumanisasikan mereka sebagai asu. Mereka mengundang komunitas kristiani untuk melintasi garis pembatas mereka untuk menyelamatkan para korban tak bersalah dalam masyarakat. Felix Wilfred mendeskripsikan Allah dalam agama Kristiani sebagai ‘sahabat seperjalanan dalam pembentukan identitas komunitas tanpa identitas.’ Allah terlibat aktif dalam periode pasca perbudakan di Mesir untuk membangun kembali simbol dan identitas komunitas yang pernah dihilangkan rezim kriminal. Sebaliknya, rezim otoriter terus-menerus membusukkan identitas bersama sebagai bangsa. Allah menghendaki keragaman dan perbedaan indentitas justru menjadi pilar persaudaraan dalam kehidupan bersama (communion of communities).
Allah Kehidupan Membangun Jejaring Perjumpaan
Penulis mengawali diskusi dengan mendengarkan Clara yang mengajukan dua pertanyaan eksistensial: Siapa aku? Dimana Aku saat ini? Clara mengklaim kembali dirinya sebagai manusia dan menolak perendaha dirinya sebagai asu. Dalam tragedi kemanusiaan Mei, Clara menyandang beban ganda sebagai warga Indonesia beretnis Cina dan perempuan. Ia tak sekedar mengalami hidup dalam tepian masyarakat, tetapi sudah ditendang keluar dari masyarakat. Ia bergumul dengan problem kehidupan dan kematian, dan jawaban kita terhadap pertanyaannya akan menentukan masa depan kehidupannya dan mereka yang lain. Ia menuntut pemerintah Indonesia untuk memandang pluralitas sebagai kekayaan bangsa. Warga Nusantara etnis Cina dalam masa kolonial Belanda menderita stigma karena tuduhan mengobarkan pemberontakan dan Warga Indonesia etnis Cina di bawah era Orde Baru menderita stigma sebagai penyebab ketidakadilan ekonomi dan kehidupan yang terpisah dari kelompok masyarakat lain.
Clara melukis sebuah Indonesia baru yang memperlakukan mereka yang tidak memiliki identitas sebagai pribadi, dan membangun persaudaraan antar beragam kelompok identitas. Sayangnya, pemerintah Indonesia mengabaikan relevansi pertanyaannya. Tragedi Mei menciptakan paranoia sosial, yang terungkap dalam kalimat ‘Aku kapok jadi non-pri’ atau ‘Indonesia adalah masa laluku.’ Ribuan warga Indonesia etnis Cina akhirnya mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan Indonesia pasca-tragedi Mei. Jutaan warga Indonesia etnis Cina mengambil keputusan untuk tetap hidup di Indonesia. Mereka keluar dari garis pembatas pecinan, sarana menjaga keberlangsungan hidup di periferi, dan mengundang bangsa Indonesia untuk mencabut garis-garis pembatas yang merusak kehidupan bersama.
Pertanyaan Clara menghantar penulis pada dua pertanyaan teologis penting: Siapa Allah? Allah berpihak kepada siapa? Allah menjumpai Clara, representasi pribadi dan komunitas yang mengalami ancaman kematian dini, sebagai Allah kehidupan. Ia mengundang kita untuk menyediakan tempat peristirahatan sementara bagi warga Indonesia etnis Cina yang hidup dalam ketakutan pasca-tragedi. Allah juga memanggil kita untuk mengunjungi para korban perkosaan massal dan membela kasus mereka demi keadilan. Ia mengundang kita untuk menamai illah-illah anti-kehidupan di Indonesia yang menyerang kehidupan pribadi atau komunitas yang tak bersalah. Kita harus menolak illah diskriminasi rasial yang menggagahi kemanusiaan warga Indonesia etnis Cina dalam tragedi Mei 1998.
Yesus menawarkan visi baru keluarga umat manusia yang mempersilakan keragaman dan perbedaan. Ia sendiri melukis ulang identitasnya sebagai Mesias Yahudi yang ternyata mengucilkan perempuan Yunani dari bangsa Siro-Fenisia dari jangkauan karya penyelamatan Allah. Ia menjadi pelintas garis batas yang menceraikan manusia dan mengundang masyarakat kita untuk melintasi garis-garis batas, meskipun kelompok-kelompok identitas kemungkinan mengucilkan kita. Ia mengundang kita untuk menciptakan ruang kehidupan bagi kelompok-kelompok non-identitas yang hidup di tepian, bahkan di luar masyarakat. Ia mengundang kita untuk menyebut diri kita ‘sebagai pelintas batas yang hidup diantara identitas-identitas lain tanpa melacurkan kepribadian kita.’ Persaudaraan antar kelompok-kelompok identitas sulit tercipta karena kita memeluk illah diskriminasi dalam kehidupan kita.
Seperti Clara, penulis mengawali refleksi teologis atas tragedi kemanusiaan Mei dengan kalimat patah-patah dengan banyak jeda air mata. Paguyuban keluarga korban mengundang penulis untuk duduk dekat dengan mereka agar penulis dapat mendengarkan tuturan penderitaan mereka. Mereka seringkali kehilangan kemampuan untuk menyusun pengalaman mereka ke dalam kalimat yang tertata. Mereka memanggil penulis untuk mengartikulasikan suara hening mereka. Penulis juga menyadari tanggung jawab menjadi pendengar (Sabda) Allah yang menjumpai para korban sejarah dalam kitab suci.
http://imgsrv.kcbs.com/image/kcbs/UserFiles/Image/uno_clo.jpg