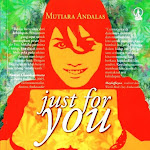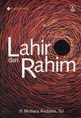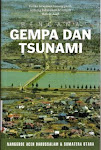Nota Bene:
Naskah ini sedianya akan diterbitkan oleh sebuah majalah Sekolah Menengah Pertama Keluarga di Kudus. Terima kasih atas kesediaan sekolah untuk menerbitkan naskah ini.
Habis Gelap (Kapan) Terbit Terang
Oleh Mutiara Andalas, S.J.[1]
Kartini merupakan pahlawan nasional perempuan yang dekat dengan dunia remaja saya. Original soundtrack ‘Ibu Kita Kartini’ yang selalu berkumandang pada peringatannya senantiasa menggetarkan hati saya. Ia salah satu pahlawan kebangkitan perempuan, bahkan nasional. Waktu duduk di sekolah menengah pertama, saya berhasrat sekali membaca surat-suratnya dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Keinginan itu baru kesampaian sekitar dua puluh tahun kemudian. Tangan saya gemetaran saat membaca gagasan-gagasan pendidikannya. Habis gelap, kapan terbit terang?
Habis Gelap Terbitlah Terang sebenarnya bukan bacaan pertama saya tentang kehidupan Kartini. Marianne Katoppo, seorang novelis perempuan, mengundang saya untuk mengungkapkan kekaguman, tanpa jatuh dalam pemberhalaan terhadapnya. Sekolah Kartini pada kenyataannya bukan sekolah pertama bagi para perempuan
Burung Kecil Terbang Jauh
Kartini lahir sebagai anak seorang priyayi Jawa. Pribadi-pribadi yang dekat dengan hidupnya menggambarkan Kartini belia sebagai burung kecil berusaha keluar dari sarang dan terbang. Pada masa itu masyarakat Jawa memiliki norma berperilaku yang
Sebagai anak priyayi Jawa, Kartini mendapat kesempatan istimewa untuk mengecap pendidikan dasar di sekolah Belanda. Ia juga menerima les tambahan pada sore harinya. Pada masa itu sebagian keluarga priyayi masih mengabaikan pendidikan bagi anak-anak perempuannya. Orang tua Kartini memberikan hak pendidikan yang lebih setara kepada semua anaknya. Mereka mengizinkan Kartini dan saudara-saudarinya untuk berkomunikasi dengan mereka secara akrab. Disamping pendidikan formal, orang tuanya juga memperkenalkan Kartini dengan kehidupan rakyat jelata. Ia mengajak puterinya untuk mengunjungi para petani baik pada masa-masa paceklik maupun panen raya.
Saat menginjak usia dua belas tahun, Kartini memasuki masa pingitan sambil menanti hari pernikahannya. Ia berhenti dari bangku sekolah dan tinggal di rumah. Ia menghormati keputusan ayahnya. Meskipun demikian, Kartini mendapat kebebasan untuk belajar mandiri di kamarnya. Kartini menggambarkan masa-masa pingitan sebagai pengalaman neraka karena ia dikunci dari dunia luar. Kartini melihat celah dunia luar dari kamarnya saat ia berkenalan dengan Ovink-Soer, istri dari asisten Residen Jepara. Kartini remaja terpesona dengan keterpelajaran Ovink-Soer dan perhatiannya pada hak-hak perempuan. Ovink-Soer pernah mengajukan pertanyaan yang membuat burung kecil itu memandang jauh keluar kamarnya, “Apa yang ingin engkau raih saat engkau beranjak dewasa?”
Kartini menyingkap situasi para saudari perempuannya yang hampir tak pernah mengajukan pertanyaan mengenai cita-cita kehidupannya. ‘Kalaupun perempuan Jawa memiliki cita-cita, hanya satu cita-citanya, yaitu menanti laki-laki yang disetujui orang tua untuk meminangnya.” Ia melihat jurang yang memisahkan cita-cita dan kesempatan untuk menggapainya. “Pertanyaannya bukan apakah perempuan menginginkannya, tetapi apakah perempuan boleh melakukannya.” Kartini memasuki episode baru sebagai pejuang perikemanusiaan perempuan. Ia berharap para perempuan dapat merealisasikan cita-citanya. Ia melawan tatanan masyarakat tradisional yang memenjarakan hidup perempuan dan membiarkan penderitaan sebagai warisan turun-temurun yang dibebankan pada bahu perempuan.
Melawan Perendahan Perempuan
Kartini mulai menyadari bahwa kegelapan menyelimuti kehidupan perempuan. Perempuan kehilangan kepribadiannya dalam masyarakat feodal. Ia sekedar menjadi harta keluarga yang kemudian beralih menjadi harta suami dengan perkawinan. Masyarakat patriarkal dari luar menawarkan tatananan kehidupan bersama. Ia sejatinya merusak tatanan kehidupan bersama karena menggagahi kehidupan perempuan. Kartini menggugat tatanan masyarakat feodal dan patriarkal itu saat memasuki jenjang perkawinan. Ia menempatkan diri sebagai pribadi yang bermartabat dihadapan suaminya. Ia tetap mencantumkan nama dirinya sebagai tanda kemerdekaan. Ia membagikan cita-cita menciptakan dunia yang lebih manusiawi bagi perempuan kepada suaminya.
Sebagai korban dari praktek perkawinan poligami, Kartini melawan praktek poligami karena merendahkan martabat perempuan. Ia juga prihatin dengan para perempuan pribumi yang mendapatkan pendidikan yang mencerahkan dari Eropa, namun memilih hidup dalam poligami. “Kita tidak dapat tutup mata bahwa perempuan yang dinikahi secara resmi oleh suami itu tak ada. Perempuan itu adalah pribadi dan ia saudara perempuan kita.” Ia menggugat pandangan bahwa laki-laki memiliki martabat lebih jika ia melangsungkan praktek poligami tanpa suara protes dari para perempuannya. Ia menangkap pesan serupa saat membaca kehidupan Fatimah, puteri Nabi Muhammad.
“Suatu kali suaminya Fatimah membawa seorang perempuan ke rumahnya untuk menjadikannya sebagai istri baru. Nabi menanyakan peristiwa itu kepada puterinya dan puterinya pada awalnya tidak menunjukkan tanda protes. Nabi kemudian memberikan sebutir telur mentah kepada puterinya dan Fatimah menaruhnya telur itu di dekat hatinya. di dekat Nabi kemudian mengambil kembali telur kembali dan telur itu telah masak. Saat Fatimah bersandar pada pohon pisang, daun-daunnya segera mengering dan pohon itu akhirnya terbakar.”
Martabat Pendidikan
Kartini pada awalnya belum memikirkan untuk mendirikan sekolah untuk meningkatkan martabat perempuan di sekitarnya. Ia kemudian menyadari bahwa kegiatan pendidikan merupakan jalan menuju masyarakat yang lebih demokratis dan setara. Ia berharap pendidikan bagi perempuan pribumi akan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat pribumi. Perempuan dapat menjadi pribadi sempurna tanpa kehilangan martabatnya. Pendidikan intelektual hendaknya berjalan berdampingan dengan perkembangan moral. Dalam esai Educate the Javanese, Kartini menyingkapkan subjek pendidikan yang diarahnya.
“Sebagai langkah pembuka, didiklah para perempuan dari kalangan ningrat. Mereka akan menyebarkannya kepada rakyat. Jadikan mereka menjadi ibu yang cakap, bijak, dan baik dan mereka akan menyebarkan terang diantara masyarakat.”
Kartini menampik tudingan bahwa kurikulum pendidikannya melunturkan identitas murid sebagai pribadi Jawa. Kebudayaan Eropa menawarkan gagasan kasih dan keadilan kepada masyarakat Jawa. Kartini mengakui pengaruh nilai-nilai ini yang berjumpa dengan darah Jawa dalam tubuhnya.
"Kami tak pernah berniat menjadikan para murid kita setengah Eropa atau Jawa. Pendidikan liberal ini pertama-tama bermaksud menjadikan mereka sungguh-sungguh pribadi Jawa, membangunkan kecintaan mereka pada bangsa dan negara dengan mata dan hati yang terbuka untuk melihat keindahan dan kebutuhan mereka. Kami ingin membagikan kekayaan kebudayaan Eropa, bukan untuk menggantikan menghapus, atau meredupkan kebudayaan mereka sendiri.”
Akses pendidikan bagi perempuan telah melewati lokasi-lokasi yang pernah dibayangkan Kartini pada zamannya. Perendahan martabat perempuan masih berlangsung dalam banyak sisi kehidupan masyarakat. Partisipasi dalam ruang politik, kesetaraan tanggung jawab dalam mengelola keluarga, perlindungan perempuan dari kekerasan di ruang domestik dan publik membutuhkan kehadiran kartini-kartini muda. Aktivitas pendidikan bermartabat karena membantu siswa-siswi didik untuk menjadi burung-burung muda yang terbang menyuarakan kemanusiaan (SELESAI).
[1] Rohaniwan Katolik yang menulis buku Kesucian Politik: Agama dan Politik di tengah Krisis Kemanusiaan (