 Mengeja Abjad Air Mata
Mengeja Abjad Air MataBab ini dalam pandangan saya merupakan bagian terpenting dari buku. Saya sekaligus mengakui sejak awal bahwa bagian ini merupakan bagian yang tersulit. Tantangan utama adalah mempersilakan korban dan keluarga korban untuk mengisahkan penderitaan mereka sendiri. Sebagian korban memilih kita untuk mengisahkan penderitaan mereka. Tantangan kita adalah mengisahkan kisah mereka dengan tetap mempertahankan kepemilikan kisah pada mereka. Tantangan ini menjadi semakin jelas ketika kita harus mengisahkan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau kehilangan orang-orang terkasih mereka dalam tragedi Mei – Semanggi 1998. Setiap panulisan ulang atau penerjemahan kisah orang lain senantiasa mengandung bahaya pengkhianatan.
Ivone Gebara, teolog kristiani perempuan dari Brasil, menawarkan jalan keluar brilian atas kesulitan saat berhadapan dengan problem penerjemahan dan representasi. Solidaritas dengan hidup korban mengatasi, meskipun tidak secara tuntas, kesulitan-kesulitan tersebut di atas.
Cara yang lebih dipilih untuk mengekspresikan pengalaman perempuan akan
kejahatan adalah mempersilakan perempuan untuk mengisahkan pengalaman mereka
sendiri. Mereka, termasuk laki-laki, yang menyaksikan kejahatan terhadap
perempuan kadang-kadang memiliki kemungkinan untuk mengisahkannya. Kenyataannya
sebagian laki-laki yang peka, dekat, dan mendukung perempuan mampu
mengekspresikan pengalaman saudarinya secara mendalam. Mereka mampu, karena
kemanusiannya, tergerak oleh tragedi perempuan yang menjadi korban kejahatan.
Mereka mampu merasakan tubuh saudari mereka diremukkan kejahatan meski mereka
memiliki tubuh yang berbeda secara biologis dan kultural.[1]
Pengalaman korban tak selalu terungkapkan secara artikulatif. Dalam kasus korban meninggal di supermarket dalam tragedi Mei, kita sering menemukan spasi panjang antar kalimat keluarga korban. Tak jarang kita berhadapand engan spasi panjang antar tangisan keluarga korban. Kita harus mengakui bahwa kita sering mengabaikan bahasa air mata atau kesenyapan. Kisah mereka sebagian terekam baik, sebagian terekam dalam ingatan para relawan yang mendampingi mereka. Kita tidak hanya mengisahkan penderitaan korban, tetapi juga berusaha setia dengan bahasa keluarga korban. Kita percaya bahwa bahasa keluarga korban, betapa pun terbatasnya, memiliki kuasa untuk sampai kepada kebenaran. Tugas utama kita adalah membantu pembaca dengan menempatkan kisah keluarga korban dalam kronologi waktu.
Dalam kasus kekerasan seksual, kisah langsung korban perempuan berada di titik nol. Data yang tersedia mengenai mereka berasal dari saksi korban. Kesaksian mereka mengenai keberadaan korban kekerasan seksual dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998 tersedia kepada masyarakat, baik dalam laporan resmi maupun dalam sastra. Kita juga menyadari bahwa telah terjadi diskusi sangat ramai mengenai minimnya suara korban langsung untuk membongkar fakta atau dakwaan kebohongan mengenai kasus mereka. Ketidakhadiran sebagian besar korban kekerasan seksual mengakibatkan publik mengalami keraguan, bahkan sebagian mengalami ketidakpercayaan terhadap kasus mereka. Minimnya akses langsung kepada korban menyebabkan kasus kekerasan seksual menjadi kontroversial, tetapi sekaligus marginal.
Buku ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998. Kita menerangi kasus ini dari kasus perkosaan di Nanking, Bosnia, dan Rwanda. Kesulitan serupa dihadapi di zona-zona konflik itu, bahkan yang kasus-kasus kekerasan seksualnya berada dalam skala lebih massal. Kita akan terkejut dengan penemuan fakta di lapangan bahwa kekerasan seksual biasanya kurang mendapat perhatian di ruang hukum dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan lainnya. Pengusutan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dalam situasi konflik politik merupakan fenomena baru dalam diskusi hak asasi manusia. Hukum sendiri belum memiliki perangkat yang memadai untuk menangani kasus ini. Persoalan terentang dari keragaman data korban, psikologi korban pasca-kekerasan seksual, hingga belum tersedianya perangkat hukum yang sensitif gender terhadap kesaksian korban dan saksi korban.
Monolog menjadi pilihan dalam mengisahkan kekerasan seksual dalam tragedi kemanusiaan Mei 1998. Ia memungkinkan kita menempatkan banyak spasi kosong kepada audiens untuk berdialog dengan korban atau saksi korban. Ia memungkinkan kita untuk mendengarkan kesaksian mereka yang tak terkatakan. Ia membuka kemungkinan terbukanya teks baru yang tidak terdapat dalam laporan resmi lembaga negara mengenai kasus itu. Judith Hermann yang mendalami secara khusus mengenai psikologi korban kekerasan seksual menghantar kita untuk memahami kesenyapan dan keterpatahan suara korban hingga penolakan korban atas pengalamannya. Hermann mengundang kita untuk memasuki dunia korban yang seringkali gelap pasca kekerasan seksual dan keterpisahan dari dunia sosialnya.
Kita mendapatkan akses yang kurang lebih lengkap mengenai peristiwa Semanggi 1998. Sebagian keluarga korban mampu mengisahkan sendiri kisah korban kepada publik. Mereka juga mengajukan tuntutan-tuntutan mereka secara langsung kepada negara. Mereka juga menandai lahirnya pejuang hak asasi manusia yang lahir dari paguyuban korban dan keluarga korban. Maria Katharina Sumarsih dan Suciwati Munir, dan beberapa keluarga lainnya yang tergabung dalam aliansi korban kekerasan negara mengambil peziarahan politik dari ruang domestik. Seperti Rigoberta Menhu dan ibu Plaza de Mayo, mereka memahami politik dalam relasi intrinsik rakyat dan kehidupannya.
Sebagaimana dituturkan Maria Katharina Sumarsih, aktivitasnya seringkali digerakkan spontanitas dan sering tak terencana. Aktivitas politiknya bersumber dari jasad puteranya yang meninggal dunia dalam peristiwa Semanggi. Hal yang sama dialami oleh Suciwati Munir. Ia menemukan kekuatan dalam perjuangan ahak asasi manusia karena perjumpaannya dengan mereka yang mengalami penderitaan dan menyediakan diri mereka dampingi. Meskipun ia aktif dalam aktivitas politik, Suciwati tetap menempatkan anak-anaknya sebagai prioritas utama. Sebagian politikus barangkali memandang mereka berada dalam posisi sangat lemah karena kepolosan mereka. Saya sendiri berada dalam posisi berseberangan dengan pandangan ini. Kesederhanaan mereka justru memberi nilai plus yang tak boleh hilang dalam kegiatan politik mereka. Mereka mengajukan pertanyaan, “Mengapa kalian mengambil kehidupan orang-orang terkasih dalam hidup kami?”
Ketika Jon Sobrino, teolog pembebasan terkemuka dari El Salvador, berbicara mengenai kesucian primordial (primordial saintliness) rakyat tersalib, tak sedikit akademisi menuduh Sobrino jatuh pada romantisasi terhadap hidup rakyat miskin dan menderita. Tulisan ini tidak melakukan penyuntingan dengan tujuan memutihkan hidup korban atau keluarga korban. Kita akan menemukan berbagai pengalaman manusiawi, seperti ketidakberdayaan, kemarahan, kepentingan diri, kelelahan, bahkan keputusasaan. Dari pribadi-pribadi real inilah undangan untuk menghormati kehidupan korban dan manusia Indonesia lahir.
[1] Ivone Gebara, Out of the Depths: Women’s Experience of Evil and Salvation (Minneapollis: Fortress Press, 2002), 15 – 16.

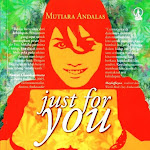
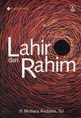




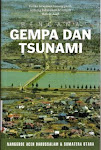












No comments:
Post a Comment