 Rekonsiliasi Semu
Rekonsiliasi SemuMengaburkan Kebenaran
Oleh Arief Priyadi[1]
Bagi kami, bagian dari keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, kata “rekonsiliasi”, “damai”, “islah” atau apa pun istilah lainnya yang bermakna senada dan sempat tersosialisasikan, merupakan hal yang amat sensitif sekaligus menjadi beban pemikiran. Dalam kenyataan akhir-akhir ini, terhadap berbagai kasus seperti berbeda pendapat, berkonflik, tindak kriminal, tindak korupsi, pelanggaran HAM dan berbagai kasus lainnya cenderung ditawarkan upaya rekonsiliasi. Jadi, bukan hanya terhadap kasus-kasus perdata saja yang diupayakan penyelesaian melalui mediasi, melainkan telah merambah ke kasus-kasus kriminal kendatipun yang terancam adalah kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan pihak yang bersengketa. Di balik sensitivitas tersebut, terbayang di dalam benak kami bahwa rekonsiliasi yang diupayakan itu tidak lebih dari upaya “menyembunyikan soal,” disertai target di mana publik dibiarkan tak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah.
Oleh Arief Priyadi[1]
Bagi kami, bagian dari keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, kata “rekonsiliasi”, “damai”, “islah” atau apa pun istilah lainnya yang bermakna senada dan sempat tersosialisasikan, merupakan hal yang amat sensitif sekaligus menjadi beban pemikiran. Dalam kenyataan akhir-akhir ini, terhadap berbagai kasus seperti berbeda pendapat, berkonflik, tindak kriminal, tindak korupsi, pelanggaran HAM dan berbagai kasus lainnya cenderung ditawarkan upaya rekonsiliasi. Jadi, bukan hanya terhadap kasus-kasus perdata saja yang diupayakan penyelesaian melalui mediasi, melainkan telah merambah ke kasus-kasus kriminal kendatipun yang terancam adalah kepentingan publik dan bukan hanya kepentingan pihak yang bersengketa. Di balik sensitivitas tersebut, terbayang di dalam benak kami bahwa rekonsiliasi yang diupayakan itu tidak lebih dari upaya “menyembunyikan soal,” disertai target di mana publik dibiarkan tak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah.
Bagi kami, Tragedi Semanggi Berdarah 13 November 1998 yang menewaskan anak kami B.R. Norma Irmawan (Wawan), adalah sebuah memoria passionis - kenangan duka yang menggugat. Mungkin terlalu berlebihan ketika kami memiliki persepsi bahwa Tragedi Semanggi adalah merupakan bagian dari sejarah, yang kiranya dapat digambarkan sebagai sebuah narasi perjuangan manusia untuk merenda ingatan, untuk menampik amnesia atau pelupaan massal atas jejak berbagai peristiwa yang melintasinya. Dan kini, setelah hampir satu dekade tragedi berdarah itu berlalu, perjuangan yang dilakukan oleh kami keluarga korban dapat diibaratkan sebagai rangkaian upaya retroaktif dalam melawan historia abscondita - melawan sejarah yang kelam, yang seakan mencoba menggembok rahasianya di balik dinding-dinding peristiwa masa lalu. Bagi kami, persepsi ini penting adanya, paling tidak untuk mengimbangi kenyataan bahwa Tragedi Semanggi tak kunjung mendapat pengakuan politik sebagai kejahatan HAM berat sehingga belum juga menghampiri ruang pengadilan untuk dikuak kebenarannya.
Ketidakjelasan proses hukum atas kasus ini menjadi pemicu munculnya perasaan pengabaian, bahkan peremehan terhadap persoalan yang bagi kami hakiki karena menyangkut pribadi yang kami kasihi, kami cintai, dan bukan semata perkara masa lalu atau pun statistik korban perubahan. Menggelindingnya konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada tahun 2000 berupa wacana, yang kemudian menjelma dalam wujud Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diinisiatifi oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat Elsam bersama Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2003, dan sempat berhasil menjadi sebuah Undang-Undang pada tahun 2004, namun berujung pada pembatalan berlakunya oleh Keputusan Mahkamah Konsitusi pada tahun 2006, sempat mencemaskan sebagian keluarga korban pelanggaran HAM. Bagaimana tidak?
Pertama, konsep tersebut apabila dirunut ke belakang tersimpul semacam konspirasi politik untuk mengubur peristiwa masa lalu; Kedua, melalui konsep tersebut kebersamaan baik antar keluarga korban maupun antar lembaga swadaya masyarakat pendamping menjadi rentan pecah - ada yang pro atau mendukung, dan ada yang kontra atau menolak terhadap konsep rekonsiliasi tersebut; Dan ketiga, dari sisi waktu, hal itu sangat merugikan perjuangan keluarga korban dalam menuntut kebenaran dan keadilan. Sekian waktu terbuang dan konsentrasi perjuangan menuntut keadilan melalui proses peradilan pun menjadi agak buyar, sebab hampir di semua lini penantiannya menjadi terfokus pada kehadiran Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan tak pelak lagi, kondisi yang demikian dimanfaatkan oleh aparat atau instansi yang berkompeten menangani kasus untuk mengulur-ulur waktu, misalnya melalui kata-kata: “Tunggu saja nanti terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi!”
Patut diduga bahwa konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dipersiapkan sejak awal oleh sisa-sisa penguasa Orde Baru melalui jalur legislasi, di mana mereka menguasai lembaga tersebut. Hal itu nampak dari tercantumnya konsep itu di dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2000, yang dalam sebuah klausul menyatakan: “… untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi … “. Sebagai langkah lanjut, konsep rekonsiliasi tersebut diturunkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana Pasal 47 menyatakan: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Juga secara eksplisit disebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dibentuk dengan undang-undang.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu telah ditempuh secara bertahap atau sistematis, dan dimulai sejak awal masa transisi. Dengan melihat tahapan tersebut dan bila direfleksikan dengan kondisi perpolitikan di negeri kita di masa transisi, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu merupakan setting politik dan hukum. Setting politik identik dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu rekonsiliasi versi sepihak, dan setting hukum identik dengan fungsi pengamanan atau pengawalan bagi tercapainya tujuan tersebut.
Dalam perjalanan waktu selama proses pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, setting politik dan hukum tersebut nampak berjalan tanpa hambatan. Hal ini disebabkan Indonesia fase transisional sama sekali belum terkukuhkan batas yang jelas dan tegas antara rezim lama yang telah berkuasa selama tiga dekade dengan pemerintahan baru yang menggantikannya. Transisi telah berlangsung dengan pola transplacement (transplasi, cangkokan), bukan dengan pola replacement (penggantian total). Akibatnya, pemerintahan pengganti berada dalam kerangkeng sistem masa lalu di mana praktek kenegaraan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh politik rezim lama. Bahkan kekuatan rezim lama masih mempunyai kekuatan mengontrol proses transisi, termasuk mengontrol sikap pemerintahan baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masa lalu di antaranya mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Sehingga mudah diduga bahwa setting politik dan hukum itu bukan saja akan bermuara pada terwujudnya rekonsiliasi melainkan juga impunity (impunitas), yaitu pembiaran atau terbebaskannya seseorang dari sanksi (bahkan tuntutan) hukum dan politik atas tindakan yang dilakukannya, dan bukan karena dibenarkan oleh hukum.
Sosialisasi secara intensif mengenai pilihan sikap bagi korban/keluarga korban melalui diskusi, seminar dan sebagainya nampaknya juga menjadi bagian penting dari tahapan yang ditempuh oleh pihak-pihak yang ingin menggolkan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pilihan sikap itu meliputi: Pertama, tidak melupakan peristiwa masa lalu dan tidak memaafkan terhadap pelaku; kedua, tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan; ketiga, melupakan dan memaafkan; dan keempat, tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan. Di antara empat pilihan sikap itu ada dua yang diakomodasi oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu “tidak melupakan dan tidak memaafkan”, yang dituangkan di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan pengadilan HAM dan mekanisme penyelesaian kasus. Juga, sikap “tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan” dituangkan dalam Pasal 47 mengenai penyelesaian alternatif melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Secara sekilas, penyelesaian alternatif ini seakan-akan memberi jalan keluar atas tersendatnya proses penyelesaian kasus akibat perangkat dan penegak hukum yang masih dikuasai oleh kekuatan rezim masa lalu. Tetapi apabila dirunut lebih jauh, penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini justru akan menciptakan impunitas secara terselubung. Melalui ketentuan tentang mekanisme atau prosedural cukup memberikan gambaran tentang impunitas, baik apabila misi itu berjalan mulus maupun apabila mengalami hambatan. Berkenaan degan mekanisme tersebut dapat dingkat beberapa catatan: Pertama, seandainya misi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berjalan mulus, dalam arti pengungkapan kebenaran bisa berlangsung - di mana pelaku bersedia mengakui kesalahannya, korban/keluarga korban bersedia memaafkan, pelaku mendapatkan amnesti, kemudian kedua pihak menandatangani kesepakatan damai sehingga tidak dibenarkan lagi adanya saling gugat - maka berarti rata-lah jalan bagi terwujudnya rekonsiliasi yang menghantar pada tercapainya hasrat agar pelaku terbebaskan dari sanksi hukum, yang berarti pula terjadi impunitas secara terselubung.
Kemudian kedua, sekiranya misi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gagal, taruhlah misalnya korban/keluarga korban tidak bersedia memaafkan, atau pelaku dinilai mengungkap peristiwa secara tidak jujur atau bahkan tidak bersedia mengakui kesalahannya, maka menurut mekanisme dalam Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kasus termaksud kemudian dilimpahkan ke Pengadilan HAM ad hoc. Di sini kasus akan dihadapkan pada sebuah persoalan yaitu apakah pengadilan termaksud bisa dibentuk atau tidak, ketika kondisi politik masih didominasi oleh atau masih berpihak pada kepentingan rezim lama. Bila Pengadilan HAM ad hoc tidak bisa dibentuk, sehingga kasus tetap menggantung, berarti pelaku tetap selamat, dan dalam hal ini terjadi impunitas terselubung pula. Seandainya kasus tersebut bisa diproses di Pengadilan HAM ad hoc, pun masih menyisakan pertanyaan sejauh mana dapat dijamin bahwa proses itu benar-benar berlangsung secara obyektif dan profesional, tanpa rekayasa? Misalnya, apakah dapat dijamin bahwa jaksa tidak bakal mengajukan tuntutan bebas bagi pelaku? Bila proses peradilan sarat dengan praktek rekayasa, apalagi berakhir dengan membebaskan pelaku dari tuntutan bahkan sanksi hukum, maka pada dasarnya telah terjadi impunitas terselubung.
Meskipun dalam Undang-Undang tentang Komisi Kebenanran dan Rekonsiliasi dinyatakan bahwa pengungkapan kebenaran merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menuju rekonsiliasi, namun justru menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan Komisi tersebut. Sikap ambiguitas Komisi nampaknya terdorong oleh keinginan menyelesaikan kasus-kasus masa lalu secara win-win solution. Keberpihakannya pada pelaku nampak pada tiadanya unsur “penjeraan”, dan tersedianya peluang untuk mendapatkan amnesti (sebuah klausul yang bertentangan dengan kaidah internasional). Sementara itu keberpihakannya pada korban/keluarga korban terungkap hanya berupa iming-iming pemberian kompensasi dan restitusi, yang sebenarnya secara leksikal merupakan penghalusan dari istilah “ganti rugi” atau “imbalan” bagi korban/keluarga korban yang bersedia memberikan maaf/pengampunan.
Dengan demikian, sensivitas korban dan keluarga korban terhadap kehadiran ide rekonsiliasi kiranya cukup beralasan, terlebih-lebih mengingat kondisi riil perpolitikan di Indonesia. Melalui konsep rekonsiliasi, pelaku cenderung diuntungkan karena terbuka kemungkinan mendapatkan peluang yang bisa dimanfaatkan. Selama pelaku masih dalam kondisi prima baik secara finansial maupun dukungan kekuatan riil, maka akan dengan mudah mengambil langkah defensif melalui celah-celah aturan yang ada. Sebaliknya, rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban akan terpinggirkan. Bisa pula terjadi pemanfaatan kondisi korban/keluarga korban yang pada umumnya amat rentan untuk ditekan dan diminta “berkorban dan berkorban lagi” melalui jargon demi rekonsiliasi dan masa depan bangsa.
Di sejumlah negara seperti Argentina, Uruguay, dan Afrika Selatan, lahirnya komisi semacam itu atas dorongan rasa empati kepada korban, dan bukan atas dasar wawasan otoriter, sehingga tujuan pembentukannya lebih menitikberatkan kepentingan korban. Sedangkan di Indonesia, kecenderungan memberikan peluang bagi pelaku pelanggaran HAM berat untuk dimaafkan justru lebih dominan. Orientasi yang mengedepan dalam setiap tahapan menggoalkan rekonsiliasi adalah pengkondisian bangsa untuk menyongsong masa depan. Orientasi demikian tentu akan mewarnai implementasinya, sehingga dikhawatirkan konsep rekonsiliasi lebih ditujukan pada terwujudnya rekonsiliasi secara formal, dan bukan menyentuh hakiki. Itulah sebenarnya sekilas kerawanan impunitas di lingkup konsep. Kerawanan di tingkat pelaksanaan bisa muncul ketika jaring impunitas bermain memanfaatkan celah kelemahan peraturan. Selama ini telah terbukti bahwa teknis-teknis hukum selalu dijadikan instrumen untuk menghambat penyelesaian kasus. Demikian pula dengan kelemahan perangkat dan aparat hukum yang tidak mampu atau tidak mau memprosesnya sehingga kasus bisa menggantung, lagi-lagi merupakan incaran strategis.
Dengan demikian, dilihat dari perspektif kepentingan korban dan keluarga korban, konsep rekonsiliasi sangat tidak menguntungkan, apalagi bila landasan konsep itu melampaui batas moral yaitu: Pertama, berangkat dari kondisi korban dan keluarga koprban yang lemah dan mudah dimanfaatkan. Misalnya melalui bujukan bahwa hukum positif tidak bakal mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, begitu pula keadilan sejati merupakan hal yang tidak bakal bisa diraih; Kedua, korban dan keluarga korban terbuat tak sadar untuk ikut terlibat dalam proses pemutihan kasusnya, serta turut andil dalam mewujudkan impunitas terselubung; Dan ketiga, intervensi terhadap sikap korban dan keluarga korban melalui pemanfaatan kondisinya yang rentan secara ekonomis, politis, dan miskin akan daya tangkal.
Konsep damai, atau rekonsiliasi, yang pernah menjelma dalam Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kini memang telah dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya tertanggal 7 Desember 2006. Namun terhadap konsep rekonsiliasi itu nampaknya masih mendarah daging di benak para pegiat rekonsiliasi. Karena itu tak ayal lagi bila, konon, kini sedang dipersiapkan draft baru untuk konsep semacam. Bagi korban dan keluarga korban, apakah hal itu merupakan ancaman terhadap perjuangan dalam menuntut kebenaran dan keadilan melalui proses peradilan, maka jawabannya adalah: walahu’alam - kami tidak tahu. Dan sampai kini, kami keluarga korban pelanggaran HAM masih tetap dengan tuntutan, agar kasus pelanggaran HA berat masa lalu diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc.
[1] Oruangtua dari B.R. Norma Irmawan yang akrab disapa Wawan, korban meninggal dalam Tragedi Semanggi Berdarah, 13 November 1998.

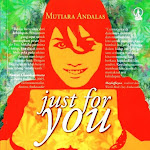
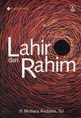




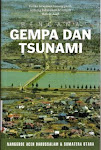












No comments:
Post a Comment