EKOTEOLOGI:
Menebus Firdaus dari Holocaust
Oleh Mutiara Andalas[1]
 Kehidupan ekologi sedang berarak menjauhi Firdaus. Holocaust barangkali merupakan kata yang mampu mewakili gawatnya krisis ekologi saat ini. Manusia bergumul mencari tahu pelaku kerusakan ekologi dan jari telunjuk mereka akhirnya kembali pada diri mereka. Manusia menjadi terdakwa utama dalam perusakan ekologi dan bertanggung jawab dalam menebus ekologi dari bahaya holocaust. Komunitas beriman tak boleh melarikan diri dari tanggung jawab global menebus ekologi. Ekoteologi merupakan sumbangan komunitas beriman untuk menebus firdaus dari holocaust ekologi. Ekoteolog melihat semesta sebagai tubuh Tuhan yang haus penebusan penebusan karena kedosaan manusia menggagahi ekologi hingga ekologi terancam mengalami kematian dini.
Kehidupan ekologi sedang berarak menjauhi Firdaus. Holocaust barangkali merupakan kata yang mampu mewakili gawatnya krisis ekologi saat ini. Manusia bergumul mencari tahu pelaku kerusakan ekologi dan jari telunjuk mereka akhirnya kembali pada diri mereka. Manusia menjadi terdakwa utama dalam perusakan ekologi dan bertanggung jawab dalam menebus ekologi dari bahaya holocaust. Komunitas beriman tak boleh melarikan diri dari tanggung jawab global menebus ekologi. Ekoteologi merupakan sumbangan komunitas beriman untuk menebus firdaus dari holocaust ekologi. Ekoteolog melihat semesta sebagai tubuh Tuhan yang haus penebusan penebusan karena kedosaan manusia menggagahi ekologi hingga ekologi terancam mengalami kematian dini.
Krisis ekologi berderet panjang melintasi batas-batas geografi. Ia juga telah merambah bumi Indonesia hampir tanpa jeda. Pembalakan hutan, pengerukan mineral, gempa bumi, gelombang pasang, dan banjir menyerakkan pertiwi Indonesia dalam skala yang semakin mengkhawatirkan. Lolosnya para pelaku perusakan ekologi dari jerat hukum dan lambannya tanggapan negara terhadap para korban bencana ekologi merupakan penera yang menunjukkan masih rendahnya kepedulian Indonesia terhadap holocaust ekologi. Kita juga menerima dampak krisis ekologi global dalam bentuk desakan dari komunitas dunia untuk memelihara hutan kita sebagai salah satu paru-paru dunia. Krisis ekologi juga mendesak teolog untuk melukis ulang gagasan mengenai Tuhan pencipta dan tanggung jawab manusia dalam penciptaan.
Ciptaan Menebus Ciptaan
Ekoteologi menamai sebuah fokus baru dalam ranah teologi sebagai tanggapan terhadap krisis ekologi. Ia merupakan anak ilmu dalam teologi yang masih membutuhkan eksplorasi akademik untuk mengisi kosa kata baru ini. Ia menandai babak baru dalam dalam relasi antara teologi dan ekologi yang dalam periode sebelumnya telah melahirkan teologi penciptaan dan lingkungan. Kedua teologi pendahulu ini berangkat dari asumsi manusia sebagai pusat ciptaan yang mendapatkan tugas dari Tuhan untuk merawat keutuhan ciptaan (integrity of creation). Ekoteologi melukis ulang kisah penciptaan dan tanggung jawab baru manusia sebagai rekan Tuhan dalam menebus kerusakan ekologi. Ekoteolog mengajukan dakwaan dosa kepada manusia kontemporer yang menggagahi ciptaan-ciptaan lain. Mereka menawarkan budaya ekologi baru yang menuntut komitmen manusia sebagai salah satu ciptaan dalam ekologi untuk membalut luka-luka dalam tubuh ekologi.
Akademisi dan praktisi di bidang-bidang lain membuka mata para teolog terhadap situasi genting ekologi kontemporer. Mereka memberikan sumbangan luar biasa kepada para teolog dalam menggeser fokus pertanyaan teologi dan membidani lahirnya ekoteologi. Pada kesempatan kali ini penulis berfokus pada gerakan ekologi dalam tradisi kristiani.[2] Para teolog yang melibatkan diri dalam diskusi krisis ekologi menggunakan hasil kajian ilmu alam berkaitan dengan sejarah ciptaan dalam alam semesta. Mereka juga menggunakan kajian ilmu-ilmu sosial untuk memotret kebudayaan manusia yang membiakkan perusakan ekologi, dan efek negatif dari teologi penciptaan dan lingkungan yang masih menekankan manusia sebagai pusat ciptaan. yang melahirkan perusakan ekologi. Mereka mengusulkan untuk tidak memisahkan diskusi krisis ekologi dari keadilan ekonomi. Para ekoteolog menyadari diri dengan rendah hati sebagai pendatang belakangan dan berkomitmen untuk melibatkan diri dalam diskusi dan praksis global menebus ekologi dari ancaman kematian dini.

Gereja hingga saat ini barangkali masih menjadi satu-satunya institusi agama yang hampir selalu berada di kursi terdakwa saat pemerhati ekologi berdiskusi mengenai pelaku utama atau figuran dalam kerusakan ekologi. Para pemerhati ekologi mendakwa Gereja sebagai pewaris tunggal budaya patriarki dan menyusun teologi penciptaan dan perawatan lingkungan yang bias patriarki. Teologi penciptaan dan perawatan lingkungan dalam prakteknya membiakkan kerusakan ekologi. Para teolog kristiani hendaknya menempatkan kritik mereka dalam bingkai pengaruh agama kristiani dalam kebudayaan Barat. Studi-studi lanjutan mengenai relasi agama kristiani dengan kerusakan ekologi, terutama kajian feminisme dan poskolonialisme, mencelikkan mata semua komunitas beriman karena virus patriarki juga bersarang dalam komunitas-komunitas beriman lainnya. Persenggamaan patriarki dengan industrialisasi dan kolonialisme membiakkan monster ekonomi yang mengabaikan kelestarian ciptaan. Monster ekonomi ini tak pernah puas dalam menghisap kekayaan ekologi. Ekoteolog tak boleh alpa terhadap para pelaku ekonomi dari level lokal sampai multinasional yang seringkali luput dari pandangan kita saat kita berbicara mengenai krisis ekologi.
Ekoteolog melukiskan kembali kisah penciptaan. Mereka menolak pandangan tradisional yang melihat penciptaan dari tingkatan yang lebih sederhana menuju tingkatan yang lebih sempurna. Dalam bingkai ini manusia menjadi puncak kisah penciptaan. Teologi penciptaan dan perawatan lingkungan dibangun dari bingkai kisah penciptaan ini. Manusia ditempatkan sebagai ciptaan istimewa dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia berelasi dengan ciptaan-ciptaan lain secara piramidal. Mereka tidak hanya menemukan diri mereka berbeda, tetapi juga terpisah dari ciptaan-ciptaan lain. Mereka menaikkan diri sebagai tuan atas ciptaan-ciptaan lainnya. Ia juga merasa mendapatkan penugasan istimewa dari Tuhan untuk merawat ciptaan-ciptaan lain. Mereka dapat mempergunakan atau mengeksploitasi ciptaan-ciptaan lain demi keberlangsungan hidup manusia.
Ekoteolog melukis kisah penciptaan secara kosmosentris. Kisah penciptaan mulai kehadiran ciptaan-ciptaan bukan manusia dan manusia menyusul kehadirannya di planet bumi. Mereka memiliki mekanisme mempertahankan dan memekarkan kehidupan mereka secara lestari. Kehidupan mereka dapat berlangsung sebelum manusia hadir diantara mereka. Manusia menjadi anggota kemudian di planet bumi setelah periode penciptaan sangat panjang. Ekoteolog menolak pencitraan manusia sebagai tuan atas ciptaan-ciptaan lain karena gagasan itu mengingkari kisah penciptaan. Manusia berelasi dengan ciptaan-ciptaan lain tidak dalam relasi hirarkis melainkan relasi lingkaran. Semua ciptaan saling terkait dan tergantung satu sama lain. Ekoteolog menanggalkan citra palsu manusia sebagai tuan atas ciptaan-ciptaan lain. Mereka tetap mengakui peran penting manusia, namun menolak klaim peran utama manusia dalam ekologi.
Ekoteolog berhadapan dengan lukisan penciptaan yang rusak karena sentuhan tangan manusia. Sebagian kerusakan ekologi terpampang jelas dalam mata kita. Kerusakan ekologi besar seringkali justru tersembunyi dari penglihatan mereka. Ekofeminis menawarkan gender sebagai instrumen hermeneutik untuk membongkar para pelaku kejahatan ekologi. Ekofeminisme lahir dari keprihatinan perempuan terhadap krisis ekologi dan perhatian mereka untuk memekarkan persaudaraan dengan alam (communion with nature). Ia hendak membantu kita yang seringkali kebingungan, bahkan tersesat dalam berelasi dengan ciptaan-ciptaan lain.[5] Patriarki, menurut Rosemary Radford Ruether, merusak kemanusiaan perempuan dan alam sepanjang sejarah peradaban. Ruether tanpa ragu menuding para pemeluk patriarki sebagai pelaku utama perusakan ekologi. Dominasi manusia terhadap alam memproduksi kerusakan fatal dalam kehidupan ekologi. Ruether mengusulkan agar perempuan dan laki-laki bertanggung jawab secara setara sebagai wakil Tuhan dalam membela kehidupan ekologi.[6]
Eros manusia menguasai ciptaan-ciptaan lain menjalar keluar dari pagar gender dan spesies. Ia menjulur dan membelit tata ekonomi global. Vandana Shiva, seorang feminis poskolonial, memandang proyek pertumbuhan ekonomi sebagai metamorfose kontemporer dari eros menguasai yang lain. Dunia Ketiga, betapapun cairnya istilah ini, menamai mayoritas warga dunia yang menjadi korban tata ekonomi global yang tidak adil. Para pemeluk proyek pertumbuhan memahami produktivitas sebagai pembiakan komoditas dan laba. Shiva dan para perempuan dari belahan Dunia Ketiga menawarkan pemahaman alternatif terhadap produktivitas sebagai pemekaran kehidupan yang lestari. Mereka melihat ekonomi bergerak ke kutub negatif (maldevelopment). Ekonomi melanggar keutuhan dan keterkaitan antar dunia ciptaan. Ia memandang perempuan dan alam sebagai obyek yang dapat digagahi demi kepentingan produksi. Ekonomi pada akhirnya justru menjadi eksploitasi, ketidakadilan, dan kekerasan terhadap ekologi.[7]
 Tata ekonomi global mengiris dunia dalam belahan negara-negara Selatan dan Utara. Negara-negara Selatan berdiam di tepian ekonomi global, sebaliknya negara-negara Utara bercokol di pusat-pusat ekonomi global. Negara-negara Selatan, betapa pun liatnya mendefinisikan kosa kata ini, menawarkan lensa hermeneutik keadilan ekonomi untuk menera tata ekonomi global dan dampaknya terhadap kehidupan ekologi. Mereka mengangkat tema ekologi sosial karena melihat relasi antara ketidakadilan ekonomi dan kerusakan ekologi. Negara-negara Selatan mengalami penderitaan yang senada dengan ciptaan-ciptaan nonmanusia. Negara-negara Utara memandang negara-negara Selatan sebagai bahan baku ekonomi. Pasar ekonomi global mendorong pertumbuhan di negara-negara pusat ekonomi dengan memproduksi kemiskinan di negara-negara tepian ekonomi. Negara-negara tepian ekonomi harus menanggung buangan limbah, sampah karbon dan radioaktif, hujan asam, penipisan ozon, dan polusi air dari industri negara-negara maju. Kekuasaan politik negara-negara Utara menopang dominasi ekonomi mereka terhadap negara-negara Selatan. Industri militer di negara-negara Utara, menurut Leonardo Boff, memasung kehidupan.
Tata ekonomi global mengiris dunia dalam belahan negara-negara Selatan dan Utara. Negara-negara Selatan berdiam di tepian ekonomi global, sebaliknya negara-negara Utara bercokol di pusat-pusat ekonomi global. Negara-negara Selatan, betapa pun liatnya mendefinisikan kosa kata ini, menawarkan lensa hermeneutik keadilan ekonomi untuk menera tata ekonomi global dan dampaknya terhadap kehidupan ekologi. Mereka mengangkat tema ekologi sosial karena melihat relasi antara ketidakadilan ekonomi dan kerusakan ekologi. Negara-negara Selatan mengalami penderitaan yang senada dengan ciptaan-ciptaan nonmanusia. Negara-negara Utara memandang negara-negara Selatan sebagai bahan baku ekonomi. Pasar ekonomi global mendorong pertumbuhan di negara-negara pusat ekonomi dengan memproduksi kemiskinan di negara-negara tepian ekonomi. Negara-negara tepian ekonomi harus menanggung buangan limbah, sampah karbon dan radioaktif, hujan asam, penipisan ozon, dan polusi air dari industri negara-negara maju. Kekuasaan politik negara-negara Utara menopang dominasi ekonomi mereka terhadap negara-negara Selatan. Industri militer di negara-negara Utara, menurut Leonardo Boff, memasung kehidupan.
Negara-negara Utara memperhatikan krisis ekologi global namun kurang menampakkan kepekaan terhadap kemiskinan dan penderitaan di negara-negara Selatan. Mereka membatasi lingkup perhatian ekologi pada spesies nonmanusia yang terancam mengalami kepunahan dini. Ekologi sosial, menurut Ingemard Hedström, lahir sebagai kritik profetik terhadap peradaban negara-negara maju yang apatis terhadap kemiskinan dan penderitaan. Krisis ekologi tidak hanya mengancam kepunahan dini spesies nonmanusia tetapi juga kematian dini orang miskin. Manusia bersama ciptaan-ciptaan lain akan berarak menuju kepunahan dini jika negara-negara maju menyembah sistem ekonomi yang tidak adil. Leonardo Boff mengutuk negara-negara maju karena mereka memeluk sistem ekonomi yang anti ekologis. Gerakan peduli lingkungan masih mendekati krisis ekologi secara parsial karena menyentuh manusia secara tak langsung. Gerakan ekologi sosial mendekati krisis ekologi dengan memperhatikan masyarakat yang mengalami kemiskinan dan penderitaan yang tidak adil.[8]
Tuhan Menebus Ciptaan
 Ekofeminis mengundang komunitas global untuk terlibat dalam melucuti budaya patriarki yang merusak kehidupan perempuan dan ciptaan-ciptaan nonmanusia. Ekososialis mengusulkan relasi baru antarciptaan melalui tata ekonomi yang memeluk kehidupan orang miskin dan menderita. Ekoteologi lahir dari perjumpaan dengan realitas kerusakan ekologi dan harapan persaudaraan antarciptaan baik dalam sejarah maupun dalam kitab suci. Korban ekologi dan Tuhan pencipta memberikan inspirasi untuk menyusun tata kelola baru yang menebus kerusakan ekologi. Ekoteologi melukiskan kembali relasi kasih antara Tuhan dengan semua ciptaan dan relasi antarciptaan dari tengah-tengah holocaust ekologi. Ia menyingkapkan harapan-Nya untuk memekarkan persaudaraan antarciptaan di bumi. Ia menempatkan manusia, ciptaan yang mampu menangkap rencana penciptaan-Nya, sebagai pemelihara ekologi bumi. Ia mengundang manusia untuk mengenakan kasih Tuhan yang menyapa semua ciptaan di tengah holocaust ekologi.
Ekofeminis mengundang komunitas global untuk terlibat dalam melucuti budaya patriarki yang merusak kehidupan perempuan dan ciptaan-ciptaan nonmanusia. Ekososialis mengusulkan relasi baru antarciptaan melalui tata ekonomi yang memeluk kehidupan orang miskin dan menderita. Ekoteologi lahir dari perjumpaan dengan realitas kerusakan ekologi dan harapan persaudaraan antarciptaan baik dalam sejarah maupun dalam kitab suci. Korban ekologi dan Tuhan pencipta memberikan inspirasi untuk menyusun tata kelola baru yang menebus kerusakan ekologi. Ekoteologi melukiskan kembali relasi kasih antara Tuhan dengan semua ciptaan dan relasi antarciptaan dari tengah-tengah holocaust ekologi. Ia menyingkapkan harapan-Nya untuk memekarkan persaudaraan antarciptaan di bumi. Ia menempatkan manusia, ciptaan yang mampu menangkap rencana penciptaan-Nya, sebagai pemelihara ekologi bumi. Ia mengundang manusia untuk mengenakan kasih Tuhan yang menyapa semua ciptaan di tengah holocaust ekologi.
Perjumpaan manusia dengan ciptaan-ciptaan lain terjadi di bumi. Manusia berelasi dengan mereka di atas pilar kesetaraan yang adil. Kisah manusia menamai ciptaan di taman Firdaus seringkali ditafsirkan sebagai penahlukan manusia terhadap ciptaan-ciptaan lain. Tindakan itu sebenarnya lebih menyatakan pengenalan manusia akan ciptaan-ciptaan lain dan pengakuan manusia akan keberadaan mereka. Eksploitasi manusia terhadap manusia dan ciptaan non-manusia merupakan tafsiran kitab suci yang mengidap bias patriarki. Kisah manusia dan ciptaan-ciptaan lain di taman Firdaus mendorong manusia untuk bertanggung jawab dalam memekarkan kehidupan semua ciptaan. Relasi yang benar antarciptaan memungkinkan semua ciptaan mengalami kasih kreatif Allah. Eksploitasi manusia terhadap ciptaan-ciptaan lain tak hanya merusak relasi ciptaan dengan penciptanya, tetapi juga merusak ekologi. Kisah Tuhan menciptakan dunia mengenal saat jeda. Tuhan mengambil waktu jeda dalam penciptaan untuk melihat kembali kreativitas ciptaan-Nya. Manusia juga memerlukan waktu jeda dalam aktivitas kreatifnya mengelola ekologi untuk memulihkan kerusakan yang dilakukannya.[9]
Holocaust ekologi terjadi ketika manusia menyerakkan karya penciptaan Tuhan. Manusia menjarah kendali semesta dari Tuhan dan menahbiskan diri sebagai penguasa atas ciptaan-ciptaan lain. Mereka menciptakan relasi timpang antar ciptaan dan mulai bertindak secara tidak adil terhadap ciptaan-ciptaan lain. Mereka memeras habis-habisan ciptaan-ciptaan lain demi menggelembungkan erosnya. Ekologi mengalami kerusakan karena manusia berubah menjadi parasit, bahkan predator terhadap yang lain. Kerusakan ekologi, papar Ruether, hanya mungkin pulih jika manusia mau menggeser perannya sebagai penguasa atas ciptaan-ciptaan lain menjadi pelayan bagi mereka. Pemulihan, bahkan penciptaan kembali hanya dapat berlangsung jika manusia membaharui relasi setaranya dengan mereka. Manusia diundang mendengarkan kembali panggilan Tuhan yang mendesain bumi sebagai ruang terbuka bagi semua ciptaan.[10]
Persaudaraan Global Menebus Ekologi
Gerakan ekoteologi bersama dengan gerakan-gerakan lainnya menyibakkan fakta manusia kontemporer yang melangkah mundur menjadi perusak rahim ekologi yang telah dan memekarkannya. Ia lahir dari perjumpaan perjumpaan kontemporer teologi penciptaan dan holocaust ekologi. Ekoteolog mendesain ulang tempat manusia dalam ekologi dan tanggung jawab baru mereka di tengah holocaust ekologi. Kita hanya memiliki waktu singkat untuk menebus ekologi dari bahaya holocaust. Ekoteologi mendorong komunitas beriman untuk terlibat dalam melestarikan ekologi dan mengungkap pelaku perusakan ekologi. Ekoteolog menolak godaan untuk mengkambinghitamkan Tuhan sebagai pemberi kuasa kepada manusia atas ciptaan-ciptaan lainnya. Kita, sebagaimana ditegaskan ekoteolog feminis Sallie McFague, menarik ke belakang (decentering) peran manusia sebagai tuan atas ciptaan dan menarik ke depan kembali (recentering) peran manusia sebagai rekan Tuhan dalam melestarikan ciptaan.
Ekoteologi turut memberikan kontribusi berharga kepada komunitas global mengenai penting dan mendesaknya krisis ekologi. Komunitas global meningkat kesadarannya akan krisis ekologi namun belum melihat krisis ekologi sebagai isu global yang memanggil semua warga bumi untuk menebusnya (global ecumene). Forum-forum global mengenai ekologi belum mampu berbicara mengenai kehidupan bersama yang terancam dengan krisis ekologi global. Mereka masih berbicara dalam batas geografi ekonomi Utara-Selatan yang menceraikan pelestarian ekologi dari keadilan sosial. Negara kita masih menangani bencana-bencana alam dengan sistem tambal sulam. Bencana alam mengalami pendangkalan karena kita gagal melihatnya sebagai cermin krisis ekologi nasional. Banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan misalnya mengalami banalitas diterima sebagai ritual tahunan. Kita belum sadar bahwa tumpukan kerusakan ekologi melemahkan sistem pertahanan internal dalam ekologi. Beberapa bencana ekologi menyingkapkan ketidakmampuan sistem internal ekologi untuk menahan kerusakan ekologi yang sudah pada stadium parah.
Kejahatan terhadap ekologi merupakan tindakan dosa melawan Tuhan. Ekoteologi memandang dosa secara baru sebagai kerusakan relasi antara ciptaan dengan Tuhan dan antarciptaan. Pandangan tradisional mengenai dosa ini gagal mengangkat kejahatan terhadap ekologi karena berfokus pada relasi antara ciptaan dengan Pencipta dan relasi antarmanusia sebagai ciptaan. Ekoteologi menilai eksploitasi manusia terhadap ciptaan-ciptaan nonmanusia sebagai dosa. Hukum di Indonesia belum atau kurang memiliki kuasa untuk menjerat perusak ekologi. Ekoteolog ditantang untuk berani menyuarakan pesan profetik di tengah-tengah lemahnya kritik terhadap para perusak ekologi. Kerusakan pada alam menimbulkan efek negatif pada semua ciptaan. Kita mencari musuh ekologi dan kita menemukan bahwa kitalah musuh ekologi itu.
Tuhan menjangkau semua ciptaan dalam penebusan. Ia menebus semua ciptaan dari ancaman holocaust. Ia juga berkenan berelasi dengan semua ciptaan dan bahkan bersemayam dalam diri mereka. Semesta dengan demikian menjadi tubuh Tuhan. Manusia dapat dan harus menjaga tubuh Tuhan dari ancaman holocaust ekologi. Kita harus menjaga bumi sebagai rumah semua ciptaan.[11] Komunitas beriman diundang untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pandangannya terhadap Tuhan dan ciptaan. Mereka diundang untuk mengingatkan umat manusia untuk menjauhi diri dari godaan menjadi parasit, bahkan predator bagi ciptaan-ciptaan lain. Manusia kontemporer diundang untuk memekarkan relasi setara yang berkeadilan dengan ciptaan-ciptaan lain demi kehidupan ekologi yang lestari.[12] Kita dipanggil menjadi rekan Tuhan dalam menebus firdaus dari holocaust ekologi (SELESAI).
[1] Rohaniwan Katolik yang sedang mendalami teologi sistematik di Jesuit School of Theology di Berkeley dan mengembangkan teologi kemanusiaan kontemporer
[2] Rosemary Radford Ruether mengamati mekarnya tulisan-tulisan perempuan mengenai ekologi. Ruether sekaligus menilai bahwa tulisan-tulisan ecofeminis belum sampai pada taraf kedalaman dan membutuhkan eksplorasi akademik lanjutan. Saya mengusulkan beberapa tulisan rintisan pendek mengenai ecofeminisme dari tradisi religius lain antara lain Stephanie Kaza, “Buddhism, Feminism, and the Environmental Crisis”; Judith Plaskow, “Feminist Judaism and Repair of the Word”; Lina Gupta, “Purity, Pollution, and Hinduism”; Chung Hyun Kyun, “Ecology, Feminism, and African and Asian Spirituality: Towards a Spirituality of Eco-Feminism.”
[3] Sallie McFague, “An Earthy Theological Agenda” dalam Carol J. Adams (Ed.), Ecofeminism and the Sacred (New York: Continuum, 1993), 84.
[4] David G. Hallman, Beyond “North/South Dialogue” dalam David G. Hallman, Ed., Ecotheology: Voices from South and North (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1994), 6.
[5] Charlene Spretnak memandang ekofeminisme seperti taman indah dengan beragam jalan masuk ke dalamnya. Ekofeminisme lahir dari perjumpaan eksistensial perempuan dengan krisis ekologi dan harapan mereka untuk memekarkan persaudaraan dengan alam (communion with nature). Gerakan pertama ekofeminisme yang berkuncup pada tahun 1960-1970-an menyadari akar patriarki dan melihat alam dan perempuan sebagai korban patriarki. Gelombang kedua ekofeminisme pada pertengahan 1970an menyadari bahwa ekologi yang semula terlepas dari hidup mereka sekarang manjadi bagian hidup mereka. Gelombang ketiga ekofeminisme berkuncup dari keterlibatan perempuan dalam gerakan lingkungan. Spretnak melihat variasi dari ketiga jalan itu dan jalan-jalan baru lainnya. Lih. Charlene Spretnak, “Ecofeminism: Our Roots and Flowering” dalam Irene Diamond and Gloria Feman Orestein, Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism (San Francisco: Sierra Club Books, 1990), 3 – 14.
[6] Rosemary Radford Ruether, New Woman/New Earth (1975), 186; Ruether, 1989, 2. Ruether, “Eco-feminism and Theology” in David G. Hallman, Ecotheology, 199 – 201.
[7] Vandana Shiva, “Development as a New Project of Western Patriarchy” dalam Irene Diamond dan Gloria Feman Orestein, Reweaving the World, 191 – 194.
[8] Leonardo Boff, Social Ecology: Misery and Poverty, dalam David G. Hallman, Ecotheology, 235 – 247.
[9] Richard Cartwright Austin, Hope for the Land: Nature in the Bible (Austin: John Knox Press, 1987), 45 – 59.
[10] Rosemary Radford Ruether, Toward an Ecological-Feminist Theology of Nature, Judith Plant, Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism (Philadelphia: New Society Publishers, 1989), 145 – 150.
[11] Sallie McFague, dalam Carol J. Adams, Ed., Ecofeminism and the Sacred, 84 – 98.
[12] Rosemary Radford Ruether, “Symbolic and Social Connections of the Oppression of Women and the Domination of Nature” dalam Carol J. Adams (Ed.), Ecofeminism and the Sacred (New York: Continuum, 1993).

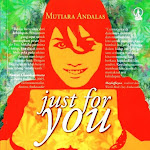
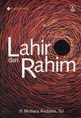




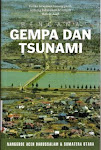












No comments:
Post a Comment