Kejahatan terhadap Kesucian Kemanusiaan
Refleksi Tragedi Mei 1998 bersama Hannah Arendt
Oleh Mutiara Andalas
Kebebasan merupakan tujuan revolusi sepanjang masa
Hannah Arendt [1]
 Biadab! Kejam! Anarkis! Tidak berperikemanusiaan! Iblis merasuki para pelaku! Kita mendengarkan komentar-komentar bernada kemarahan terhadap para pelaku kekerasan terhadap korban tragedi Mei 1998. Sebagian masyarakat melihat di depan mata mereka sendiri kekerasan terhadap korban di ruang terbuka. Sebagian saksi melihat para pelaku berperilaku aneh seakan-akan mereka tidak bertindak di luar kesadaran. Mereka menunjukkan perilaku seperti binatang buas dengan mata nyalang terhadap korbannya. Mereka mungkin menerima suntikan medis tertentu sehingga mereka kehilangan kepekaan terhadap jeritan korban. Manusia dalam keadaan normal tidak mungkin melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar perikemanusiaan. Menhankam Wiranto, dalam sebuah pertemuan akbar dengan komunitas Tionghoa, merasa perlu klarifikasi terhadap tuduhan keterlibatan dirinya dalam tragedi kemanusiaan itu. Ia takut sekali kalau masyarakat umum memandangnya dengan penuh kebencian seakan-akan ia iblis dalam tragedi kemanusiaan Mei.[2]
Biadab! Kejam! Anarkis! Tidak berperikemanusiaan! Iblis merasuki para pelaku! Kita mendengarkan komentar-komentar bernada kemarahan terhadap para pelaku kekerasan terhadap korban tragedi Mei 1998. Sebagian masyarakat melihat di depan mata mereka sendiri kekerasan terhadap korban di ruang terbuka. Sebagian saksi melihat para pelaku berperilaku aneh seakan-akan mereka tidak bertindak di luar kesadaran. Mereka menunjukkan perilaku seperti binatang buas dengan mata nyalang terhadap korbannya. Mereka mungkin menerima suntikan medis tertentu sehingga mereka kehilangan kepekaan terhadap jeritan korban. Manusia dalam keadaan normal tidak mungkin melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar perikemanusiaan. Menhankam Wiranto, dalam sebuah pertemuan akbar dengan komunitas Tionghoa, merasa perlu klarifikasi terhadap tuduhan keterlibatan dirinya dalam tragedi kemanusiaan itu. Ia takut sekali kalau masyarakat umum memandangnya dengan penuh kebencian seakan-akan ia iblis dalam tragedi kemanusiaan Mei.[2]
Kita juga mendengarkan lautan kemarahan dan spekuasi saat para petinggi Nazi duduk sebagai terdakwa di pengadilan Nuremberg dan Yerusalem. Tak sedikit orang mengira iblis bersemayam dalam diri para pelaku. Sebagian ingin tahu apakah mereka mereka secara medis sehat. Ada pula yang ingin mengetahui apakah mereka masih memiliki hati nurani. Hannah Arendt (1906 – 1975), seorang filsuf politik, tampil dengan komentar yang sangat tidak popular mengenai para pelaku. Ia memandang para pelaku sebagai orang-orang sehat yang melakukan kejahatan terhadap sekitar 6 juta warga Yahudi secara sadar.[3] Arendt melihat kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan anti-politik yang didesain secara sistematis oleh rezim otoriter.
Tulisan ini hendak mengangkat gagasan Arendt mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan implikasinya dalam memahami tragedi kemanusiaan Mei 1998.
Otoritarianisme sebagai Anti-Politik
 Holocaust meruntuhkan peradaban Barat. Peristiwa kemanusiaan itu mengalami pendangkalan saat para ahli politik mendekatinya dengan lensa hermeneutik tradisional perang, dan bahkan kekerasan. Lensa hermeneutik politik tradisional gagal melihat Holocaust sebagai fenomena rezim otoriter yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Holocaust meruntuhkan peradaban Barat. Peristiwa kemanusiaan itu mengalami pendangkalan saat para ahli politik mendekatinya dengan lensa hermeneutik tradisional perang, dan bahkan kekerasan. Lensa hermeneutik politik tradisional gagal melihat Holocaust sebagai fenomena rezim otoriter yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hannah Arendt menangkap kepincangan akademik dalam memahami tragedi kemanusiaan itu.
Ia melihat Holocaust sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Arendt menggunakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai lensa hermeneutik baru dalam memahami Holocaust.[4]
Lensa hermeneutik politik tradisional memandang kekerasan secara utilitarian. Ia melihat Holocaust sebagai peristiwa kekerasan dalam rangka menahlukkan lawan. Deportasi terhadap warga Yahudi, penempatan mereka di wilayah tertentu, dan akhrinya pembasmian mereka Penahlukan ekonomi atau militer bukan merupakan tujuan dari deportasi, konsentrasi, dan pembasmian warga Yahudi. Hannah Arendt mengalami kesulitan untuk melihat tujuan rezim Hitler menciptakan dan pada akhirnya menyelesaikan persoalan Yahudi dengan kekerasan. Hannah Arendt meihat fenomena baru dalam Holocaust dimana kekerasan bukan merupakan sarana demi tujuan penahlukan melainkan kekerasan sebagai tujuan. Rezim otoriter dibangun di atas pilar kekerasan.
Hannah Arendt juga mempertanyakan lensa hermeneutik tradisional mengenai kejahatan yang juga mengidap utilitarianisme. Arendt membedakan kejahatan yang memiliki tujuan dari kejahatan yang anti-tujuan. Ia berjumpa dengan industri pembantaian manusia yang memperkerjakan manusia, termasuk warga Yahudi, untuk membantai warga Yahudi. Ia berjumpa dengan realitas rezim otoriter yang melibatkan buruh massal yang bekerja pada pabrik pembantian manusia dan problematika untuk menjerat kejahatan mereka terhadap kemanusiaan.
Namun hukum hanya mengadili sebagian pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan membiarkan yang lain mendapatkan kebebasan dari tanggung jawab hukum. Para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan berkelit dari hukum karena mereka hanya merupakan sekrup kecil dalam industri pembantaian manusia. Mereka mau, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari sistem otoriter.
Hannah Arendt melihat kemungkinan menyeret para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tanggung jawab moral dalam Holocaust ke ruang hukum. Di mata Arendt, para pelaku memiliki kebebasan untuk menolak keterlibatan dalam proyek inhumanitas rezim otoriter.
Arendt mengundang komunitas dunia untuk bertanggung jawab terhadap kemanusiaan lain dengan melawan kejahatan terhadap kemanusiaan di luar geografi mereka. Sebaliknya para pelaku berusaha menyembunyikan diri di belakang negara otoriter. Mereka memandang diri mereka sekedar sebagai pesuruh di negara otoriter. Kehidupan mereka akan terancam mengalami kematian dini jika mereka menolak perintah. Mereka tidak memiliki kebebasan karena mereka hanya melaksanakan perintah.
Rezim totaliter memahami politik secara negatif sebagai penahlukan total dan menolak politik secara positif sebagai kebebasan. Ia memproduksi masyarakat massa yang tidak memiliki signifikasi politik. Masyarakat massa menghilangkan individualitas. Mereka menghilangkan kebebasan manusia dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Rezim totaliter pada abad dua puluh tidak menyerang negara, melainkan menyerang masyarakat. Individu sulit untuk melarikan diri apalagi melawan masyarakat dalam masyarakat massa karena masyarakat massa menginkorporasikan semua tingkat penduduk.[5] Sebaliknya Arendt memandang politik sebagai fenomena dunia publik dan signifikasi manusia sebagai subyek dalam hidup berpolitik.
Manusia memiliki kemampuan politik jika ia mampu mengorientasikan dirinya di ruang publik. menekankan signifikasi manusia dalam politik. Manusia berpartisipasi dalam urusan publik.[6]
Rezim otoriter mengidap ketulian politik. Ia menyamakan kekuasaan dengan perintah, kepatuhan, dan bahkan teror.
Arendt menolak kekerasan sebagai essensi sebuah rezim kekuasaan. Ia melihat kekerasan sebagai puncak keputusasaan rezim otoriter. Teror rezim otoriter menghilangkan kekuasaan oposisi. Rezim otoriter mencapai bentuk sempurna ketika ia menghilangkan kekuasaan. Mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusaian yang memiliki potensi kerusakan yang sulit diprediksi dan dipahami. Rezim totaliter mempekerjakan warga Yahudi untuk melakukan pembantaian terhadap warga Yahudi lain. Para warga Yahudi yang terlibat dalam eksekusi itu kemudian menjadi korban berikutnya. Rezim otoriter memakan anaknya sendiri. Arendt membuka jalan baru dalam diskusi politik mengenai Holocaust saat ia berbicara mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Rezim otoriter tak hanya menyerang kehidupan warga Yahudi melainkan kehidupan seluruh umat manusia.
Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Diskusi kekerasan memasuki babak baru dengan kasus pengadilan Eichmann. Hannah Arendt memandang kejahatan Eichmann tidak sekedar terarah pada warga Yahudi, tetapi tertuju pada umat manusia.
Arend juga mengkritik kebungkaman komunitas dunia, termasuk politikus, yang gagal membaca fenomena kamp konsentrasi dan rezim otoriter. Dunia politik memandang kekerasan rezim otoriter sebagai topik marginal. Komunitas dunia sebagai manusia politik juga tidak berbicara mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena diam ini kekerasan menjadi marginal dalam bidang politik.
Politik mengalami pendangkalan menjadi antipolitik ketika kita memuja atau memberikan justifikasi terhadap kekerasan.[7]Ia juga mengalami pelacuran akademik ketika memberikan penjelasan muran tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kajahatan yang berakar dalam diri manusia sebagaimana banyak dikesankan dalam kisah-kisah kitab suci dan kisah klasik manusia lainnya.[8]
Hannah Arendt menyatakan bahwa fakta memiliki sifat ngeyel. Ia tetap ada meskipun sejarahwan/wati atau sosiolog menolak untuk belajar darinya. Atau meskipun semua orang melupakannya.[9]
Hannah Arendt menyadari bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan interupsi terhadap kenyamanan politik dalam mendekati tragedi kemanusiaan Holocaust.
Arendt melihat bahwa Holocaust memiliki daya interuptif terhadap sejarah kemanusiaan.[10]Ia mengundang para politikus untuk menggunakan kebebasan mereka untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik dan menggugat rezim otoriter.[11] Rezim otoriter membahayakan keberlangsungan hidup dunia (a world of durability) dan rasa aman dunia (an island of security). Mereka hendak menundukkan kebebasan manusia dan memerosokkan sejarah pada dehumanisasi. Arendt membedah perut politik rezim otoriter dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Rezim otoriter menciptakan persoalan Yahudi dan berhasil menggerakkan masyarakat untuk berdiri pada kutub non-Yahudi.
Ia tidak mengakui keberadaan warga Yahudi secara sosial. Ia membaptis warga Yahudi secara politik sebagai warga yang memiliki relasi timpang dengan warga Jerman. Ia hendak menciptakan negara Jerman tanpa kehadiran warga Yahudi. Ia mempraktekkan politik de-nasionalisasi menjadi senjata ampuh untuk menyingkirkan minoritas sosial yang tak diinginkankannya. Ia mengajukan deportasi paksa sebagai solusi pertama terhadap persoalan Yahudi. Deportasi paksa menemui kemacetan karena beberapa negara menarik dukungannya terhadap kebijakan resmi ini setelah mengetahui deportasi merupakan penghalusan dari pelenyapan warga Yahudi.[12]
Solusi kedua terhadap persoalan Yahudi adalah menempatkan warga Yahudi pada ruang isolasi. Pada awalnya rezim otoriter hendak mengumpulkan semua warga Yahudi dan membentuk negara Yahudi. Ia kemudian menyadari bahwa ia tidak memiliki ruang yang mampu menampung warga Yahudi yang mengalami deportasi paksa karena jumlah mereka berada dalam kisaran jutaan. Mereka juga memiliki waktu sangat pendek untuk melaksanakan solusi kedua. yang jumlahnya mencapai hitungan jutaan. Ia juga tidak dapat melaksanakan solusi kedua dalam waktu singkat. Rezim otoriter, misalnya, melibatkan kompetensi medis untuk melakukan pembunuhan sistematis terhadap warga Yahudi.[13]
Solusi final terhadap persoalan Yahudi adalah melakukan pembunuhan paksa terhadap warga Yahudi di lokasi-lokasi kekuasaan rezim otoriter. ‘Pembantaian,’ ‘likuidasi,’ ‘pembunuhan’ dan kata-kata senada jarang muncul dalam dokumen resmi. Rezim otoriter menggunakan istilah-istilah eufeministik, seperti ‘solusi final,’ ‘evakuasi,’ dan ‘perawatan khusus’ untuk menyebut pembunuhan paksa.
Ia menggunakan istilah-istilah halus ‘perubahan lokasi tinggal,’ ‘penempatan kembali,’ dan ‘kerja di negara Timur’ untuk deportasi paksa. Ia menggunakan eufemisme bahasa untuk membedakan tindakannya dari tindakan kebohongan atau pembunuhan. Mereka mendirikan industri pembasmian manusia melalui metode penembakan atau racun gas.[14]
Penjahat Kemanusiaan
Tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan mengalami jalan berliku. Para pelaku menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan sebagai penjahat kemanusiaan. Mereka mengaku menerima ancaman kehidupan dari rezim otoriter jika mereka menolak terlibat dalam solusi terhadap persoalan Yahudi. Rezim otoriter meminta ketaatan mayat (the obedience of corpse) kepada mereka dan bertindak kejam terhadap pembangkangan perntah. Salah satu Jenderal dalam pengadilan di Nuremberg mengungkapkan ketaatan mayat ini dalam pembelaanya,
“Seorang prajurit tak pernah mengemban tugas sebagai hakim atas atasannya. Sejarah atau Tuhan bertindak atas hakim atasan saya.”[15]Para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaaan membela diri mereka dihadapan hukum dengan menyatakan bahwa mereka telah berbuat maksimal untuk mengurangi jumlah korban. Mereka juga menyayangkan tiadanya suara profetik dari komunitas moral atau agama yang mempengaruhi mereka untuk menolak kejahatan terhadap korban. Komunitas moral atau agama hanya datang untuk meminta keringanan penderitaan terhadap warga Yahudi.
Salah satu episode tergelap dalam sejarah komunitas Yahudi adalah keterlibatan mereka dalam kejahatan terhadap kemanusaiaan sesama warga Yahudi.
Eichmann menyadari kekuatan terbatasnya untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menggunakan tangan-tangan lain untuk menggerakkan mesin pembantaian massal. Ia melihat kemungkinan untuk melibatkan warga Yahudi dalam proyek deportasi paksa terhadap sesama mereka. Para warga Yahudi yang terlibat dalam pembantaian massal mengalami nasib sama dengan sesamanya kemudian. Mereka hanya mendapatkan waktu lebih panjang dari antrean deportasi paksa. Komunitas Yahudi mencari alasan keterlibatan para pemimpin Yahudi sebagai instrumen kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pemimpin Yahudi para periode itu tidak hanya menghancurkan sesama mereka tetapi juga diri mereka sendiri. Rezim otoriter berhasil menyulut gairah kekuasaan para pemimpin Yahudi atas kehidupan sesama mereka.
Hannah Arendt menilai rezim otoriter Hitler telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hitler tidak hanya menyerang warga Yahudi tetapi semua warga dunia yang memegang nilai-nilai kemanusiaan. Umat manusia akan mengalami kepunahan dini jika semua rezim otoriter memperoleh tiket gratis untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kita menyelenggarakan tribunal internasional demi keadilan korban. Tribunal internasional mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan dengan hukuman bagi para pelakunya.[16] Tribunal internasional harus menghadirkan saksi untuk membela korban. Ia menjatuhkan tuduhan kepada pelaku sebagai penjahat kemanusiaan (hostis generis humani), bukan sebagai manusia atau monster sadis. Ia harus diselenggarakan sesegera mungkin sebelum para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan menghilangkan bukti-bukti kejahatan mereka.[17]
Mengeja Ulang Tragedi
 Hannah Arendt memberikan kontribusi besar kepada penulis untuk mengeja ulang peristiwa Mei 1998.
Hannah Arendt memberikan kontribusi besar kepada penulis untuk mengeja ulang peristiwa Mei 1998. “Mei Kelabu,” “Kerusuhan Mei” dan “Kerusuhan Etnis” merupakan istilah popular untuk menangkap realitas peristiwa Mei 1998
. “Mei Kelabu” lebih mengungkapkan perubahan, bahkan buruknya cuaca politik Indonesia yang kemudian melahirkan era reformasi. “Kerusuhan Mei” menitikberatkan ledakan politik yang melampaui kontrol negara untuk mencegah kekacauan politik dan anonimitas pelakunya. “Kerusuhan etnis” berfokus pada realitas etnis Tionghoa yang beberapa kali menjadi target korban dalam peristiwa Mei 1998. Istilah-istilah popular tersebut membantu publik untuk merangkai peristiwa Mei 1998. Meskipun demikian istilah-istilah tersebut mengidap cacat serius dalam membingkai peristiwa kemanusiaan itu. Penulis lebih memilih untuk menamai peristiwa Mei 1998 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Mei Kelabu” menangkap perubahan drastis dalam iklim politik Indonesia, namun cenderung memandangnya sebagai keniscayaan sejarah untuk melahirkan era reformasi. Kita mudah sekali tergoda untuk mendangkalkan persoalan korban karean terobsesi dengan era reformasi. Korban menempati posisi marginal, bahkan persoalan korban seolah tertebus dengan lahirnya era reformasi. Reformasi tampil sebagai peristiwa keselamatan bagi bangsa Indonesia yang menebus penderitaan korban. Istilah ini juga mengabaikan para penjahat kemanusiaan yang menciptakan kematian prematur terhadap hidup korban.
“Kerusuhan Mei” menangkap gejolak sosial yang menggerakkan massa yang mengungkapkan frustasi politik dengan mengambil paksa milik pribadi atau merusak fasilitas publik. Ia melahirkan kata “penjarah” untuk menyebut massa yang mengambil paksa barang-barang di pusat-pusat ekonomi dan yang mengalami kematian dini di pusat-pusat ekonomi yang mengalami pembakaran. Kata “provokator” muncul kemudian untuk menyebut kelompok massa terorganisir yang memompa emosi massa yang semula menjadi penonton dalam gejolak sosial menjadi massa yang anarkis. Istilah “kerusuhan Mei” tidak melangkah lebih jauh untuk mempertanyakan keberadaaan kekuatan lebih besar yang meminjam tangan provokator. Ia juga mengabaikan pertanggungjawaban massa karena mereka hanya menjadi korban provokasi.
“Kerusuhan etnis” menyingkap fakta korban warga Indonesia etnis Tionghoa dalam peristiwa Mei 1998. Kebanyakan kerusuhan terhadap warga Indonesia etnis Tionghoa berlangsung di tempat mereka bekerja atau hidup. Mereka yang memandang peristiwa Mei 1998 sebagai kerusuhan etnis berjasa mengangkat para perempuan Indonesia etnis Cina yang mengalami kekerasan seksual. Mereka melawan viktimisasi ganda terhadap warga Indonesia etnis Cina yang menjadi korban dan terdakwa dalam peristiwa Mei 1998. Pandangan ini cenderung mereduksi persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Mei 1998 menjadi persoalan Tionghoa. Akibatnya, ia mengabaikan fakta korban non-Tionghoa karena merasa bukan merupakan persoalan mereka.
Kejahatan terhadap kemanusiaan tampil sebagai istilah kemudian untuk menamai peristiwa Mei 1998. Para korban hidup dan keluarga korban mengakui bahwa istilah ini masih menyimpan kerapuhan secara akademik. Namun, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan menangkap secara kokoh realitas peristiwa Mei 1998 dari mata korban.
Ia menyingkap keberadaan sebuah rezim otoriter yang menggelar orkestra kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Rezim otoriter ini kemungkinan merekrut massa dan meminjam tangan mereka untuk melangsungkan orkestra kematian. Dalam tragedi kemanusiaan Mei, kita banyak melihat warga biasa yang tampil pada barisan depan sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan Mei mudah meredup dari pandangan publik sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena ia nampak sebagai kerusuhan massal. Masyarakat secara psikologis menderita kebisuan ketika hendak mengangkat kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa 1998 karena pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan hidup berdampingan dengan korbannya.
Aliansi Korban
Korban hidup dan keluarga korban berada dalam tegangan yang tak mudah terjembatani antara kebutuhan menyambung kehidupan ekonomi dan perjuangan politik menuntut rezim otoriter mereka pasca-kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebanyakan dari mereka memilih untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergantung kepada pihak lain dalam soal ekonomi ketika mereka memperjuangkan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan kepada negara. Mereka juga menyadari bahwa perjuangan politik membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan menyita waktu dalam hitungan tahun. Perjuangan politik mereka menggapai keadilan seringkali mengalami masa-masa kelelahan karena negara menunjukkan kekurangseriusan, bahkan ketidakseriusan dalam mengusut kejahatan terhadap kemanusiaan secara hukum. Mereka juga merasakan lemahnya solidaritas sosial terhadap korban kejahatan terhadap kemanusiaan.
 Rentang waktu antara tragedi kejahatan terhadap kemanusiaan dengan masa sekarang tak jarang melemahkan perjuangan korban dan solidaritas sosial. Beberapa paguyuban korban hidup dan keluarga korban menggagas aliansi korban kekerasan negara. Mereka menyadari bahwa
Rentang waktu antara tragedi kejahatan terhadap kemanusiaan dengan masa sekarang tak jarang melemahkan perjuangan korban dan solidaritas sosial. Beberapa paguyuban korban hidup dan keluarga korban menggagas aliansi korban kekerasan negara. Mereka menyadari bahwa negara mudah sekali mengapungkan tragedi kemanusiaan dalam waktu yang terus melaju.
Harapannya, pembiaran kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan akan melemahkan perjuangan korban dengan sendirinya tanpa negara menyentuhnya. Aliansi korban kekerasan negara merupakan payung yang melingkupi perjuangan bersama paguyuban korban demi keadilan hukum. Situasi negara sampai sekarang ini belum mengizinkan korban kekerasan memperjuangkan kasus hukumnya masing-masing. Aliansi korban kekerasan negara percaya bahwa mereka akan memberikan tekanan politik lebih besar kepada negara jika mereka memperjuangkan kasus mereka secara bersama-sama.
Tuntutan aliansi korban kekerasan negara untuk menggelar sidang bagi para pelaku kekerasan mengekspresikan tekad mereka untuk memberikan keadilan kepada korban. Aliansi korban kekerasan negara mengundang masyarakat untuk menyadari bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga tubuh sosial.
Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan menolak impunitas terhadap kejahatan mereka. Pengadilan hak asasi manusia akan memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (SELESAI).
[1] Hannah Arendt, On Revolution (USA: Penguins, 1991), 11.
[2] Dokumentasi Audio Visual “Kapan Tuntas?”
[3] Hannah Arendt mengungkapkan keberatan atas kategorisasi dirinya baik sebagai filsuf politik maupun sebagai teoretikus politik. Ia melihat semacam perselisihan terselubung antara tradisi filsafat yang menekankan manusia sebagai mahkluk yang berpikir dan tradisi politik yang menekankan manusia sebagai mahkluk yang bertindak. Arendt melihat kecenderungan filsafat yang terobsesi untuk bersikap objektif terhadap alam dan manusia. Ia melihat ketidakmungkinan filsuf untuk bersikap objektif terhadap politik. Ia melihat filsafat menghalangi penglihatannya terhadap politik. Lih Hannah Arendt, the Portable Hannah Arendt (
[4] Hannah Arendt, Essays in Understanding, 1930 – 1945 (New York: Harcourt Brace, 1994), 302.
[5] Hannah Arendt, “The Crisis in Culture: Its Social and Political Significance” in Ronald Beiner and Jennifer Nedelsky, Judgment, Imagination, and Politics: Themes from Kant and Arendt (, 2001), 4 – 5.
[6] Ibid, 17 – 20.
[7] Hannah Arendt, On Revolution, 13. 18 – 19.
[8] Hannah Arendt, On Revolution, 21.
[9] Hannah Arendt, On Revolution, 25.
[10] Hannah Arendt, On Revolution, 30.
[11] Hannah Arendt, On Revolution, 32 – 34.
[12] Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1968, xiv. 269. 275; Hannah Arendt, “Stateless Persons,” in Hannah Arendt, The Portable Hannah Arendt, 52; Hannah Arendt, Eichmann in
[13] Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, 68 – 82.
[14] Hannah Arendt, Eichmann in
[15] Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, revised and enlarged edition, (New York: Penguin Books, 1994), 149.
[16] Hannah Arendt, 268 – 270.
[17] Hannah Arendt, 274 – 277.

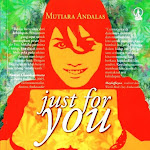
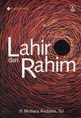




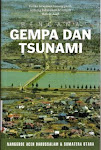












2 comments:
Wadow, panjangnya. Kirim ke mana yang ini?
he...he...he... gak cukup 5 menit bacanya... untuk koleksi sendiri dulu aja... rencananya mau saya masukin ke draft buku itu...
Post a Comment