 Hermeneutika Korban
Hermeneutika KorbanJakarta, 20 September 2007
Kepada Yth.
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta.
Dengan hormat,
Bersamaan dengan Aksi Diam yang ke-35, sebentuk aksi yang selalu kami (para korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia - HAM) lakukan di depan Istana Presiden, setiap Kamis sore pukul 16.00-17.00 WIB tepat, perkenankanlah kami mengingatkan Bapak Presiden bahwa sewindu yang lalu, tepatnya pada 24 September 1999, pernah terjadi penembakan secara brutal oleh aparat bersenjata dengan peluru tajam terhadap mahasiswa dan warga masyarakat yang menimbulkan sejumlah korban tewas, yang kemudian dikenal dengan sebutan Tragedi Semanggi II. Sejumlah korban tewas tersebut adalah: Yan Yun Hap (Mahasiswa UI, ditembak ketika aksi unjuk rasa telah usai), Zainal Abidin, Teja Sukmana, M. Nuh Ichsan, Salim, Jumadi, Fadly, Deny Julian, Yusuf Rizal, Saidatul Fitria, dan Meyer Ardiansah. Penembakan itu terjadi ketika mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa menolak diberlakukannya UU PKB (Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya), sebuah UU yang disusun oleh Pemerintah (di bawah Presiden B.J. Habibie) dan DPR RI (yang keanggotaannya didominasi oleh orang-orang pro status-quo Orde Baru). UU tersebut ditolak oleh masyarakat karena memberi peluang kepada aparat bersenjata, yang cenderung dijadikan alat penguasa, untuk melakukan tindakan represif terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang menghendaki terwujudnya demokrasi dan terbebaskannya kehidupan masyarakat dari genggaman penguasa otoriter.
Terhadap Tragedi Semanggi II ini, keluarga korban menuntut penyelesaian melalui Pengadilan HAM ad hoc. Namun, untuk menuju ke penyelesaian tersebut selalu ada upaya-upaya menghadangnya baik melalui tataran hukum maupun secara politis. Ambil contoh, ketika kami menuntut agar kasus Trisakti dan Semanggi I-II (TSS) dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc dan mendapat dukungan yang cukup signifikan, maka digelarlah persidangan kasus Trisakti di Peradilan Militer untuk sekedar memperlihatkan bahwa kasus tersebut telah/sedang tertangani. Ketika kasus Semanggi II diangkat kembali dengan tuntutan agar diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc, maka digelarlah persidangan kasus Semanggi II dan diberitakan oleh media massa bahwa yang menjadi terdakwa adalah seorang anggota TNI, Praka Tuaputy dari Kostrad, selaku pelaku penembakan. Namun bagaimana kelanjutan persidangan tersebut dan apa hasilnya, walahu’alam. Beritanya sirna seiring dengan surutnya tuntutan publik.
Kasus Semanggi II, juga Kasus Trisakti dan Semanggi I, kini masih menggantung karena Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti hasil penelitian Komnas HAM yang menyatakan bahwa dalam kasus TSS terjadi pelanggaran HAM berat. Penolakan itu disertai alasan karena belum dibentuk Pengadilan HAM ad hoc melalui Keppres berdasarkan usulan DPR. Sementara itu, DPR tidak mau mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden karena telah ada Rekomendasi DPR 9 Juli 2001 berupa laporan akhir Pansus DPR yang menyatakan bahwa peristiwa TSS bukan pelanggaran HAM berat. Pada 30 Juni 2005 Komisi III DPR merekomendasikan agar kasus TSS dibuka kembali, namun lagi-lagi kandas setelah Bamus (Badan Musyawarah) DPR tidak mau mengagendakannya dalam Rapat Pimpinan DPR. Rekomendasi Komisi III DPR tersebut hanya mendapat dukungan 3 fraksi di DPR yaitu Fraksi-PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi PAN.
Sampai sekarang, kasus TSS menjadi bola panas yang menggeliat di antara beberapa instansi yang mestinya berkompeten yaitu: Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR. Karena saling lempar, maka kasus TSS kini tetap menggantung, pada hal kasus tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan demi memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Oleh karenanya, sudah seharusnya Bapak Presiden tidak turut andil dalam menggantung kasus tersebut, melainkan justru mendorong ke arah penyelesaian segera. Dan bila perlu, secepatnya menerbitkan Keppres tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus termaksud. Siapa lagi dan kapan lagi kalau bukan Bapak Presiden, meskipun masa jabatan untuk periode ini tinggal beberapa bulan lagi. Sudah lama kami penuh harap, semoga Bapak Presiden mempunyai kepedulian terhadap penyelesaian kasus TSS ini.
Demikian, dan atas perhatian Bapak Presiden kami ucapkan banyak terima kasih.
Hormat kami,
atas nama Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban
Suciwati Munir, Sumarsih, Bedjo Untung
Keheningan Subversif
Keheningan melahirkan kata-kata. Keheningan hadir di depan Istana Negara setiap Kamisan antara pukul 16.00 - 17.00. Suara paguyuban korban dan keluarga korban suci dan sekaligus subversif. Paguyuban korban dan keluarga korban membela kesucian hidup korban yang meninggal prematur karena kekerasan negara. Mereka menggugat negara yang menghindar dari tanggung jawab sebagai pelaku kekerasan terhadap korban. Negara melakukan kejahatan mutilasi kebenaran engan membuang korban kekerasannya ke dalam kotak sampah sejarah Indonesia.
Keheningan Subversif
Keheningan melahirkan kata-kata. Keheningan hadir di depan Istana Negara setiap Kamisan antara pukul 16.00 - 17.00. Suara paguyuban korban dan keluarga korban suci dan sekaligus subversif. Paguyuban korban dan keluarga korban membela kesucian hidup korban yang meninggal prematur karena kekerasan negara. Mereka menggugat negara yang menghindar dari tanggung jawab sebagai pelaku kekerasan terhadap korban. Negara melakukan kejahatan mutilasi kebenaran engan membuang korban kekerasannya ke dalam kotak sampah sejarah Indonesia.
Keheningan menjadi bahasa resistensi paguyuban keluarga korban terhadap amnesia. Mereka menuliskan nama dan kisah korban. Setiap nama memiliki nafas kehidupan. Paguyuban korban dan keluarga korban mengundang kita masuk dalam semesta para korban. Mereka melakukan interupsi terhadap bahasa resma negara yang mengingkari kebenaran. Sebaliknya negara mengeluarkan sabda final kepada kita mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang diciptakannya. Negara menolak bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan Mei-Semanggi 1998 karena merasa tidak melakukan aksi kriminal yang memproduksi kematian prematur korban.
Rentang waktu antara tragedi kemanusiaan hingga saat ini diisi dengan kontestasi kebenaran antara paguyuban korban dan keluarga korban melawan negara. Paguyuban korban dan keluarga korban hendak menciptakan anamnesis sosial. Mereka mendakwa negara sebagai pelaku kekerasan yang hendak memproduksi amnesia sosial. Publik berada di tengah-tengah konflik kebenaran. Publik diundang untuk mempersilakan paguyuban korban dan keluarga korban memasuki panggung drama sejarah Indonesia. Paguyuban korban dan keluarga korban seringkali mengisahkan penderitaan korban dengan secarik kertas. Penderitaan menghancurkan kronologi kisah. Namun, mereka berhasil memberikan identitas kepada korban yang megalami kematian prematur karena kriminalitas negara. Mereka sadar bahwa mengisahkan hidup korban di negara kriminal itu seperti melukis di atas kanvas padang pasir.
Rentang waktu antara peristiwa masa lalu dengan masa kini dapat melemahkan ingatan kita. Meskipun demikian, pelupaan sosial itu terutama bukan merupakan proses alami, melainkan diproduksi secara sistematis oleh negara. Apatisme sosial menyekat hidup korban dari geografi hidup bersama.
Anamnese sosial bertunas dari perjumpaan dengan korban. Hidup korban menyapa kita dan menumbuhkan solidaritas kepada korban. Kisah korban melalui keluarga mereka atau relawan kemanusaiaan menjadi hati buku ini. Penulisan ulang kisah korban pasca-tragedi harus berani masuk dalam kronologi dan detail peristiwa. Saat mengisahkan hidup korban, kita tidak ingin menghilangkan pengalaman orisinal dan subversif korban. Kata, air mata, ritual dan keheningan korban hidup dan keluarga korban menjadi bahasa resistensi terhadap amnesia sejarah. Sisi-sisi dalam kemanusiaan seperti kedukaan, ketakberdayaan, kemarahan tetapi sekaligus suka cita, harapan, dan ketabahan korban, merupakan dinamika menuju anamnesis sejarah.
Ibu Plaza de Mayo, Rigoberto Menchú, Aung San Suu Kyi, Elie Wiesel, dan Hannah Arendt tampil sebagai representasi korban dan saksi korban dari belahan dunia yang berkenan menjadi sahabat paguyuban korban dan keluarga korban kekerasan negara di Indonesia. Mereka menulis surat, monolog, dan dialog imajiner dengan paguyuban korban dan keluarga korban dari lokasi masing-masing. Solidaritas sosial dengan korban melintasi batas-batas georgrafi teritorial. Solidaritas belahan dunia lain terhadap hidup korban di Indonesia merupakan resistensi global aktif terhadap upaya sistematis rezim kriminal untuk mengisolasi hidup korban dari dunia sosialnya.
Para Ibu Plaza de Mayo yang melakukan aksi menolak penghilangan paksa selama 20 tahun berbicara kepada kita mengenai kekuatan solidaritas antarkorban. Perjuangan melawan negara kriminal mudah patah jika masing-masing keluarga korban berjuang sendiri dan demi kepentingan sendiri. Mereka menyadarkan kita bahwa perjuangan mereka tak sekedar mengembalikan kehidupan anak atau cucu mereka yang hilang. Seperti dituturkan Eduardo Galeano, sosiolog Argentina, represi politik menculik sejarah.[1] Represi politik di Argentina menghilangkan tiga generasi kehidupan, yaitu orang tua korban, korban, dan anak-anak korban. Rekonsiliasi sosial, apalagi humanisasi sejarah, tak pernah tercipta jika negara menutup paksa kasus kekerasan yang dilakukan atau didukungnya dengan impunitas kepada pelaku kekerasan dan restitusi ekonomi kepada keluarga korban.
Rigoberta Menchu dari Guatemala tampil dalam dialog imajiner sebagai sosok pejuang kemanusiaan perempuan yang lahir dari perut penderitaan. Ia terlibat dalam paguyuban korban dan keluarga korban yang mengalami represi negara. Ia berbagi kisah mengenai pertarungan klaim kebenaran mengenai tragedi kemanusiaan yang menciptakan kematian prematur korban. Rezim otoriter mementaskan teater kekerasan dalam grafik yang di luar batas perikemanusiaan. Mereka hendak menekuk lutut korban hidup agar bersimpuh di depan mereka. Mereka menahlukkan hidup korban secara total dengan mencabut paksa nafas kehidupannya. Kekerasan militer yang merusak tubuh korban di luar batas-batas perikemanusiaan meninggalkan jejak penderitaan yang laten dalam ingatan korban hidup dan sekaligus menghilangkan jejak identitas pelakunya.
Aung San Suu Kyi akan berdialog secara imajiner dengan Menhankam RI. Suu Kyi mengajukan politik kasih sebagai alternatif terhadap politik senapan yang banyak dipeluk rezim otoriter. Politik senapan sejak awal tercerabut dari akar rakyat. Ia justru memproduksi kematian prematur pada rakyat. Ia memiliki kredo, “yang memiliki senjata, memegang kekuasaan.” Suu Kyi dalam dialog imaginer menilai bahwa negara Indonesia masih memeluk politik senapan. Ia mengundang Menhankam RI untuk menerima paguyuban korban dan kelaurga korban yang menuntut keadilan hukum bagi korban yang mengalami kematian prematur.
Elie Wiesel sebagai korban hidup Holocaust berdialog secara imajiner dengan relawan kemanusiaan mengenai peran mereka sebagai saksi hidup korban. Saksi kemanusiaan bertanggung jawab menghentikan atau sekurang-kurangnya menahan laju pelupaan sosial. Tanpa kehadiran saksi kemanusiaan, ingatan akan penderitaan yang selama ini dibawa paguyuban korban dan keluarga korban akan menghilang. Saksi kemenusiaan membawa ingatan korban dalam dirinya untuk disebarkan kepada dunia. Pelupaan sosial meluncur cepat mengubah korban di sisi bawah sejarah dari memiliki identitas pada anonimitas.
[Hannah Arendt]
Selain mendengarkan para pekerja kemanusiaan dari luar Indonesia, buku ini mengundang pembaca untuk menulusuri ziarah mereka yang bukan-korban di Indonesia yang memutuskan menjadi sahabat para korban pasca tragedi kemanusiaan. Mereka mengalami jatuh bangun dalam membangun relasi dengan korban hidup dan keluarga korban. Solidaritas merupakan terminologi yang merangkum kisah kenangan para pekerja kemanusiaan terhadap kisah hidup korban yang terus-meneruskan digelapkan negara secara sistematis. Solidaritas sejati dengan korban tumbuh dari perjumpaan mistik non-korban dengan korban. Solidaritas dengan hidup korban ini seringkali membawa konsekuensi ancaman kehidupan, bahkan kematian prematur terhadap pekerja kemanusiaan.
Pelupaan Sosial
Kurun waktu sejak tragedi hingga peringatan terhadap tragedi merupakan periode kritis bagi paguyuban korban dan keluarga korban. Mereka menyerukan resistensi terhadap amnesia sosial yang diciptakan negara, dan menanti jawaban publik atas kesaksian subversif mereka. Suara subversif paguyuban korban dan keluarga korban semakin vokal seiring dengan kesadaran bahwa mereka harus melawan amnesia sosial. Publik yang tidak mau berempati dengan hidup korban memeluk amnesia sosial. Publik terkadang mengalami kesulitan untuk melihat kebenaran realitas versi paguyuban korban dan keluarga korban. Dalam situasi demikian, publik kadang-kadang mengibarkan bendera putih dalam pencarian kebenaran mengenai korban. Mereka akhirnya cenderung membaca dokumen resmi mengenai hidup korban yang diproduksi negara yang berujung pada amnesia sosial.
Tragedi kemanusiaan, seperti kekerasan seksual dan kematian dengan tubuh dibakar atau ditembak, seringkali menghancurkan hidup korban dan keluarga korban. Penderitaan menyerakkan hidup dan bahasa mereka. Kisah mereka sering tersela jeda panjang air mata. Dalam keadaan psikis yang lelah dan kehilangan harapan, korban tak jarang memilih bungkam selama periode yang sangat lama. Mendengarkan suara korban dalam kondisi seringkali menjadi aktivitas yang sangat melelahkan. Kisah mereka terserak, cacat, dan lemah kronologi. Penderitaan juga menyebabkan paguyuban korban dan keluarga korban seringkali kesulitan mengungkapkan tuntutan mereka kepada pihak-pihak yang menyebabkan kematian hidup korban secara artikulatif. Dalam situasi demikian, masyarakat non-korban hendaknya tidak pertama-tama menuntut korban hidup untuk berbicara secara lebih artikulatif tetapi lebih empatik mendengarkan suara korban.
Hermeneutika korban menawarkan cara baru dalam memandang persoalan korban tragedi kekerasan negara. Ia melihat kegagalan hermeneutika politik dalam membela hidup korban. Titik tolak hermeneutika politik adalah negara. Hermeneutika politik berusaha membongkar identitas negara sebagai pelaku kekerasan terhadap hidup korban. pelaku kekerasan terhadap korban. Negara dalam kenyataannya sangat lihai melakukan kekerasan tanpa meninggalkan jejak. Mereka yang memeluk hermeneutika politik sering terjebak dalam berbagai teori konspirasi politik yang berlarut-larut. Mereka sering kelelahan mengejar negara sebagai terdakwa utama dalam tragedi kemanusiaan. Pada saat yang sama, mereka cenderung melepaskan solidaritas mereka dengan korban. Hermeneutika korban mulai dari serpihan hidup korban yang terserak. Mereka yang memeluk hermeneutika korban menggunakan serpihan hidup korban untuk merekonstruksi wajah pelaku kekerasan.
[1] Eduardo Galeano, We Say No: Chronicles, 1963 – 1991, translated by Mark Fried et al. (New York: W.W. Norton, 1992), 215.

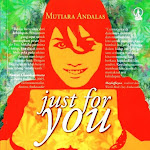
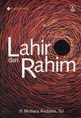




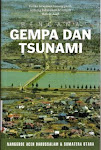












No comments:
Post a Comment