
Marianne Katoppo (1943 – 2007)
Teolog sebagai Penyair Allah
Oleh P. Mutiara Andalas, S.J.
Saat rehat kuliah penulis bertegur sapa dengan Choan-Seng Song yang mengampu kuliah. “Saya kagum pada Saudara,” demikian pengakuan penulis. “Saya pernah menulis artikel teologis berdasarkan tulisan-tulisan Saudara,“ lanjut penulis. “Saya mendidik kamu bukan agar engkau suatu hari nanti menyebutku guru. Aku mendidikmu agar engkau suatu hari melampaui guru yang pernah mendidikmu.” Ia menambah tekanan dalam kalimat terakhirnya. “Apakah ada figur lain yang mempengaruhi teologimu?” tanya Choan-Seng Song serius. “Marianne Katoppo.” “Marianne Katoppo telah menghilang lama. Apa aktivitasnya sekarang? Saya sudah lama tidak menemukan tulisan teologinya,” katanya sambil menerawang ke masa lalu. Percakapan terputus oleh ajakan untuk kembali masuk ruang kuliah.
Pertanyaan C.S. Song menggelayuti benak saya. Sepulang dari ruang kuliah saya langsung mencari informasi tentangnya di internet. Saya menemukan berita mengenai diskusi sastra yang mengupas novel Raumanen. Novelnya diluncurkan kembali dalam rangka 30 tahun sejak penerbitan pertama. Pada waktu lain saya menemukan alasan ia absen untuk berkontak dengan para sahabat teolog lain. “Saya kurang dukungan finansial untuk konferensi teologi. Selama ini saya mengongkosi sendiri perjalanan-perjalanan saya.”
Raumanen sebagai Syair Liyan
Marianne Katoppo memilih jalan kepenyairan karena ‘bentuk fiksi adalah cara yang bagus untuk mengungkapkan pemikiran, ide, cita-cita, dan impian kita.” Novel Raumanen memenangi sayembara penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta (1975), dan juga memperoleh penghargaan Yayasan Buku Utama (1978) dan SEA Write Award dari Ratu Sirikit (1982). Selain Raumanen, Marianne Katoppo juga menulis Novelnya yang Dunia Tak Bermusim (1974), Anggrek Tak Pernah Berdusta (1977), Terbangnya Punai (1978), dan Rumah Di Atas Jembatan (1981). Ia juga menerjemahkan novel-novel asing, seperti Malam karya Elie Wiesel dan Lapar karya Knut Hamsun. Korrie Layun Lampan menyarikan keunikan novel-novel yang ditulis Marianne Katoppo.
Novel pertamanya Raumanen (1977) memperlihatkan penuturan yang cerdas dengan menggali persoalan kejiwaan dan pandangan hldup para tokohnya. Terbangnya Punai (1978) menunjukkan lambang kemerdekaan dengan kisah cinta antarbangsa. Angrek Tak Pernah Berdusta (1979) menunjukkan penggaliannya pada segi suara hati, dan Dunia tak Bermusim (1984) mengangkat pengalaman pribadi saat dibukanya hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Korea Selatan.
Untuk kepentingan tulisan ini, penulis membaca novel Raumanen dan karya teologis Compassionate and Free secara serempak. Penulis membaca Raumanen sebagai syair perempuan sebagai Liyan (the other). Citra perempuan sebagai ciptaan Allah yang merdeka semakin kelihatan saat penulis membaca Raumanen. Compassionate and Free menanggapi pertanyaan-pertanyaan teologis yang diajukan Marianne Katoppo dalam Raumanen.
Bisakah cinta meruntuhkan benteng tradisi dan budaya? Apakah pria dan wanita melawan tekanan agama dengan cara yang sama? Apakah mistisisme masih punya tempat dalam kehidupan sehari-hari kita? Dari mana seorang wanita mendapatkan kekuatannya?
Penulis mengamati bahwa karya sastra jarang sekali dibaca dalam perbandingan dengan karya teologisnya. Akibatnya baik kritik sastra maupun kritik teologis kurang memadai hasil akhirnya. Kritikus sastra misalnya menemukan bahwa Marianne Katoppo menggambarkan karakter-karakter utamanya secara kurang utuh dan bahkan secara hitam putih. Sebagian pembaca menangkap Raumanen sebagai kisah perempuan yang dikalahkan nasib atau keputusasaan perempuan yang hanya mendapat sambutan cinta sebelah tangan. Sebagian pembaca kecewa dengan akhir kisahnya yang seakan menghapus semua gambaran awal yang positif mengenai karakter Raumanen. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang dikemukakan Raumanen sebagaimana tersebut di atas dianggap terlalu abstrak dan dilewatkan begitu saja.
Penulis memulai dengan melihat sejarah teks Raumanen. Marianne Katoppo pada awalnya menempatkan Raumanen sebagai bagian dari teks Dunia Tak Bermusim. Ia belakangan memperlakukan Raumanen sebagai teks tersendiri. Ia juga mengisahkan ekstase literer yang kemudian melahirkan Raumanen sebagai novel.
Mula-mula kisah inti Raumanen hanya merupakan salah satu bab dalam Dunia Tak Bermusim. Namun akhirnya kuhilangkan, karena rasanya patut menjadi cerita sendiri. Fokusnya lain, berbeda dengan fokus Dunia Tak Bermusim.”
“Lalu pada suatu sore yang hening, tiba-tiba ilham menyambarku. Aku seakan-akan melihat Raumanen berdiri di taman sunyi, menunggu tamu-tamu yang tak kunjung datang, mengharapkan teman-teman yang sudah lama pergi. Aku juga menyaksikan Monang datang, mencarinya.”
Melanie Budianta, pengajar ilmu budaya di Universitas Indonesia, menyoroti kecerdasan Marianne Katoppo dalam bereksperimen dengan struktur novelnya.
Raumanen beda dengan struktur novel populer lainnya, cara penceritaan di mana tokoh Monang dan Manen, diungkap bergantian. Di teks sastra dunia, penceritaan dua tokoh, yang menghadirkan pola back tracking jelas bukan hal yang baru. Namun di antara novel pop, bahkan di novel sastra Indonesia masa itu, eksperimen struktur tergolong sedikit.
Marianne Katoppo membuka novel dengan kesendirian Raumanen di rumah kecil di bawah pohon flamboyan tua. Teman-temannya mulai jarang menjenguknya. Monang, kekasihnya, jarang menengoknya karena ia takut ketahuan istrinya. Saat berkunjung ke rumahnya, Monang membawa bunga Mawar Kuning kesenangan Raumanen. Monang mengungkapkan keterpisahannya dari Rumanen.
Padahal sudah sepuluh tahun, Raumanen. Sudah sepuluh tahun, hampir seperempat hidupku, aku terpaksa hidup terpisah darimu.
Novel bergerak maju dengan mundur ke masa lalu tokoh-tokohnya. Pengarang menempatkan kisahnya di Jakarta pada awal tahun 1960-an. Ia memperkenalkan Raumanen Romokoi sebagai gadis Manado berusia 18 tahun yang cantik, mahasiswi hukum yang terlibat sebagai aktivis pergerakan mahasiswa, dan berasal dari keluarga yang terbuka. Nama Raumanen berasal dari bahasa Minahasa kuno yang berarti ‘gadis pembawa panen.’ Ia memperkenalkan Hamonangan Pohan sebagai jejaka Batak yang berasal dari keluarga kaya, arsitek. Monang merupakan kependekan dari Hamonangan yang berarti ‘Menang.’ Sejak awal pengarang menampilkan Raumanen dan Monang sebagai pribadi setara. Pengarang menggambarkan Raumanen Rumokoi sebagai perempuan dengan kepribadian kaya, sedangkan Hamonangan Pohan sebagai laki-laki dengan kekayaan pribadi. Keduanya berjumpa pertama kali di sebuah pesta di rumah seorang Profesor pelindung gerakan mahasiswa Kristen di Jakarta.
Pengarang memberikan keterangan tambahan mengenai Monang melalui teman-teman Raumanen. Mereka menggambarkan Monang sebagai laki-laki parlente yang sangat senang berganti pacar perempuan. Raumanen memandang relasi awalnya dengan Monang sebagai hubungan sebatas kakak dan adik. Benih-benih cinta keduanya berkuncup. Raumanen tak lagi memandang Monang sekedar sebagai kakaknya. Monang merasa Raumanen berbeda dibandingkan dengan gadis-gadis yang pernah dipacarinya. Ia melihat Raumanen sebagai gadis yang selama ini diidam-idamkannya.
Teman-teman Raumanen kembali memberikan peringatan karena melihat perkembangan relasi Raumanen dengan Monang. Ibunya menasehati Raumanen untuk serius dalam kuliah dulu. Pengarang menghantar pembaca pada realitas ‘chauvinisme regional’ yang kemungkinan menghalangi realasi antara Raumanen dan Monang.
Hampir 20 tahun sesudah revolusi, sesudah dua windu lebih penduduk Nusantara berpengalaman hidup sebagai “orang indonesia”, ternyata beban prasangka serta wasangka terhadap suku lain masih belum dapat dilepaskan dengan begitu mudah. “Orang Mana?” dan “Anak Siapa?” masih tetap jadi nada-nada pertama suatu perkenalan baru.
Perbuatan seksual antara Raumanen dan Monang akhirnya berlangsung di bungalow di Cibogo, di daerah Puncak. Perbuatan yang kemudian berlangsung berulang kali mengakibatkan kehamilan Raumanen. Alih-alih relasi seksual semakin menyakinkan Raumanen akan cinta Monang kepadanya, relasi seksual itu justru membuat Raumanen ragu akan ketulusan cinta Monang. Pacarnya lebih memperlakukannya sebagai obyek daripada partner seksual. Raumanen menghendaki Monang memiliki kebebasan dalam mencintainya. Ia akan menolak menikah dengan Monang jika pacarnya itu melakukannya sebagai kewajiban karena telah membuntingi Raumanen. Kehamilan Raumanen menjadi pintu masuk bagi Marianne Katoppo untuk membongkar ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, dan keterpasungan pribadi di bawah tekanan keluarga dan adat. Ia menolak peran istri sebagai obyek seksual dan hamba bagi suami.
Lagipula aku takut. Takut masa depan. Haruskah aku menjadi istri Monang sekarang? Membagi hidupku sekarang, mengarahkan cita-citaku agar serasi dengan cita-citanya?
Marianne Katoppo menghantar pembaca pada kisah Sahar dan Rachel yang memilih cinta dan berusaha membebaskan diri dari kungkungan adat dan keluarga yang berusaha menceraikan mereka. Keduanya memaksa Pastur di salah satu gereja untuk menikahkan mereka. Rencana mereka terhalang karena pastur membutuhkan waktu untuk mengurus administrasi mereka. Ibunya Rachel berpura-pura merestui relasi puterinya dengan Sahat dan meminta Sahat mengembalikan Rachel ke rumah. Sehari setelah kepulangan Rachel ke rumah, ibunya menyogok pastur untuk menikahkan Rachel dengan laki-laki lain yang bukan pilihannya. Kegagalan Sahat untuk menyunting Rachel yang menjadi pilihan hidupnya membayang-bayangi Raumanen.
“Siapa tahu Monang tiba-tiba berbalik seperti yang dilakukan Rakhel? Monang pun anak orang kaya yang manja.”
Keraguan Raumanen atas cinta Monang menjadi kenyataan. Ungkapan bahagia Monang atas kehamilan Raumanen dan janji untuk menikahinya hanya berusia sesaat. Raumanen melihat Monang sebagai orang asing yang memintanya untuk menanggalkan keinginan menikah dengannya. Monang mengusir Raumanen saat Raumanen dan sahabatnya tiba-tiba berkunjung ke rumahnya yang sedang mengadakan pesta. Monang semakin menjadi pribadi asing di mata Raumanen ketika menyodorkan Phillips, teman organisasinya dan dokter yang mengetahui kehamilannya pertama kali sebagai penggantinya. Monang melihat pernikahan dengan Phillips sebagai jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri hubungan dengannya. Alasan finansial semakin membongkar ketundukan Monang pada paksaan orang tua untuk menikah dengan perempuan yang dipilihkan mereka.
“Habis bagaimana? Tak usah begitu dramatis, Raumanen. Coba realistis dulu. Pikirkanlah, kau mau hidup dari apa nanti?gajiku Cuma 8000 rupiah sebulan. Sangkamu kita bisa hidup dari gaji itu, apalagi kalau sudah ada anak nanti?”
Raumanen membayangkan tanggapan negatif masyarakat yang memandang relasi mereka sebagai yang belum direstui Tuhan namun sudah menguncupkan kehidupan. Ia berjumpa dengan masyarakat yang memandang rendah perempuan yang telah kehilangan keperawanan fisiknya.
Bila kami nanti naik ke pelaminan, bersama-sama, bila kelak kami bersujud di hadapan pendeta, semua akan mencibir, akan memandang kami dengan cemooh dan benci, karena mereka sudah tahu bahwa sebelum direstui Tuhan dan manusia Manen dan Monang sudah mencicipi cawan cinta itu.
Raumanen bergumul sendirian dengan kuncup kehidupan dalam rahimnya. Kuncup kehidupan baru kemungkinan besar akan lahir cacat karena penyakit seksual Monang menularinya. Padahal, ia berharap bahwa anaknya lahir untuk terlibat membentuk sejarah. Selama beberapa waktu ia dapat menjaga kuncup kehidupan itu sehingga ia dapat mengalami kehidupan di dalam rahimnya. Raumanen berada dalam posisi terjepit karena ia tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan bayi jika ia ia melahirkannya di dunia dalam keadaan dijangkiti penyakit. Saat bayi itu diaborsi, Marianne Katoppo sama sekali jauh dari maksud menawarkan jalan keluar mudah dari situasi sulit yang dialami karakter rekaannya. Pengarang justru mau membongkar praktek aborsi sebagai jalan sesat yang sering dipakai masyarakat untuk mengakhiri kehidupan yang tidak dikehendakinya.
Ia bergumul dengan perintah Tuhan, “Jangan membunuh.” Pergumulan dengan orang-orang terdekatnya dan Tuhan banyak mencurahkan air matanya. Ia menjumpai pribadi Tuhan sebagai ‘Yang Lain.’ Ia belum pernah menjumpai Pribadi ini dalam kehidupan imannya maupun dalam kehidupan gerejanya. Raumanen belum dapat berbicara lebih lanjut mengenai pengalaman spiritual ini. Raumanen menyingkap sedikit misteri perjumpaan dengan Tuhan barunya saat ia mengakhiri kehidupannya. Pengarang mengundang pembaca untuk memberi makna atas kematian dini Raumanen. Apakah pilihan bunuh diri merupakan akhir dari puncak keputusasaanya terhadap hidup? Ataukah, ia justru menjemput kehidupan lain karena ia menjumpai penolakan di kehidupan bumi? Marianne Katoppo membuka kesempatan kepada pembaca untuk memilih akhir kisah novel dengan menjawab pertanyaan di atas. Ia menyingkapkan jawabannya dengan cara istimewa, yaitu menempatkannya di dalam puisi Kahlil Gibran.
“Karena maut dan kehidupan itu
satu adanya.
Sama seperti sungai dan samudra satu jua
Karena mati itu tak lain dari
berdiri telanjang dalam badai
serta bersatu dengan matahari
Dan berhenti bernafas tak lain dari pada menceraikan nafasmu
dari pasang surut yang tak kunjung henti
Hingga kau dapat naik serta mekar mencari Ilahi.”
Dialog Sastra dan Teologi
Pada bagian pertama tulisan, penulis membaca karya sastranya dari perspektif teolog laki-laki pro-feminis katolik Indonesia. Sebagaimana nampak dalam ulasan penulis, beberapa bagian novel menjadi lebih terbaca karena penulis menempatkan Raumanen dalam dialog dengan Compassionate and Free. Marianne Katoppo istimewa di mata penulis karena ia mengawali dialog antara sastra dan teologi di Indonesia. Sepanjang pengetahuan penulis, ia tidak pernah menulis artikel tentang dialog ini. Ia pernah merujuk Maria de Groot sebagai teolog dan ahli bahasa yang membuka matanya terhadap kenyataan dominasi simbol laki-laki yang melumpuhkan pewahyuan. Ia juga merujuk Karl Rahner yang melihat kemungkinan teolog sebagai penyair. Marianne Katoppo melangkah lebih jauh daripada sekedar berbicara tentang dialog sastra dan teologi. Ia mempraktekkannya baik dalam karya sastra maupun teologisnya Karya-karya sastranya mengangkat gagasan teologis dan karya-karya teologisnya yang ditulis dengan kecerdasan seorang sastrawi menarik perhatian penulis.
Marianne Katoppo berhasrat untuk membangun sebuah teologi perempuan Asia. Ia memahami teologi baik sebagai disiplin maupun sebagi refleksi kritis mengenai Allah. Ia ingin mengangkat pengalaman perempuan kristiani Indonesia akan Allah. Ia memandang Gereja sebagai institusi patriarkal yang terlibat dalam menciptakan penderitaan bagi perempuan dan rakyat miskin. Gereja buta terhadap perempuan yang mengalami diskriminasi, perendahan, dan penindasan. Mereka juga meremehkan pengalaman perempuan akan Allah sebagai histerik, bahkan mendakwanya sebagai heretik. Ia ingin melukis Kristus sebagai Kristus sebagai Pribadi berbelas kasih dan merdeka yang melawan struktur-struktur penindasan. Sebagaimana novel Raumanen, karya teologisnya Compassionate and Free membutuhkan pembacaan ulang dengan kepekaan akan ratapan perempuan dan harapan mereka untuk menjadi pribadi yang merdeka yang mengasihi Allah dan sesama.
Namaku Liyan
Marianne Katoppo melihat lukisan dirinya sebagai liyan. Ia seorang kristiani diantara saudara-saudari Muslim dan ia seorang perempuan Minahasa dimana laki-laki dan perempuan memiliki posisi setara yang hidup dalam masyarakat Jawa yang menekankan superioritas laki-laki atas wanita. Ia mengamati bangsa Indonesia bergerak dari kesadaran akan kedaerahan menuju kesadaran nasional. Transformasinya dari masyarakat tradisional menuju masyarkat industri dan sekular, dan kemudian menuju masyarakat pluralistik bergerak lambat. Ia juga melihat dirinya sebagai liyan dalam Gereja Indonesia, bahkan mungkin Asia.
Marianne Katoppo juga menangkap lukisan diri perempuan Asia sebagai liyan. Anak yang menikah pada usia dini, istri siri, petani, buruh pabrik, kuli perkebunan, anak-anak balita perempuan yang kekurangan gizi, dan anak gadis yang dijual orang tuanya bernama perempuan. Ia bernama Rosmala yang bkerja sebagai pemijat panggilan di hotel. Mereka dapat bernama Inem dan Ina, dua perempuan kristiani yang bekerja di lokalisasi Kramat Tunggak. Mereka seringkali tak dikenali namanya, namun penderitaannya tergambar dari pekerjaan mereka. Mereka adalah perempuan yang menjadi buruh di perkebunan teh, buruh pemecah batu, dan buruh pabrik yang mukanya dipermak tahi manusia karena menuntut hak mereka. Mereka dapat bernama profesi buruh kontrak, istri kontrak, pelacur, dan babu. Mereka hilang kepribadiannya dan tinggal menjadi komoditas. Penderitaan juga dapat mengambil wajah laki-laki dan perempuan di Bali yang beralih dari sektor produktif ke sektor jasa pelayanan tubuh mereka. Namun mereka dapat pula bernama Mari Ulfah Santoso dan S.K. Trimurti yang duduk dalam kabinet Republik Indonesia dan nama-nama lain yang menjabat posisi publik.
Faktor budaya dan pendidikan menciptakan kondisi bagi perempuan Indonesia untuk berperan sebagai suruhan, budak, dan obyek seksual. Pelucutan citra sejati perempuan terjadi baik dalam sejarah maupun dalam cerita mitos. Sebutan wanita dan penghilangan nama perempuan setelah pernikahan untuk mengikuti nama suaminya juga menunjukkan perendahan perempuan dalam bahasa. Saat menilik beberapa budaya Indonesia, ia menemukan perempuan berperan utama dan berdaulat. Perempuan dapat berperan seorang ibu bagi anak-anak yang lahir dari luar rahimnya dengan jalan mengasihi dan mendidik mereka.
Marianne Katoppo berteologi di tengah arus masyarakat Indonesia, bahkan Asia yang sedang giat membangun dirinya. Ia kritis terhadap ‘pembangunan’ karena kata ini semakin menjadi sinonim dari perbudakan kontemporer. Pembangunan semakin menjadi kata ganti untuk kuasa mammon. Gaya hidup borjuis dapat dianggap sebagai tanda kehadiran persaudaraan sebagai putera-puteri Allah (the kin-dom of God). Teologi gagal jika ia justru menjadi aktivitas bertele-tele dengan konsep abstrak. Teolog telah menjauhi panggilan awalnya ketika ia bergabung dalam klub borjuis yang berperut buncit dan ‘memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang.’ Ia juga menggugat Gereja yang satu kaki bernama ‘ibadat’ berkubang pada lumpur kemewahan dan sebelah kaki bernama ‘pelayanan’ berjingkat-jingkat menghindar dari terpercik tanah penderitaan. Teologi Asia dikerjakan dalam desakan waktu dengan pertaruhan hidup-mati manusia Asia. Ia memgongkar kuasa-kuasa mammon atau Anti-Allah yang merusak kekayaan material sehingga akhirnya bersifat anti-manusia, anti-agama, dan menindas. Apakah pembangunan ekonomi berarti mengorbankan Liyan? Apakah kita menemukan Allah dalam diri Liyan? Gereja hendak mengidentifikasikan dirinya dengan siapa? Apakah Gereja peduli dengan rakyat miskin?
Allah sebagai Liyan
Marianne Katoppo meminjam gambaran biblis ‘perempuan yang sakit bertahun-tahun hingga punggungnya bungkuk dan tidak dapat berjalan lagi’ untuk berbicara tentang situasi perempuan di Asia. Perempuan merindukan Tuhan meletakkan tangan atas mereka sehingga mereka dapat berdiri tegak lagi sebagai manusia. Marianne Katoppo juga meminjam gambaran ‘kepala rumah ibadat yang gusar karena Tuhan mentahirkan perempuan pada hari Sabat’ untuk berbicara mengenai perilaku Gereja. Institusi gereja yang memiliki potensi kekuasaan untuk berbicara kepada masyarakat dan melakukan perkara mulia kepada perempuan justru terlibat dalam melanggengkan penekukan paksa terhadap kehidupan perempuan. Ia taat buta dengan aturan ibadat dan buta terhadap kuasa anti-Allah yang menekuk kehidupan perempuan.
Marianne Katoppo menampilkan Maria sebagai model manusia merdeka (liberated human being). Maria berdaulat sebagai pribadi karena ia berelasi setara dengan Yosef. Ia kehilangan kedaulatannya seandainya ia menghamba pada suaminya. Ia menggunakan kebebasannya untuk mengasihi Allah. Ia bekerja keras untuk dapat memberi makan dan pakaian kepada Yesus. Ia berperan penting sebagai ibu yang mendidik Yesus untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Ia terlibat dalam pewartaan Injil keselamatan kepada dunia. Ia menjadi pendamping setara Yosef yang bekerja sebagai tukang. Maria memiliki kepekaan sebagai ibu terhadap ketidakadilan yang menekuk kehidupan manusia. Ia mengambil resiko dengan kehidupannya demi masyarakat yang lebih adil. Laki-laki dan perempuan berpaling kepada Maria karena ia menjadi personifikasi mereka yang kehidupannya direnggut penderitaan. Maria juga menjadi simbol mereka untuk mengembalikan kembali citra mereka sebagai manusia.
Sebagian teolog mengungkapkan kehati-hatiannya, bahkan berpaling dari Maria sebagai simbol manusia yang berbelas kasih dan merdeka. Mereka menolak penggambaran Maria sebagai gadis berparas elok, ringkih, dan pandangan matanya menunduk ke tanah atau menatap ke langit. Penggambaran demikian justru menjadikan Maria sebagai obyek yang dapat disalahgunakan untuk menjinakkan perempuan dan melumpuhkan korban-korban lain yang mengalami penderitaan. Mereka melihat bahaya serius dari ungkapan Maria “Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu” sebagai teks yang dapat dipelintir untuk membenarkan penghambaan perempuan kepada laki-laki (male chauvinism).
Marianne Katoppo menyegarkan lukisan kita akan Maria sebagai perempuan-manusia dengan menilik bahasa yang dipergunakan kitab suci untuk menyebut Maria. Ia menafsirkan keperawanan Maria secara simbolik religius. Keperawanan tidak menunjuk kepada fakta fisik, tetapi kepada sikap batin. Keperawanan fisik menghilang begitu perempuan melakukan hubungan seksual, mengasuh anak, dan beranjak lansia. Keperawanan batin tetap bersemayam meskipun perempuan telah melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Arti utama keperawanan adalah kemerdekaan sebagai manusia. Maria menghamba kepada manusia lain, melainkan ia mengabdi kepada Allah. Ia mengungkapkan kesuburannya sebagai manusia dengan memberikan kehidupannya kepada Allah. Selain mengoreksi pandangan umum keliru mengenai pribadi Maria, Marianne Katoppo juga mengajukan revisi terhadap citra keliru yang dikenakan gereja kepada Allah. Dibandingkan teolog berbahasa Inggris, Belanda, dan Jerman, teolog Indonesia tidak berhadapan dengan persoalan dengan kata ganti untuk menyapa Allah. Meskipun demikian Marianne Katoppo mendeteksi beberapa teolog laki-laki berusaha melakukan penekukan eksegetis (exegetical contortion) untuk menghindari menghubungkan belas kasih Allah (rechamim) dengan aspek feminin Allah. Ia juga mengikuti terjemahan Roh Kudus (Ruach) yang semula berjender perempuan dalam bahasa Ibrani, kemudian berubah berjenis kelamin netral dalam bahasa Yunani, dan akhirnya menjadi laki-laki dalam bahasa Latin.
Tuhan, Raja, Bapa, dan Penguasa adalah sebagian citra laki-laki yang dikenakan kepada Allah. Marianne Katoppo mengundang kita untuk melihat pula citra Allah sebagai Ibu, Penghibur, Pemberi Kehidupan, Kebijaksanaan (Hokmah), dan Kehadiran (Shekinah). Selain menampilkan citra-citra lain, Marianne Katoppo juga mengoreksi sebutan-sebutan kepada Allah yang sepintas mendukung Allah sebagai yang berjenis kelamin laki-laki. Sapaan Allah sebagai Bapa melukiskan kesuburan dan kreativitas illahi yang memperhatikan umat-Nya dengan penuh kasih. Kebebasan tanpa kungkungan merupakan esensi dari Roh Kudus. Clement dari Alexandria, Anselmus dari Canterbury, dan bahkan Paus Yohanes Paulus I mengakui keibuan Allah.
Teologi sebagai Puisi
Sebelum mengakhiri tulisan, saya membuat beberapa catatan terhadap karya teologis Marianne Katoppo. Ia pelan-pelan mengubah pandangan penulis yang semula memperlakukan dia sebagai esais Allah menjadi penyair Allah. Ia menjauhkan diri dari citra teolog sebagai seseorang yang menekuk Allah dalam sebuah formulasi teologis yang berlekuk-lekuk. Menyitir Czesław Milłosz dari Lithuania, seorang penyair melakukan ‘an expedition not in search of the golden fleece of a perfect form but as necessary as love.’ Milłosz mengulang pesan serupa dalam dialog dengan teolog.
Thus, brother theologian, here you are,
Connoisseur of heaven and abysses,
Year after year perfecting your art,
Choosing bookish wisdom for you mistress,
Only to discover you wander in the dark.
Marianne Katoppo menggali teks kitab suci, karya teolog gereja, tradisi religius dan budaya lain untuk menemukan bahasa yang yang menyingkapkan pengalaman perempuan akan Allah. Penulis mengamati beberapa saat lelah yang dialami Marianne Katoppo. ‘Tak seorang pun dari kami tahu jika ada laki-laki yang memiliki rahim.’ ‘Bagaimana perempuan mengalami dirinya sebagai citra Allah jika Allah penciptanya berkelamin laki-laki?’ Ia kurang hati-hati saat menjatuhkan penilaian kepada Gereja sebagai institusi dengan bahasa dan praktek seksis. Ia perlu lebih memberi perspektif sejarah Gereja kepada pembaca sehingga mereka dapat melihat dinamika real Gereja yang bergumul melepaskan dirinya sebagai institusi patriarkal. Ia kadang-kadang menampilkan Gereja sebagai realitas singular dengan satu suara vokal. Pencarian kata yang lebih menyapa Allah bukan merupakan tujuan akhir aktivitas penyair Allah. Pencarian perempuan akan lukisan yang semakin utuh mengenai Allah memekarkan harapan akan pembebasan-keselamatan manusia Asia.

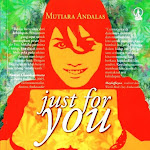
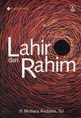




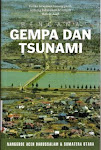












No comments:
Post a Comment