
http://www.foxnews.com/images/260542/0_62_020507_indonesia_floods.jpg
Bab 2
Tanah Asia bergejolak
saat penginjil menabur benih kristianitas.
Pada bab pertama, penulis menyingkapkan pergumulan personal-akademik dengan feminisme dan teologi perempuan. Bab ini menghantar pembaca untuk memasuki hati teologi perempuan dengan meletakkannya pada konteks
Robert Schreiter menawarkan tiga pendekatan kunci kepada teolog agar lebih memiliki hati dalam mendengarkan budaya. Pertama, kita hendaknya melihat budaya secara holistik. Agama sekaligus merupakan jalan dan pandangan kehidupan. Teolog seringkali membedakan teologi, magis, dan superstition. Namun antropologi memandang ketiganya sebagai manifestasi dari satu realitas yang sama. Kita dengan demikian diharapkan terbuka terhadap kepercayaan dan praktek agama yang selama ini terabaikan. Kita diharapkan juga menilik fenomena-fenoma non-religius terutama dalam konteks budaya sekular dan anti-agama.
Kedua, kita hendaknya memperhatikan kekuatan-kekuatan yang membentuk identitas dalam suatu budaya. Sebuah masyarakat budaya menarik garis pembeda diri mereka dengan yang lain, dan memiliki pandangan terhadap dunia. Garis pembeda diri ini dalam beberapa budaya jelas, sedangkan dalam beberapa budaya lain lebih kabur. Teolog diharapkan melihat tarik menarik dinamis antara garis pembeda dan pandangan dunia ini.
Ketiga, kita hendaknya menangkap dinamika perubahan sosial. Kita seringkali mandeg dalam melihat masyarakat. Teologi pembebasan, misalnya, mempertanyakan perilaku Gereja dalam relasi dengan Allah di tengah situasi kemiskinan dan kekerasan politik. Perapatan ruang dan waktu dunia karena kemajuan telekomunikasi, ekonomi independen, dan urbanisasi global mengubah peta dunia. Kita diharapkan peka terhadap kemajuan, kemandegan, dan bahkan kemunduran yang mungkin terjadi karena perubahan sosial.
Schreiter mengusulkan pendekatan semiotik terhadap budaya sebagai terusan lebih lanjut komprehensif terhadap tiga pendekatan kunci di atas. Pendekatan semiotik melihat budaya sebagai jaringan komunikasi, dimana berlangsung sirkulasi pesan verbal dan non-verbal, yang membentuk sistem makna. Pembawa dan penerima menyusun serangkaian kode atau seperangkat aturan sehingga pesan dapat dimengerti atau ditafsirkan secara benar. Pendekatan interdisiplinernya dan perhatiannya pada semua dimensi kebudayaan, baik verbal maupun non-verbal, baik empiris maupun non-empiris, menghindari reduksi dan determinisme budaya. Pengamatannya pada beragam sistem tanda dalam suatu budaya dan konfigurasinya membantu kita untuk melihat identitas suatu budaya dan sekaligus menghindari bahaya etnosentrisme. Perhatian pada pola-pola perubahan mengundang kita untuk melihat perubahan lebih dari sekedar penyimpangan terhadap identitas.
Pendekatan semotik terhadap budaya membuat kita lebih sadar akan posisi kita sebagai orang dalam sehingga kita dapat mengharapkan suara otentik atau orang luar sehingga kita dapat mengharapkan untuk berhubungan dengan perubahan dan komunikasi lintas budaya. Perspektif pembicara membantu kita menjaga integritas tradisi. Perspektif pendengar membantu kita untuk melihat kelanjutan hidup tradisi. Tugas berikutnya adalah membaca teks budaya yang tersimpan atau tersembunyi dalam perayaan bersama atau dalam karya seni. Budaya memiliki pesan lebih dari satu dan dalam saat perubahan kita perlu menyeleksi pesan-pesan tersebut karena semuanya tumpang tindih untuk mendapat tempat utama. Komunitas agama, misalnya, perlu mendeskripsikan pengalaman keselamatan dari kejahatan dosa dalam suatu budaya.
Virginia Fabella dari Filipina mengundang kita untuk peka terhadap realitas plural Asia sebagai lokasi berteologi. Para teolog kristiani Asia berteologi dari benua dimana kurang lebih 97% penduduknya memeluk agama-agama lain.
Pluralisme agama, budaya, dan bahasa membedakan benua Asia dari Dunia Ketiga lain. Asia sekurang-kurangnya memiliki tujuh zona besar bahasa, lebih daripada yang dapat diklaim benua lain. Ia merupakan rahim yang melahirkan semua agama besar dunia, dengan perkecualian agama kristiani dan yahudi, Asia merupakan rumah kehidupan bagi sebagian besar pemeluknya.
Virginia Fabella melanjutkan pernyataannya dengan pertanyaan yang menohok ulu hati komunitas kristiani. Di benua Asia dapatkah komunitas kristiani mendaku Yesus Kristus sebagai penebus seluruh dunia? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai penebus yang unik dan universal, sementara mayoritas warga Asia belum pernah mendengar tentang-Nya atau menolak-Nya dalam peziarahan mereka untuk dunia yang lebih baik?
Persoalan yang mengemuka saat penulis hendak berbicara lebih lanjut mengenai realitas Asia adalah menarik garis waktu. Kesadaran poskolonial menyadarkan penulis untuk lebih peka terhadap waktu. Menyitir R.S. Sugirtharajah, masa depan semakin terbuka, sedangkan masa lalu semakin terbuka pada perubahan. Sebagian teolog kristiani menarik garis waktu sejak dari periode para penyebar Injil menginjakkan kaki di tanah misi. Studi-studi teologis kemudian melihat kehadiran penyebar agama-agama lain di tanah Asia. Para teolog ini peka terhadap agama-agama dan budaya-budaya lain yang lebih dahulu menjejakkan kaki di Asia. Para misionaris membawa pesan Injil di benua Asia yang sudah menganut keragaman agama dan budaya. Tulisan-tulisan di sekitar perjumpaan antara Gereja dengan masyarakat Asia acapkali mengabaikan perjumpaan komunitas agama dan budaya lain dengan masyarakat Asia. Penulis mengundang pembaca untuk selalu menyadari fakta ini setiap kali kita membicarakan perjumpaan komunitas kristiani dengan komunitas agama dan budaya lain di Asia.
Meskipun lahir di Asia, masyarakat Asia memandang agama kristiani sebagai agama asing yang dibawa dari penginjil Eropa kurang lebih bersamaan dengan pedagang Eropa yang melakukan ekspansi ekonomi. Para pedagang Eropa kemudian meluaskan ekspansinya ke ruang politik pula. Ekspansi ekonomi-politik sedemikian berhimpitan dengan penginjilan sehingga masyarakat Asia kemudian memandang kristianitas sebagai bagian dari unholy trinity ‘Gold, Glory, and God.’ Para penginjil kristiani bergumul untuk melepaskan kelekatan agama kristiani dengan penjajahan. Pada saat yang sama mereka mewartakan pesan Injil kepada masyarakat Asia. Penulis menyadari tulisan-tulisan teologis di sekitar tema ini berangkat dari perspektif kristiani. Kwok Pui-lan mengundang kita untuk ‘menemukan Injil dalam Dunia non-Injil.’ Yasuko Morihara Grosjean mengajukan klaim pembebasan perempuan di Jepang perlu dikaitkan dengan kedatangan budaya Barat, terutama kristianitas. Salib pada awalnya menjadi simbol penindasan baru sebelum akhirnya kristianitas menggerakkan masyarakat Filipina untuk melawan penindasan.
Nantawan Boonprasat Lewis melihat 1940-an dan 1950-an sebagai periode keterlibatan perempuan dalam gerakan kemerdekaan, dan periode 1960-an dan 1970-an sebagai periode partisipasi perempuan dalam hak asasi manusia. Periode selanjutnya adalah perjuangan masyarakat Asia untuk mengusir penjajahan. Penolakan atau keterlibatan setengah hati Gereja dalam perjuangan bersama melawan penjajahan kemudian memunculkan istilah ‘gereja kaisar’. Sebaliknya partisipasi dalam perjuangan yang seringkali mengakibatkan penderitaan bagi Gereja membuat Gereja semakin berakar di tempat barunya. Marianne Katoppo, penyair Allah perempuan Indonesia, mengangkat tema nasionalisme yang melampaui sekat-sekat etnik dan agama dalam karya teologi-sastranya. Ia mendeteksi bahwa gerakan perempuan di Indonesia tumbuh bersama dengan gerakan politik untuk kemerdekaan.
Periode setelah kemerdekaan negara-negara Asia juga membawa babak baru dalam perkembangan teologi Asia. Gereja bergumul untuk membangun dirinya sebagai Gereja lokal dengan tetap menjaga roh Gereja perdana. Para teolog juga bergumul untuk menyusun teologi yang berakar pada tanah Asia. Mereka kritis terhadap teologi-teologi yang dikembangkan di belahan dunia lain yang kurang peduli, bahkan mengabaikan realitas Asia. Kritik terhadap teologi yang dikembangkan di Barat ini kemudian mendorong mereka untuk menyusun teologi dari masing-masing lokasi di Asia. Teolog juga menangkap bentuk-bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain.
Konteks-konteks baru tersebut memacu teolog Asia untuk mengembangkan teologi-teologi baru sebagai tanggapan atasnya. Teologi pembebasan adalah teologi yang berkuncup, bermekar, dan berbunga dalam praksis/proses pembebasan. Teologi pembebasan Asia merupakan tanggapan terhadap realitas rakyat tersalib yang berlawanan dengan pesan kehidupan yang diwartakan Yesus. Teologi dialog antarbudaya dan antaragama merupakan refleksi lebih lanjut terhadap keberadaan Gereja di tengah-tengah budaya-budaya dan agama-agama lain yang membentuk masyarakat Asia. Ia menggugat paradigma lama terhadap budaya-budaya dan agama-agama lain di Asia sebagai primitif dan anti-kristiani. Marianne Katoppo peka terhadap kecenderungan teolog Indonesia untuk menggenggam warisan lama teologi Eropa yang menumpulkan teologi Indonesia. Teologi poskolonial Asia yang dikembangkan Kwok Pui-Lan kritis terhadap warisan kolonial yang masih menempel pada masyarakat dan Gereja Asia setelah penjajahan berakhir. Teologi perempuan membongkar masyarakat dan agama patriarkal yang menggagahi kemanusiaan perempuan, dan mengklaim kembali kemanusiaan perempuan sebagai puteri Allah. Ia mengangkat perkara-perkara perempuan yang seringkali dilewatkan, bahkan disembunyikan secara sistematik oleh teologi-teologi yang mengidap bias patriarkal.
Teologi perempuan Asia merayakan keberadaan perempuan dan kontribusi mereka di masyarakat dan Gereja. Perempuan kristiani Asia menamai dan mendaku kontribusi mereka di masyarakat dan Gereja dari tepian (boundary existence). Aruna Gnanadason dari India melihat bahwa teologi perempuan pada tahun 1983 – 1984 bukan muncul dari perubahan dalam Gereja, melainkan dari gerakan perempuan baik di pedesaan maupun perkotaan. Teolog perempuan Asia mencari bahasa-bahasa baru untuk dalam teologi selain bahasa tulisan. Ia berbeda dari teologi perempuan di tempat lain karena perbedaan konteks masyarakat dan Gereja. Kwok Pui-lan menyatakan bahwa teolog perempuan Asia dipanggil
untuk memahami kode-kode budaya masyarakatnya, masuk ke dalam sumber-sumber tradisi Asia yang kaya, dan belajar untuk bertutur dengan orang miskin perempuan di Asia sebelum mereka dapat menyusun suatu teologi yang menyentuh jiwa manusia Asia.
Proyek teologi perempuan Asia lebih luas daripada perubahan bahasa mengenai Allah. Para teolog perempuan Asia menyadari sisi penting bahasa inklusif mengenai Allah. Bahasa membentuk kesadaran dan memiliki kuasa untuk menyatakan realitas. Meskipun demikian teologi perempuan Asia tidak menempatkan pencarian bahasa yang lebih inklusif untuk Allah sebagai prioritas utama. Keadilan jender lebih menjadi perhatian utamanya. Perjuangan pada level simbolik-budaya belum memadai untuk meraih keadilan jender. Ia harus diraih dengan perjuangan sosial-politik. Dalam kaitan ini, mereka menghindari ketimpangan konstruksi jender yang menggambar perempuan sebagai baik dan laki-laki sebagai jahat. Selain ketidakadilan gender, para teolog perempuan Asia juga memperhatikan isu ras, kelas, heteroseksisme, dan kolonialisme. Mereka ingin membangun teologi yang secara intrinsik anti-diskriminasi jender, ras, kelas, dan kolonial. Teologi perempuan Asia melawan segala bentuk imperialisme. Ia mengundang dan menyambut kehadiran pro-feminis dalam perjuangan mereka.
Penulis merasa perlu untuk berbicara lebih lanjut mengenai beberapa keprihatinan masyarakat abad 20 dan awal 21 ini yang memerlukan perhatian lebih serius dari teolog kristiani. Abad 20 merupakan abad ilmu dan teknologi. Kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang ini memberi kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk berkuasa atas alam. Dunia mengalami perpecahan dan manusia perlu menata kembali relasi antarciptaan dalam ekologi yang damai dan adil. Leviatan itu bernama manusia. Alih-alih semakin menyatukan manusia, kemajuan ilmu dan teknologi faktanya justru semakin mengecualikan rakyat miskin. Ilmu dan teknologi mengalami kegagalan untuk menjinakkan leviatan bernama manusia. Ia juga terbatas untuk menjawab pertanyaan mengenai solidaritas antarciptaan. Marianne Katoppo, teolog kristiani perempuan Indonesia, bergumul dengan kata ‘pembangunan’ yang disucikan para pendukung ideologinya dan melucuti kuasa-kuasa Anti-Kehidupan yang menggagahi dan merenggut kemanusiaan Asia.
Absolutisme atau totalitarianisme politik juga menandai abad ini. Pemasungan demokrasi, penangkapan tokoh-tokoh pro-demokrasi, kekerasan negara-militer merupakan fenomena mencolok di bidang politik. Negara-negara yang diatur dengan cara militer seringkali melakukan kekerasan bersenjata terhadap warganya hingga kudeta bersenjata terhadap negara. Suara-suara korban kekerasan militer-negara yang terpampang di depan mata kita pun masih kesulitan untuk menembus pintu keadilan hukum. The Tears of Lady Meng, pembacaan baru terhadap penderitaan korban yang dipaksa membangun tembok besar Cina, karya Choan-Seng Song yang mengkritik rezim Cina melakukan kekerasan politik terhadap warganya. Teolog perempuan Asia diharapkan juga menceburkan diri dalam bidang teologi politik untuk ‘mengubah paradigma lama eros politik menjadi paradigma baru spiritualitas politik.
Keprihatinan lain yang gawat adalah absolutisme ekonomi. Ia seringkali dilekatkan dengan kata globalisasi. Beragam definisi mengenai globalisasi baik dari perspektif politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan mengingatkan kepada kita akan kompleksitas dan keterbatasan pendekatan tunggal untuk menyingkapkan fenomena globalisasi. Masing-masing definisi dengan demikian memberikan sumbangan kepada kita untuk lebih memahami globalisasi. John Tomlinson dalam Globalization and Culture (1999) memahami globalisasi sebagai ‘jejaring keterkaitan yang bergerak cepat dan merapat dan kesalingtergantungan yang mewarnai kehidupan sosial.’ Tomlinson mendorong diskusi lebih jauh dengan menyatakan bahwa budaya berarti bagi globalisasi dan globalisasi berarti bagi budaya. Budaya merupakan aspek intrinsik, bahkan unsur konstitutif dari proses keterkaitan kompleks tersebut. Tindakan-tindakan dasar kita, seperti menguruskan tubuh, berpuasa selama bulan suci agama, atau protes dengan mogok makan, merupakan keputusan-keputusan budaya. Globalisasi mengubah paradigma lama kita terhadap budaya yang melekat pada lokalitas yang tetap. Globalisasi memperlemah ikatan budaya dengan lokalitas (deterritorialization). Ia juga mendorong kita untuk lebih memiliki kesadaran akan budaya global.
Globalisasi ekonomi merupakan proses ekonomi sekaligus menawarkan jalan kehidupan beserta sistem nilainya. Negara-negara Dunia Pertama memandang globalisasi seolah-olah sebagai agama dunia baru. Globalisasi menyatukan semua orang yang semula tersekat oleh batas-batas geografi, politik, budaya dan ekonomi. Para pendukungnya berjanji menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Mereka, baik negara-negara maju maupun korporasi trans-bangsa, berjanji pula mengulurkan bantuan kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi.
Felix Wilfred menilai secara kritis globalisasi ekonomi sebagai peminggiran, bahkan pelupaan terhadap rakyat miskin dan peredupan kesadaran sosial. Globalisasi ekonomi dalam kenyataannya sekarang membuncitkan perut pelaku besar ekonomi. Keberpihakan komunitas agama pada orang miskin dalam konteks demikian berarti melawan totalitarianisme ekonomi yang mengorbankan rakyat dan negara miskin secara brutal. Felix Wilfred menengarai teolog kristiani Asia belum menanggapi pertanyaan ekonomi-kehidupan ini secara memadai. Teolog kristiani Asia gagap saat korban globalisasi mengadu kepada mereka dengan persoalan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Sekarang adalah nama bagi rakyat miskin di tengah gelombang arus globalisasi. Korban globalisasi mengisahkan perlawanan gigih mereka melawan leviathan ekonomi. Korban globalisasi memberi pesan kepada teolog kristiani akan ancaman kematian dini mereka dan penolakan Allah kehidupan terhadap totalitarianisme atau absolutisme ekonomi yang menggagahi kehidupan putera-puteri-Nya.
Ira Rifkin dalam Spiritual Perspectives on Globalization melihat sumbangan agama-agama peran dalam memberi makna kepada komunitas di tengah pergolakan ekonomi dan budaya karena globalisasi. Rifin merangkum gagasan Paus Yohanes Paulus II sebagai wakil komunitas Gereja Katolik terhadap globalisasi.
Gereja Katolik memiliki wawasan dan praktek universal, dan dengan demikian menyambut janji globalisasi yang menyatukan manusia. Meskipun demikian penerapan globalisasi cacat berat karena kompetensi ekonomi saja tidak mencukupi. Pertumbuhan ekonomi harus adil bagi semua, tertauma mereka yang paling lemah untuk berkompetisi. Hal ini merupakan makna dari martabat manusia dan keadilan. Hal ini menciptakan komunitas. Hal demikian mendukung perdamaian. Hal demikian memungkinkan keutuhan spiritual bagi kemanusiaan. Inilah ajaran Yesus Kristus.

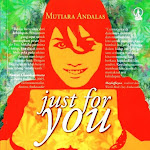
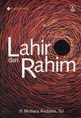




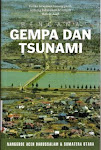












No comments:
Post a Comment