Mutiara Andalas, S.J.
AKSI KAMISAN, NEGARA KRIMINAL DAN TEOLOGI POLITIK
Semoga fajar merekah sebelum mataku
yang berpeluh duka terkatup selamanya.
Sun Ai Park[1]
|
|
Pertengahan November 2008 Indonesia memperingati satu dasawarsa tragedi kemanusiaan Semanggi.[2] Tragedi berdarah Semanggi II menyusul pada tanggal 24 September 1999. Dokumentasi tragedi merekam pornografi kekerasan aparat keamanan yang mencederai, bahkan merenggut kemanusiaan korban secara paksa. Satu dasawarsa seperti baru berlangsung kemarin bagi sebagian keluarga korban. Mereka yang terpaut jauh dari tragedi cenderung melupakannya. Perhatian mereka telah beralih pada perkara-perkara kemanusiaan lain. Melawan propaganda politik dan arus waktu yang melucuti kenangan atas tragedi, paguyuban keluarga korban menyelenggarakan aksi Kamisan. Mereka berdiri hening dengan pandangan terarah ke istana presiden. Mereka mengingatkan bangsa Indonesia akan rezim kriminal yang telah merenggut kehidupan anak-anaknya.
Sebelum melangkah lebih lanjut, penulis mengungkapkan alasan pribadi mengangkat tema ini. Penulis pernah aktif dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TruK) yang terlibat dalam menyelamatkan korban tragedi Semanggi. Keterlibatan berlanjut dengan mendampingi peziarahan paguyuban keluarga korban demi Indonesia baru tanpa kekerasan. Sebagaimana dituturkan penulis dalam buku Kesucian Politik: Agama dan Politik di tengah Krisis Kemanusiaan (2008), tragedi kemanusiaan 1998 menghidupkan kembali diskusi agama dan politik yang semula sudah dianggap final. Kesucian politik merupakan gugatan terhadap praktik komunitas agama dan politik yang dehumanitatif terhadap korban sebagai ciptaan Allah. Teologi politik merupakan kritik terhadap komunitas agama yang seringkali seringkali lamban, bahkan bungkam terhadap penderitaan korban yang dilakukan rezim politik kriminal.[3] Penulis mengawali pembahasan dengan membaca aksi Kamisan. Kajian politik Indonesia masih mengesampingkan, salah mengerti, dan bahkan belum memahami bahasa keheningan paguyuban. Penulis kemudian membahas keberadaan rezim kriminal yang melalui jejak luka dan kematian korban. Akhir tulisan melihat paras teologi politik pasca-tragedi kemanusiaan 1998.
Keheningan Subversif
Aksi Kamisan tercetus dari perbincangan sederhana orang tua almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan, Sigit Prasetyo, dan Yap Yun Hap. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan paguyuban, mereka menilai kinerja aparat terhadap tragedi kemanusiaan Semanggi. Kasusnya belum mengarah pada kemajuan, apalagi penyelesaian. Ketiganya kemudian menggagas sebuah aksi hening di depan istana presiden untuk menekan lembaga negara agar menuntaskan kasus Semanggi dan melawan pelupaan atasnya. Mereka pada awalnya jauh dari bayangan menyelenggarakan aksi dengan pengerahan massa. Mereka bahkan akan mulai bertiga dengan atribut duka cita dan selebaran kemanusiaan. Mereka kemudian menawarkan aksi kepada keluarga korban lain. Sebagian kesulitan untuk terlibat dalam aksi karena tanggung jawab finansial atau alasan kesehatan. Sebagian bahkan mengundurkan diri dari paguyuban karena capai dengan capaian perjuangan. Kelelahan serupa menimpa pendampingnya. Aksi Kamisan pertama berlangsung pada hari Kamis, 18 Januari 2007 dengan peserta paguyuban keluarga korban tragedi Trisakti-Semanggi I-II, Mei 1998, penculikan aktivis 1997/1998, Tanjung Priok 12 September 1984, Talangsari 7 Februari 1989, 1965, 27 Juli 1996, penggusuran dan Munir.[4]
Paguyuban keluarga korban berdiri hening selama satu jam di depan istana presiden. Selama aksi wakil paguyuban membacakan tuntutan mereka. Keheningan paguyuban barangkali mengejutkan publik karena paguyuban perlu menyuarakan tuntutan mereka secara lantang kepada negara. Publik kemungkinan memahami keheningan sebagai komunikasi tanpa komunikasi. Keheningan sejatinya merupakan salah satu bentuk komunikasi. Ia merupakan komunikasi dengan cara alternatif. Keheningan setara kuasanya dengan komunikasi kata dalam menyampaikan pesan. Publik dapat mengalami transformasi berkat pesan yang disampaikan dalam keheningan. Keheningan menaruh penderitaan dalam rahimnya, menghantarkannya, dan menghadapkan publik dengannya. Keheningan yang komunikatif dapat berupa keheningan diantara kata dan keheningan yang menolak kata. Keheningan yang pertama memandang penting setiap kata berarti demikian pula keheningan diantaranya. Kelemahannya, publik pendengar seringkali kesulitan menangkap pesan secara penuh saat pembicara menyampaikan pesannya.
Paguyuban keluarga korban kadang-kadang memilih keheningan yang menolak kata karena tuturan kata telah mengalami kegagalan menghantar publik pendengar pada transformasi. Kegagalan dapat terjadi karena publik pendengar barangkali menolak untuk mendengarkan pesan pembicara. Kemungkinan lainnya, komunikasi dengan kata macet sebelum pesannya sampai ke telinga publik pendengar. Keheningan yang menolak penggunaan kata seringkali menjadi jalan terakhir bagi paguyuban keluarga korban untuk memberikan kesaksian. Tantangannya bukan dengan bahasa, melainkan dengan absensi bahasa. Keheningan model ini rentan jatuh menjadi kebungkaman. Paguyuban keluarga korban yang bungkam terhadap tragedi mengkhianati korban yang meninggal dunia dan generasi yang hidup. Kebungkaman mereka dapat berarti mengabaikan korban dan menyetujui kriminalitas pelaku terhadap korban.
Dengan segala daya dan upaya, para korban pelanggaran hak asasi manusia telah berjuang dari waktu ke waktu, dari masa ke masa tanpa mengenal lelah. Namun kebenaran dan keadilan itu tak jua menyala, bahkan kian meredup. Segala artikulasi telah diungkap, negara tetap bebal dan bungkam. Di segala kegelapan dan keredupan itu, hari ini kembali korban menerjemahkan artikulasinya dengan segala harap, melalui diam dan berdiri termenung di pusat kekuasaan ini [istana Presiden], bersama segala simbol kedukaan kekelaman hak asasi manusia di negeri ini. Sebab kata tak lagi bermakna, kini! [5]
Paguyuban keluarga korban berperan sebagai penghantar pesan dari korban yang menderita luka atau kematian dini dalam tragedi kemanusiaan. Mereka menjembatani dunia korban dan generasi yang hidup. Kedekatan mereka sebagai keluarga korban memberikan mereka kuasa untuk menyampaikan pesan korban kepada publik pendengar. Paguyuban keluarga korban bertugas menyampaikan pesan mengenai bahaya rezim kriminal kepada generasi yang hidup. Negara pun menjadi pemeluk illah kematian jika meringankan hukuman terhadap pelaku kekerasan, apalagi sengaja melepaskan mereka dari tuntutan hukum. Mereka memiliki harapan akan Indonesia baru tanpa kekerasan. Selain mentransformasikan publik pendengar, mereka juga mengalami transformasi diri. Mereka semula melakukan protes kepada negara atas kematian anak-anak mereka. Mereka kemudian menjadi pembela kehidupan putera-puteri Indonesia. Godaan dalam aksi Kamisan adalah menahlukkan diri pada rezim kriminal karena kehilangan harapan melawan kekuasaan mereka. Selain mendaraskan ratapan mereka kepada negara, mereka juga mendaraskannya kepada Allah kehidupan.[6]
Bahasa tubuh paguyuban yang berdiri di depan istana presiden mengungkapkan kekuatan mereka sebagai subyek politik. Napak tilas terhadap paguyuban keluarga korban memperlihatkan peran transisional dari pekerja kemanusiaan dalam mengayuh roda kehidupan paguyuban. Pekerja kemanusiaan mendorong keluarga korban untuk membentuk paguyuban. Mereka memfasilitasi pertemuan paguyuban dan memberi pembekalan politik dalam pertemuan. Saat berurusan dengan lembaga-lembaga negara dan publik, mereka seringkali berdiri di samping paguyuban, bahkan tampil sebagai juru bicara yang mewakili paguyuban. Paguyuban keluarga korban seringkali menerima bantuan dari pekerja kemanusiaan saat merumuskan tuntutan aksi. Aksi kamisan memunculkan paguyuban sebagai subyek politik baru dan mengembalikan posisi pekerja kemanusiaan sebagai kekuatan pendukungnya. Pelepasan peran transisional ini kadang berujung konflik karena pekerja kemanusiaan berprasangka paguyuban hendak berjalan sendiri tanpa keterlibatan mereka lagi. Paguyuban tampil ke depan karena telah menemukan suara yang sempat menghilang saat tragedi. Mereka kini dapat menyampaikan tuntutan secara langsung kepada negara.
Aksi Kamisan menempatkan paguyuban dalam posisi berhadapan dari muka ke muka dengan aparat negara. Kedekatan ini menyimpan potensi positif bagi paguyuban keluarga korban karena mereka dapat menyuarakan tuntutan mereka dan aparat negara dapat mendengarkan suara mereka. Posisi yang sangat dekat dengan aparat negara sekaligus menyimpan kerentanan berkaitan dengan keselamatan peserta aksi Kamisan. Tindakan represif aparat terhadap aksi akan langsung mengenai peserta aksi. Paguyuban keluarga korban sebelumnya berada dalam posisi relatif aman karena pekerja kemanusiaan menempatkan diri sebagai perisai di samping bahkan di depan mereka. Saat terjadi aksi represif dari aparat terhadap aksi paguyuban, pekerja kemanusiaan memasang badan mereka demi mengelakkan paguyuban keluarga korban dari kekerasan fisik. Aksi Kamisan menyingkap identitas anggota paguyuban dihadapan aparat negara. Jika hendak meneror paguyuban, negara lebih mudah mengarah pada target korbannya.
Peserta aksi Kamisan berdiri hening dengan pandangan terarah ke istana presiden. Paguyuban keluarga korban berdiri sebagai saksi atas kematian anak-anak mereka. Mata mereka yang tertuju ke istana presiden, menyitir Pam Allister, merupakan ‘tindak publik melawan rezim.’ Aksi mereka di depan istana presiden dengan foto-foto korban, aksi simbolik, dan pembacaan pernyataan menjadi aktivitas subversif. Aksi di depan istana presiden merupakan pilihan cerdas paguyuban karena lokasi tersebut menarik perhatian publik dan aparat negara. Aksi Kamisan kadang-kadang membuat gerah rezim kriminal karena mereka mereka kehilangan ruang untuk menyembunyikan diri dan tindakan kriminalnya dari mata paguyuban. Mata paguyuban mengikuti setiap gerakan kriminal mereka. Keputusasaan rezim terhadap aksi Kamisan seringkali diluapkan dengan pembubaran paksa aksi mereka.[7]
Paguyuban keluarga korban merasakan kemendesakan untuk menyampaikan tuntutan kepada negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Sumarsih, ibu dari almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan,
Bagi saya hidup, mati, kebenaran, keadilan, pengampunan hanya ada di tangan Tuhan. Yang saya harapkan pemerintah mengggelar pengadilan hak asasi manusia ad hoc Trisaksi dan Semanggi I - II. Tanpa ada kemauan baik presiden, DPR, pengadilan hak asasi manusia ad hoc, apa pun yang kami lakukan dan apa pun yang kami perjuangkan tidak akan terwujud.[8]
Seruan senada diungkapkan orang tua Sigit Prasetyo. Ia bersama keluarga korban lainnya menyingkapkan sumber kekuatan mereka, yaitu kasih orang tua kepada anak-anaknya. Mengenakan jaket merah dengan tulisan depan ‘Korban Semanggi I dan tulisan belakang ‘Anakku Sigit Prasetyo mati dibunuh TNI bangsaku sendiri di Semanggi,’ bapak Widodo mengungkapkan
Saya dendam benar. Kecewa benar. Sakit hati saya….Terus-terang saya punya semboyan rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kalau nyawa saya masih melekat di raga, saya akan menuntut sampai di ujung dunia.[9]
Paguyuban keluarga korban mengundang masyarakat untuk mengenang korban Semanggi dan korban kekerasan negara lainnya. Saat menuturkan kematian anak-anak mereka pasca-tragedi, sebagian masyarakat memandangnya sebagai tindakan subversif. Sebagian mengalami kengerian dengan tragedi korban dan memilih untuk tutup telinga. Dalam hitungan satu dasawarsa, korban telah menjadi anonim di mata sebagian masyarakat. Perhatian masyarakat sudah beralih ke perkara-perkara kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Paguyuban mengundang masyarakat, meminjam istilah Gesine Schwan, untuk merekatkan ikatan kebersamaan sosial (social communality). Kebersamaan sosial mensyaratkan kita untuk keluar dari kuasa destruktif kebungkaman terhadap tragedi politik. Kita hendaknya menghilangkan sikap lepas bebas negatif, ruang sempit kepentingan diri, kebekuan emosional, dan sebagainya.[10]
Negara Kriminal
Tragedi kemanusiaan Semanggi meninggalkan jejak luka dan kematian pada tubuh korban. Lukman Firdaus, Teddy Wardhani Kusuma, Bernardinus Realino Norma Irmawan, Sigit Prasetyo, Heru Sudibyo, Engkus Kusnadi, Muzammil Joko, Uga Usmana, Abdullah/Donit, Agus Setiana, Budiono, Doni Effendi, Rinanto, Sidik, Kristian Nikijulong, dan Hadi meninggal dunia secara dini dalam tragedi Semanggi I. Yap Yun Hap beserta tujuh warga sipil mengalami kematian dini dalam tragedi Semanggi II.[11] Kita akan melihat ceceran darah semakin banyak jika menyertakan korban luka dalam tragedi kemanusiaan Semanggi. Paguyuban keluarga korban menyingkap wajah kriminal negara pasca-tragedi Semanggi. Orang tua almarhum Sigit Prasetyo mencantumkan tulisan pada makam anaknya, “Dibunuh bangsaku sendiri.” Ayah almarhum juga menulis pesan senada di rumahnya, “Ayah berharap engkau jadi insinyur sayang kamu dibunuh tentara.” Ibunya juga membela almarhum, “Anak saya bukan kriminal!” Ia juga mencari dalang tragedi Semanggi yang merenggut kehidupan puteranya.[12] Masyarakat sebelumnya memandang negara sebagai pelindung kehidupan rakyatnya. Tragedi Semanggi menyentak masyarakat karena negara telah gagal melindungi kehidupan rakyatnya, bahkan aparatnya terlibat dalam pengambilan paksa kehidupan korban. Di mata paguyuban keluarga korban, hanya negara kriminal dapat berbuat demikian.
Negara menolak tuduhan kriminal dalam tragedi kemanusiaan Semanggi. Aparat militer menunaikan panggilan suci untuk menyelamatkan masa depan negara dengan cara mengamankan Sidang Istimewa. Mereka terpaksa menghalau aksi mahasiswa demi melindungi wakil rakyat yang menghadiri Sidang Istimewa. Penghalauan aksi huru-hara melibatkan pasukan sipil pamswakarsa yang sengaja dibentuk untuk menyukseskan Sidang Istimewa. [13] Aparat militer mengambil alih posisi pamswakarsa di depan saat menghalau aksi mahasiswa dalam tragedi Semanggi. Mereka mengakui bentrokan yang menyerupai perang melawan mahasiswa. Mereka bahkan mengakui fakta aparat yang melakukan tembakan pada demonstran. Aparat militer mensinyalir penggunaan peluru tajam sebagai aksi susupan dari pihak ketiga yang sengaja hendak menjadikan mahasiswa sebagai korban dan menggagalkan sidang istimewa. Mereka juga mensinyalir kelompok anarkis menyusup dalam gerakan mahasiswa dengan agenda menciptakan kekacauan sosial.
Aparat militer meminta publik untuk membaca kekerasan yang terpaksa dilakukannya secara arif. Kekerasan merupakan jalan terakhir setelah negosiasi damai menemui jalan buntu. Kekerasan dalam tragedi Semanggi merupakan pertahanan defensif, bukan kekerasan pro-aktif. Aparat hanya memiliki pilihan tunggal kekerasan (lack-of-choice justification) karena mahasiswa bersikeras bergerak menuju gedung DPR/MPR untuk menggagalkan sidang istimewa. Aparat militer berhasil mengembalikan ketertiban umum melalui kekerasan terbatas dengan jumlah korban mininal. Mahasiswa yang berhasil menyelamatkan kehidupan meneriakkan “anjing” dan “pembunuh” kepada aparat militer. Negara menolak dakwaan paguyuban bahwa tragedi Semanggi sebagai serangan langsung terhadap kehidupan korban. Aparat negara mengingatkan paguyuban korban untuk menghindari eksploitasi penderitaan, apalagi menganggap tragedi Semanggi sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Mereka juga menolak dakwaan sebagai pelindung terhadap dalang tragedi dengan hanya mengajukan ke meja hijau beberapa prajuritnya. DPR periode 1999 – 2005 menyatakan tragedi Trisakti dan Semanggi bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Badan musyawarah DPR telah dua kali melakukan veto terhadap rekomendasi dari Komisi III DPR untuk menggelar pengadilan hak asasi manusia ad hoc.
Penulisan kisah tragedi Semanggi masih jauh dari kata final. Ahli sejarah mengakui keterbatasan mereka dalam menangkap peristiwa. Mereka dengan rendah hati menyadari bahwa mereka hanya menangkap jejak peristiwa. Sejarah merupakan pengetahuan yang telah mengalami penyuntingan (mutilated knowledge). Ia merupakan pengetahuan melalui dokumen yang bertujuan mencari kebenaran.[14] Kisah resmi negara mengenai tragedi Semanggi cenderung menyingkirkan, bahkan menghapus kenangan sejarah korban di masa lalu. Peringatan akan tragedi, menyitir Vera Schwarcz, menyingkap sebagian kenangan sejarah di tengah propaganda rezim politik untuk melupakannya (enforced amnesia).[15] Kisah mengenai tragedi politik yang sama mengalami keragaman karena pihak-pihak yang berkepentingan, menyitir Jeffrey N. Wasserstrom, menciptakan mitos sejarah (mythologize history).[16] Ignacio Martín – Baró, seorang imam Yesuit yang menjadi martir politik di bawah rezim militer kriminal El Salvador, memerikan negara yang menciptakan kisah resmi terhadap tragedi kemanusiaan untuk membohongi publik.
Objeknya adalah menciptakan versi resmi terhadap fakta, kisah resmi yang mengabaikan aspek-aspek penting dari realitas, menciutkan yang lain, dah bahkan mempersalahkan atau mereka-reka yang lain. Kisah resmi dijejalkan kepada publik dengan propagranda yang sangat intensif dan agresif, yang bahkan dengan beking jabatan-jabatan resmi tertinggi.... Saat, entah karena sesuatu alasan, fakta-fakta yang bertentangan dengan kisah resmi muncul, mereka langsung dilibas.... Pernyataan-pernyataan publik tentang realitas bangsa, laporan pelanggaran hak asasi manusia, dan pembongkaran terhadap penciptaan kisah resmi, kebohongan institusional, dipandang sebagai aktivitas subversif.[17]
Paguyuban keluarga korban menyadari kemungkinan distorsi dalam menyampaikan kebenaran mengenai tragedi. Namun mereka menolak kisah resmi negara yang menempatkan korban sebagai kriminal. Mereka melangsungkan perlawanan gerilya dengan mengisahkan dan menuliskan kisah korban. Usaha senada dibuat mereka yang berpaut dekat dengan tragedi Semanggi. Kenangan publik, sebagaimana diungkapkan Claudia Koonz, merupakan medan peperangan antara ingatan kerakyatan dan dan ingatan resmi demi hegemoni.[18] Mereka menggugat ideologi keamanan nasional yang di(salah)gunakan aparat militer untuk membenarkan pembubaran aksi mahasiswa dengan kekerasan senjata. Mereka membangun jaringan dengan paguyuban keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia lain. Arah perjuangan mereka meluas dari mencari keadilan untuk anak-anak mereka yang meninggal karena kekerasan negara ke menciptakan Indonesia baru tanpa kekerasan. Ibu Sumarsih, salah seorang peserta aksi Kamisan, bertutur
Kami (Jaringan Solidaritas Keluarga Korban) melakukan sosialisasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat ini ke pelosok-pelosok pedesaan sampai ke tingkat internasional. Kami akan bercerita bahwa di Indonesia ada kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965, penculikan, peristiwa Tanjung Priok, Semanggi I – II, Trisakti dan sebagainya.[19]
Paguyuban keluarga korban menciptakan ruang perjumpaan dengan negara. Saat negara menyerahkan uang belasungkawa, keluarga menghargai itikad baiknya namun mengembalikannya dengan sopan. Mereka menolak uang dijadikan penebus kehidupan anak mereka. uang belasungkawa berarti jika diberikan sebagai bagian dari pengakuan akan kesalahan negara dalam tragedi. Permintaan maaf secara verbal dari negara penting bagi paguyuban keluarga korban, namun belum mencukupi. Negara hendaknya menunjukkan wajah manusiawinya sebagai tanda pertobatan sejati dalam waktu relatif dekat.[20]
Keberhasilan sebuah rezim dalam penegakan hak asasi manusia, bukan diukur dengan keberhasilan melupakan, mengabaikan, mengingkari, atau pun mengubur kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu atau di masa kini, melainkan sebaliknya yaitu harus diukur dengan keberanian dan keberhasilan menuntaskan kasus-kasus pelanggan hak asasi manusia pada masa lalu dan masa-masa berikutnya. [21]
Usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau sejenisnya, menyitir Hendardi, hendaknya jangan justru menjadi lembaga permaafan bagi pelaku.[22] Rekonsiliasi mensyaratkan keberadaan pelaku yang merenggut kehidupan korban dan korbannya. Paguyuban keluarga korban mengalami kesulitan untuk memberikan pengampunan jika pelaku berdiri dihadapan korbannya tanpa rasa sesal atas kriminalitas yang telah dibuatnya. Rekonsiliasi hendaknya jangan pernah dieksploitasi untuk memutihkan kasus dan membersihkan tangan berdarah pelakunya. Undangan rekonsiliasi juga akan berakhir sia-sia jika yang hadir ternyata justru orang-orang lain yang dipaksa bermain peran sebagai pelaku. Paguyuban hendaknya juga bersedia menyingkirkan kemarahan dan bahkan kebencian terhadap pelaku. Rekonsiliasi sejati, menyitir Desmond Tutu, membebaskan mereka dari status korban dan sikap tergantung pada pelaku kekerasan. Ia mengembalikan lagi martabat keduanya sebagai manusia.
Berteologi dari Golgotha
Johann Baptist Metz, salah satu peletak dasar teologi politik, melihat kemungkinan dialog baru antara teologi dan politik. Metz melihat kecenderungan teolog yang membiarkan pengillahan politik (political idolatry). Ia melihat panggilan teolog kristiani untuk terlibat dalam membebaskan politik dari berhala totalitarianisme. Dihadapan rezim politik totaliter yang menghancurkan kenangan penderitaan korban, teolog mengembalikan kenangan penderitaan sebagai tradisi subversif. Mereka menjadi rekan politikus sehingga politikus dapat menunaikan tugasnya mewujudkan emansipasi atau kebebasan. Sebaliknya politikus mengingatkan teolog yang seringkali kebal terhadap sentuhan penderitaan korban. Mereka menggedor pintu kamar teolog yang mengunci diri untuk memikirkan subyek manusia. Mereka mengajak teolog untuk keluar menyaksikan subyek yang manusia yang ditulisnya sebagian menjadi korban politik dan sebagian yang lain menggagahi kemanusiaan korbannya. Politikus menjadi rekan bagi teolog untuk menunaikan tugasnya mengkonkritkan penebusan manusia di dunia.[23]
Tragedi kemanusiaan 1998 menghidupkan kembali pertautan agama dan politik yang semula sudah dianggap final. Pertautannya melewati pencarian garis batas antara menjadi warga gereja dan Indonesia (faithful citizenship). Perhatian Gereja Katolik juga melampaui pencarian afiliasi dan representasi politik, bahkan sikap politiknya terhadap rezim penguasa. Pengadilan terhadap Romo Ignatius Sandyawan Sumardi, S.J. memotret pergumulan kontemporer dari Gereja, terutama pejabatnya, yang tarik menarik antara politik hati nurani dan politik negara. Tragedi kemanusiaan 1998 mengubah wajah Gereja Katolik. Korban memasuki pelataran gereja, sebagian pejabat gereja turun dari altar untuk menyambut mereka, mahasiswa-mahasiswi Katolik turun ke jalan, dan sebagian warga Gereja menyingsingkan baju sebagai relawan-relawati kemanusiaan. Kita melihat wajah duka keluarga yang rumahnya dirusak dan usaha ekonominya dikuras massa. Kita mendengar ratapan mereka yang anggota keluarganya hilang, terluka, diperkosa, dan meninggal dunia. Korban menanyakan keterlibatan Gereja yang memeluk Allah kehidupan di tengah negara kriminal. Gereja yang bersekutu dengan rezim kriminal menyembah illah kematian. Sebaliknya Gereja yang memeluk Allah kehidupan membela korban dari ancaman pengambilan paksa kehidupannya oleh rezim kriminal. Kesucian politik merupakan kosa kata baru dari pertautan agama dan politik dalam krisis kemanusiaan 1998.
Paguyuban keluarga korban bersimpuh dihadirat Allah untuk mencerna tragedi kemanusiaan yang merenggut kehidupan anak-anak mereka. Kawasan Semanggi, makam, rumah, dan tempat ibadah menjadi tempat-tempat utama bagi mereka untuk mencari sebab kematian dini anak mereka. Saat berdoa di makam puteranya, Ibu Sumarsih mendaraskan doa
Bapa ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Engkaulah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kami. Bapa terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapa kini hanya doa yang selalu kami panjatkan kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan anakku. Juga para pejuang demokrasi yang lainnya Yap Yun Hap, Sigit Prasetyo, Engkus Kusnaedi, Heru Sudibyo, Muzamil Joko, dan masih banyak lainnya.”[24]
Sebagian masyarakat menganjurkan keluarga korban untuk melihat kematian anak mereka sebagai takdir Allah dan menerimanya dengan ikhlas. Ada pula yang menghibur orangtua korban dengan penghakiman illahi terhadap pelaku. Allah akan menindak sendiri pelakunya jika pengadilan manusia gagal menghukum penjahat kemanusiaan. Paguyuban korban mengakui kuasa Allah atas kehidupan manusia. Mereka akan memberikan anak mereka jika Allah menghendakinya demikian. Namun, mereka menyangsikan pengambilan paksa kehidupan anak mereka dengan senjata sebagai kehendak Allah. Pelaku pembunuhan justru menggagahi Allah dengan merenggut paksa kehidupan ciptaan-Nya. Nasehat untuk menerima kematian anak mereka secara ikhlas melukai hati keluarga korban dan menghujat Allah. Komunitas agama menyadari bahwa rezim kriminal seringkali menyalahgunakan bahasa agama dengan mendakwa Allah sebagai kambing hitam atas kematian dini korban, dan mencuci tangan mereka yang berlumuran darah.
Tempat ibadat menempati posisi istimewa bagi paguyuban keluarga korban dalam perjuangan meraih keadilan korban. Paguyuban berjumpa dengan Allah yang berduka bersama mereka dan menghibur mereka. Allah mendorong mereka untuk menuntut keadilan hukum bagi anak-anak mereka. Gereja memberikan tanggapan beragam terhadap tragedi Semanggi. Keragaman tanggapan Gereja bersumber dari pandangannya tentang negara dan paguyuban keluarga korban. Sebagian pejabat Gereja memandang tragedi Semanggi masih menyimpan kontroversi. Mereka cenderung meminta komunitasnya untuk melakukan acara bersama paguyuban sebagai aktivitas diluar gereja. Beberapa aktivis gereja menyediakan forum bagi paguyuban untuk menyampaikan kesaksian. Gereja tarik menarik antara memperhatikan kepentingan umatnya dan kepentingan lintas lokalitas eklesial. Ia juga lebih berbicara mengenai perkara-perkara yang berdampak langsung pada kehidupan umatnya. Perkara ekonomi dan ekologi lebih sering menjadi perbincangan di mimbar gereja daripada perkara politik.
Teologi politik Indonesia menempatkan korban tragedi kemanusiaan yang berada di tepian masyarakat dan gereja dalam pusat perhatiannya. Korban politik merupakan paras konkrit dari subyek. Teologi politik mengingatkan gereja akan penghujatan Allah baik oleh komunitas agama maupun rezim kriminal. Teolog politik menangkap keberadaan illah religius dan sekular. Jon Sobrino memperluas konsep illah yang semula digunakan terbatas dalam ruang agama ke ruang sekular. Absolutisme kekayaan, kekerasan, dan keamanan nasional merupakan nama beberapa illah sekular. Illah religius dan sekular mendaku klaim absolut dan keduanya menelan korban. [25] Teolog politik Indonesia menjauhkan diri dari godaan untuk membatasi pembicaraan pada illah religius. Illah sekuler seringkali jauh lebih berbahaya daripada illah religius. Dalam tragedi kemanusiaan Semanggi, kita menyaksikan pengillahan politik dan illah keamanan nasional yang mencederai dan merenggut kehidupan korban secara paksa.
Teolog politik kemanusiaan membaca kisah Yesus dalam kitab suci secara baru.[26] Ia peduli dengan pribadi-pribadi yang menjumpai atau dijumpai Yesus. Ia juga berpaling pada pribadi-pribadi yang tak bersuara dalam kitab suci, namun juga mengalami penderitaan. Rezim kriminal membantai anak-anak di Bethelem dan sekitarnya dalam rentang usia bayi Yesus. Pembantaian membabi-buta berlangsung karena mereka memandang anak-anak tersebut sebagai ancaman politik. Penulis Injil mengungkapkan kesulitan untuk menggambarkan penderitaan orang tua dengan kematian anak-anaknya. Ia mencari referensi untuk membahasakan kedalaman penderitaan orang tua korban. Ia mengutip kitab Yeremia “Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang sangat sedih; Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.”[27] Meskipun Yesus selamat dari ancaman kematian rezim Herodes, orang tuanya tetap mencemaskan keselamatannya. Pergantian rezim politik dari Herodes kepada anaknya Arkhelaus sama sekali belum memberikan jaminan aman bagi kehidupan Yesus. Orang tuanya memang meninggalkan Mesir, namun mencari tempat tinggal yang jauh dari pengawasan rezim kriminal.[28]
Pengarang Injil Lukas menampilkan latar rezim agama dan politik dari pewartaan Yohanes mengenai pengampunan.
Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waku Hanas dan Kayafas menjadi Imam Besar.[29]
Yohanes memanggil orang yang berkerumun kerumunan secara berani sebagai keturunan ular beludak. Ia menegur prajurit untuk menghindari perampasan dan pemerasan demi melipatgandakan gaji mereka. Raja Herodes juga mendapat tegoran darinya karena mengambil istri saudaranya dan karena kejahatan lainnya. Ia menanggapi tegoran dengan memenjarakan Yohanes dan kemudian memancung kepalanya.[30]
Yesus mengajukan kritik terhadap praktek penarikan pajak dari negara yang membebani bahu rakyat. [31] Pemungut cukai menjadi kelompok sosial yang dibenci rakyat karena merupakan kepanjangan tangan rezim politik yang memeras kehidupan rakat dan memperkaya diri dengan menagih pajak melebihi ketentuan. Pejabat agama menggunakan isu membayar pajak untuk menjerat Yesus dihadapan pejabat negara. Mereka menggali lubang jebakan kepada Yesus dengan pilihan ekstrem mengabdi Allah atau Kaisar. Dalam skenario mereka, Yesus akan terbukti bersalah seandainya Ia memilih menjatuhkan pilihan kepada Allah. Sebaliknya seandainya memilih tunduk pada Kaisar, Yesus akan kehilangan wajah dihadapan rakyat. Yesus keluar dari jebakan dengan kritik ganda baik kepada pejabat negara yang diwakili orang-orang Herodian dan pejabat agama. Yesus berbicara kepada para pendengarnya mengenai sebuah rezim politik yang mengadi Allah dan melayani rakyatnya.[32] Pada kesempatan lain, Ia mewanti-wanti para murid-Nya untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang pejabat agama dan Herodes.[33]
Meskipun hidup di bawah rezim politik kriminal, Yesus menjauhkan diri dari memukul rata semua aparat rezim sebagai jahat. Ia menyediakan diri untuk menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Perwira itu mengasihi hambanya dan mengundang Yesus untuk menyembuhkannya. Ia juga mengasihi warga dan mendukung hidup keagamaan warga dengan menanggung pembangunan tempat ibadat mereka.[34] Penginjil juga menyebut Yohana, isteri Khuza bendahara Herodes, sebagai salah satu perempuan yang mendukung pelayanan Yesus.[35] Yesus tanpa takut menyebut Herodes sebagai serigala.[36] Ia mengajukan kritik terhadap penguasa yang memiliki kepentingan disebut pelindung dan menekankan tugas utama mereka sebagai pelayan rakyat.[37]
Saat ditangkap, Yesus menolak sangkaan sebagai penyamun. Imam-imam kepala dan Mahkamah Agama, sebagai representasi pejabat agama, menuduh Yesus dihadapan pengadilan agama dengan kesaksian palsu. Pengarang Injil menunjukkan ironi dengan menyatakan bahwa kesaksian mereka bertentangan satu sama lain. Pengadilan agama mempersalahkan Yesus sebagai penghujat Allah karena mengklaim diri sebagai Mesias.[38] Mereka kemudian menyerahkan Yesus kepada Pilatus dengan tuduhan menyesatkan rakyat. Pilatus gagal menangkap Yesus sebagai saksi kebenaran. Ia bahkan mempertanyakan pemahaman Yesus mengenai kebenaran. Yesus memahami kebenaran Politik yang dianutnya jauh dari nilai kebenaran. Ia menggadaikan kebenaran demi menyelamatkan karir politiknya.[39] Pengadilan Yesus menyingkap pertarungan antara dua posisi politik dan teologi. Marcus J. Borg menyatakan,
Politik bela rasa Yesus berseberangan dengan teologi elit, yaitu politik kesalehan dan kemurnian yang berpusat di kenisah dan memberikan legitimasi pada tatanan bersama yang ada.... Politik dan teologi elit menempatkan rakyat di bawah kaki penguasa.... Kerajaan Allah memiliki nuansa teo-politik. Para pendengar Yesus mengetahui kekuasaan Herodes atau Kaisar. Allah mengajukan paradigma baru dalam memerintah umat-Nya.[40]
Saat memanggul salib ke golgotha, Yesus bersua dengan perempuan yang menangisi dan meratapi-Nya. Mereka berjumpa dan berdialog intim sebagai pribadi yang mengalami penderitaan di bawah rezim agama dan politik kriminal. Yesus menghargai bela rasa yang ditunjukkan perempuan terhadap penderitaan-Nya. Di tengah penderitaan sebagai perempuan, mereka masih dapat berbela rasa dengan penderitaan Yesus. Mereka membawa serta pula penderitaan anak-anak dan pribadi-pribadi lain yang dekat dengan kehidupan mereka. Yesus mendorong perempuan mengingat penderitaan mereka dan anak-anaknya. Ia menangkap penderitaan yang dialami perempuan dan menyingkapkannya kepada kita. Dalam penderitaan salib, Ia menunjukkan bela rasa terhadap penderitaan orang yang mengikuti jalan salib-Nya. Perempuan menjadi saksi atas kriminalitas rezim yang menghukum korban tanpa kesalahan dengan memandang penyaliban Yesus. Kriminalitas rezim terpampang telanjang melalui tubuh Yesus yang dipaku di salib.[41]
Penutup
Kita memperingati tragedi Semanggi untuk menuntut keadilan bagi korban dan mendorong ke arah Indonesia baru tanpa kekerasan. Keadilan korban masih jauh dari rengkuhan paguyuban. Sebagian masyarakat belum menangkap pesan kemanusiaan demi Indonesia baru tanpa kekerasan. Paguyuban keluarga korban Semanggi yang bergabung dalam aksi Kamisan meneriakkan pesan kemanusiaan mereka kepada negara dalam keheningan. Paguyuban keluarga korban membopong tubuh korban, mengangkat fotonya, dan mencari pelaku yang merenggut kehidupan korban. Mereka menolak rezim kriminal yang mengillahkan politik dan menggagahi korban. Rezim kriminal membungkam kesaksian paguyuban dan menghapus kenangan atas korban dengan memutarbalikkan kebenaran. Paguyuban keluarga korban mengundang komunitas agama untuk berbela rasa dengan korban politik. Di mata penulis sebagai teolog politik Katolik, rezim kriminal merenggut kesucian politik. Teolog politik hendaknya mendorong komunitas agama untuk berpaling kepada korban politik dan melawan rezim kriminal yang mencederai kemanusiaan korban (SELESAI)
[1] Sun Ai Park, ‘the Wish’ dalam Doing Theology in a Divided World, 173.
[2] Sebagian besar tulisan mengenai peristiwa Semanggi berfokus pada tindakan aparat militer menembaki gerakan mahasiswa yang mencederai dan merenggut kematian korban. pada tanggal
[3] Mutiara Andalas, ‘Kesucian Politik’ dalam rubrik opini harian KOMPAS, Selasa, 13 Mei 2008.
[4] Untuk informasi lebih lanjut mengenai masing-masing tragedi kemanusiaan dari perspektif paguyuban keluarga korban, silakan berkunjung ke http://www.kontras.org/
[5] Surat Terbuka Jaringan Solidaritas Keluarga Korban kepada Negara pada tanggal 18 Januari 2007.
[6] Gagasan Elie Wiesel mengenai keheningan diantara kata dan keheningan yang menolak kata membantu penulis dalam memahami aksi hening paguyuban keluarga korban. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai perkara ini, silakan lihat Robert McAfee Brown, Elie Wiesel: Messenger to All Humanity (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1983), 30 – 36.
[7] Pam Allister membuat sebuah ulasan bernas dan cerdas mengenai aksi Ibu Plaza de Mayo di
[8] Dokumentasi Audio – Visual TV 7 “Saksi Hidup Tragedi Semanggi 1998.”
[9] Dokumentasi Audio-Visual oleh Aliansi Korban Kekerasan Negara ‘Perjuangan Tanpa Akhir Menggapai Keadilan: Tragedi Trisakti, Semanggi I & II (2005).
[10] Gesine Schwan, Politics and Guilt: The Destructive Power of Silence, translated by Thomas Dunlop (
[11] Selain mengingat korban meninggal dalam tragedi kemanusiaan Semanggi II di Jakarta, kita perlu mengingat pula korban-korban meninggal lain dalam waktu yang berdekatan yang menolak Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB). Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah meninggal dalam aksi mahasiswa di Lampung pada tanggal 28 September 1999 di depan Koramil Kedaton. Meyer Ardiansyah meninggal dalam aksi mahasiswa di Palembang pada tanggal 5 Oktober 1999 di depan Markas Kodam II/Sriwijaya.
[12] Dokumentasi Audio – Visual TV 7 “Saksi Hidup Tragedi Semanggi 1998.”
[13] Mayjen (Purn) Kivlan Zein mengusulkan agar negara memberikan penghargaan kepada pamswakarsa yang menjadi korban saat menunaikan tugas dalam menyelamatkan sidang istimewa.
[14] Paul Veyne, Writing History: Essay on Epistemology, Translated by Mina Moore – Rinvolucri (Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1984), 3 – 14.
[15] Vera Schwarcz, ‘Memory and Commemoration: The Chinese Search for a Livable Past’ dalam Popular Protest & Political Culture in Modern China, edited by Jeffrey N. Wasserstrom & Elizabeth J. Perry, Second Edition (Oxford: Westview Press, 1994), 183.
[16] Jeffrey N. Wasserstrom, ‘History, Myth, and the Tales of Tiananmen,’ dalam Popular Protest & Political Culture in Modern China, 274.
[17] Ignacio Martín – Baró, ‘Political Violence and War as Causes of Psychological Trauma in El Salvador,’ International Journal of Mental Health 18 (1989), 10 – 11, sebagaimana dikutip dari Rita Arditti, Searching for Life, The Grandmothers of the Plaza de Mayo and the Disappeared Children of Argentina (Berkeley, CA: The University of California Press, 1999), 84.
[18] Claudia Koonz, ‘Between Memory and Oblivion: Concentration Camps in German Memory’ dalam Commemoration: The Politics of National Identity, Edited by John R. Gillis (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 261.
[19] Dokumentasi Audio – Visual TV 7 “Saksi Hidup Tragedi Semanggi 1998.”
[20] Giorgio Calcagno, ‘The Drowned and the Saved,’ dalam The Voice of Memory Primo Levi, 109 – 113.
[21] Surat Terbuka Jaringan Solidaritas Keluarga Korban kepada Negara pada tanggal 18 Januari 2007.
[22] Dokumentasi Audio-Visual oleh Aliansi Korban Kekerasan Negara ‘Perjuangan Tanpa Akhir Menggapai Keadilan: Tragedi Trisakti, Semanggi I & II (2005).
[23] Johann Baptist
[24] Dokumentasi Audio-Visual oleh Aliansi Korban Kekerasan Negara ‘Perjuangan Tanpa Akhir Menggapai Keadilan: Tragedi Trisakti, Semanggi I & II (2005).
[25] Jon Sobrino, Where is God? Earthquake, Terrorism, Barbarity, and Hope, translated by Margareth Wilde (
[26] Penulis berhutang budi kepada teolog Johann Baptist Metz, Jon Sobrino, dan Ivonne Gebara untuk melihat penderitaan Yesus dan korban illah kematian dalam kitab suci.
[27] Matius 2, 16 – 18.
[28] Matius 2, 19 – 23.
[29] Lukas 3, 1 – 3.
[30] Lukas 3, 14. 19 – 20.
[31] Matius 16, 24 – 27.
[32] Matius 22, 15 – 22; Markus 22, 15 – 22; Lukas 20, 20 – 26.
[33] Matius 16, 6; Markus 8, 15.
[34] Lukas 7, 1 – 10.
[35] Lukas 8, 3.
[36] Lukas 13, 42.
[37] Lukas 22, 25 – 26.
[38] Matius 26, 47 – 68; Markus 14, 43 – 65; Lukas 22, 47 – 54; Yohanes 18, 1 – 14. 19 – 24.
[39] Yohanes 18, 37 – 38a.
[40] Marcus J. Borg, The God We Never Knew: Beyond Dogmatic Religion to a More Authentic Contemporary Faith (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1997), 143 – 144.
[41] Lukas 23, 27 – 28. 49.

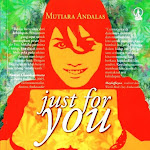
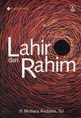




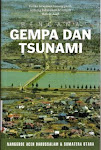












No comments:
Post a Comment